Nah, pendidikan harus jadi jembatan. Caranya? Melalui tiga pilar. Pertama, Eco-literacy: setiap orang paham bahwa keputusan ekonomi punya dampak biologis. Kedua, Etika Bisnis Hijau: beralih dari mindset profit semata ke triple bottom line (People, Planet, Profit). Ketiga, Inovasi Teknologi: menciptakan tenaga kerja yang mahir mengelola ekonomi sirkular, di mana limbah bukan sampah, melainkan bahan baku baru.
Mimpi tentang Ekonomi yang Berputar
Model ekonomi linear "ambil-buat-buang" sudah jelas usang. Banyak pakar, seperti dari Ellen MacArthur Foundation, mendorong transisi ke ekonomi sirkular. Di Indonesia, transisi ini butuh keberanian politik.
Kebijakan harus memberi insentif bagi perusahaan yang beroperasi dengan limbah minimal. Di sisi lain, kebijakan ekologi tak boleh cuma melarang. Ia harus memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk hidup sejahtera dari alam yang mereka jaga inilah inti ekonomi regeneratif.
Belajar dari Bencana
Lihatlah peta bencana belakangan ini. Daerah dengan deforestasi tinggi hampir selalu jadi yang paling rentan banjir dan longsor. Ini bukan kebetulan. Ini data empiris yang harusnya mempertemukan Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup di meja yang sama.
Pendidikan di wilayah rawan bencana juga perlu diubah. Bukan cuma soal cara menyelamatkan diri saat air bah datang, tapi juga pemahaman mengapa banjir itu bisa terjadi. Bagaimana partisipasi warga menjaga daerah aliran sungai justru bisa menyelamatkan ekonomi mereka sendiri.
Jawa Barat dan Upaya Menemukan Kembali Keseimbangan
Di tingkat daerah, Jawa Barat menunjukkan betapa gentingnya masalah ini. Dengan tutupan hutan yang tersisa sekitar 20 persen, langkah radikal diambil. Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, memberlakukan moratorium penebangan pohon di kawasan berisiko tinggi.
Tapi KDM sadar, kebijakan fisik tak akan cukup tanpa revolusi kesadaran. Di sinilah program Panca Waluya hadir sebagai instrumen pendidikan karakter. Ia bukan sekadar kurikulum, tapi upaya mengembalikan jati diri manusia yang sadar lingkungan.
Melalui nilai Waluya Jasmani dan Rohani, siswa diajari bahwa kesehatan mereka fisik dan mental bergantung pada kesehatan alam. Menanamkan rasa hormat pada tanah dan air sejak dini adalah kunci. Kebijakan ekologi harus berakar kuat di kesadaran masyarakat.
Keselarasan ini diperkuat dengan kebijakan tata ruang yang kaku, tak bisa ditawar untuk investasi semata. Penutupan tambang bermasalah dan pembatasan bangunan di area resapan air adalah langkah nyata untuk menyeimbangkan kembali alam yang sudah oleng.
Bencana yang datang silih berganti adalah pesan keras: "bisnis seperti biasa" sudah tamat. Kita tak bisa terus membangun pencakar langit di atas tanah yang amblas.
Pada akhirnya, ekonomi adalah anak dari ekologi. Jika sang ibu alam sakit, anak itu tak akan pernah tumbuh sehat. Pendidikan adalah kesempatan terakhir kita untuk memperbaiki pola pikir generasi mendatang, agar mereka tak mengulangi kesalahan yang sama.
Sudah waktunya berhenti bertaruh dengan masa depan. Mari berinvestasi pada keberlanjutan. Sebab, satu hal yang pasti: tidak ada pertumbuhan ekonomi di planet yang mati.






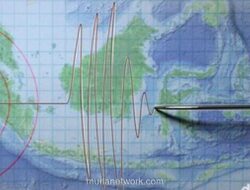




Artikel Terkait
Di Balik Senyum Kampus: Saat Kekuatan Lahir dari Keberanian untuk Lelah
Rindu yang Tertinggal di Stasiun Bandung
Tembak-Menembak di Yahukimo, Sopir Pikap Nyaris Jadi Sasaran
AS dan Iran Siap Berunding di Istanbul di Tengah Ketegangan yang Meningkat