“Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah hadits hasan)
Nabi bukan cuma imam shalat. Beliau adalah kepala negara, panglima perang, hakim, pemimpin politik umat. Al-Qur’an pun memerintahkan dengan gamblang: “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan…” (QS. Al-Baqarah: 208).
Lalu, sejak kapan politik dikeluarkan dari Islam yang kaaffah itu? Yang terjadi, makna politik sengaja dipelintir. Selalu dicitrakan kotor, pragmatis, penuh intrik. Padahal dalam khazanah Islam, politik adalah siyasah: seni mengatur urusan umat agar keadilan tegak dan kezaliman dicegah.
Jadi, ketika sebuah khutbah membahas kezaliman penguasa, perampasan tanah, atau hukum yang tumpul ke atas, lalu langsung dicap “politik praktis”, itu sejatinya adalah cara membungkam. Masjid sengaja dijauhkan dari realitas umat. Jamaah disibukkan dengan ritual, tapi dibuat tuli terhadap jeritan sosial. Islam direduksi jadi agama privat, bukan sistem hidup. Ini proyek lama musuh-musuh Islam. Memisahkannya dari kekuasaan, dari hukum. Tujuannya cuma satu: agar ia jinak, tak lagi mengganggu status quo, tak lagi mengancam kekuasaan yang zalim.
Warisan yang Tak Kunjung Usai
Sejarah kita punya catatan kelam. Dulu, kolonialisme Barat tak pernah melarang shalat. Mereka “hanya” melarang jihad. Mereka tidak memusuhi bangunan masjid, tapi mereka memusuhi masjid sebagai pusat peradaban dan perlawanan.
Sekarang, pola itu terulang dengan cara yang lebih halus. Bukan dengan larangan terang-terangan, melainkan lewat regulasi, “kesepakatan pengurus”, atau jargon “menjaga persatuan”. Padahal, yang seringkali dijaga adalah kenyamanan penguasa, bukan kebenaran Islam.
Lantas, apa yang bisa dilakukan?
Pertama, pengurus masjid harus ingat kembali fungsi aslinya. Masjid adalah pusat peradaban umat. Ia milik jamaah, bukan perpanjangan tangan kekuasaan. Ia seharusnya jadi benteng moral masyarakat.
Kedua, kita harus jujur membedakan antara politik praktis partisan dengan politik nilai. Mengkritik kezaliman, membela yang tertindas, itu bukan kampanye partai. Itu inti dari dakwah Islam itu sendiri.
Ketiga, para dai dan khatib jangan mudah menyerah. Jika satu pintu masjid tertutup, selalu ada mimbar lain. Sejarah membuktikan, menyampaikan kebenaran tak pernah bergantung pada izin siapapun.
Terakhir, jamaah harus kritis. Jika masjid mulai alergi membahas isu-isu umat, tak ada salahnya kita bertanya: sebenarnya, masjid ini sedang melayani siapa?
Islam tidak lahir untuk jadi agama pelengkap penderita. Ia hadir untuk membebaskan. Jika masjid ikut-ikutan mempreteli Islam dari dimensi politiknya, jangan heran bila umat kehilangan arah dan kezaliman merajalela. Masjid yang takut pada kebenaran, pada akhirnya hanya akan melahirkan umat yang takut melawan kezaliman.
Jakarta, 10 Januari 2026









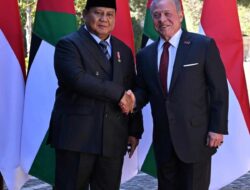

Artikel Terkait
Ramadan, Tradisi Ziarah ke Makam Ulama dan Tokoh Sejarah di Sulawesi Selatan
BMKG Prakirakan Hujan Seharian di Makassar dan Sekitarnya pada Kamis
Mudik Gratis Jakarta 2026 Dibuka untuk Warga Non-DKI, Pendaftaran Dikelompokkan Berdasarkan Tujuan
Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Wafat di Jakarta