Ambil satu ilustrasi. Ketika seorang warga biasa, yang berusaha melindungi keluarganya dari ancaman, malah berhadapan dengan proses hukum yang terasa tidak proporsional, publik membaca itu sebagai pembalikan rasa adil. Mereka melihatnya jelas.
Ini bukan tuntutan untuk membiarkan pelanggaran. Ini tuntutan agar nalar hukum ditegakkan: pertimbangkan konteks, proporsionalitas, kehati-hatian, dan kebijaksanaan. Hukum yang mekanis dan kaku tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan ketakutan, bukan kepastian.
Karena itulah, kritik publik tidak bisa dijawab dengan simbol atau retorika kerendahan hati semata. Keadilan yang gagal di level paling nyata menuntut perbaikan yang sama nyatanya: peningkatan kualitas penyidikan, supervisi yang sungguh-sungguh, keberanian pimpinan untuk mengoreksi anak buah, dan komitmen untuk menempatkan keadilan sebagai roh penegakan hukum. Tanpa itu, pernyataan paling elok sekalipun akan terdengar hampa.
Memang, krisis kepercayaan hampir selalu diiringi dinamika politik. Saat kritik mengeras, yang sering bergerak lebih cepat adalah upaya konsolidasi legitimasi. Dari sudut pandang manajerial, hal ini bisa dipahami.
Tapi masalah muncul ketika legitimasi dirawat lebih giat daripada kinerja itu sendiri yang dibenahi. Publik bisa membaca sinyal ini. Stabilitas yang dibangun di atas narasi tanpa koreksi, pada akhirnya, hanyalah stabilitas semu.
Ada paradoks lain yang mengemuka. Lembaga perwakilan kita, yang punya fungsi pengawasan, di momen-momen tertentu bisa terbaca lebih sibuk menjaga stabilitas institusional ketimbang menyuarakan kegelisahan rakyat yang diwakilinya.
Jadinya, ketika tuntutan perbaikan bergema keras di luar, sementara di dalam justru terdengar gemuruh peneguhan dukungan, pesan yang sampai ke masyarakat menjadi rancu. Politik memang bagian dari kenyataan. Yang jadi soal adalah proporsinya. Politik seharusnya membuka jalan bagi pembenahan, bukan menjadi penggantinya.
Sebenarnya, kompas untuk perbaikan ini sudah jelas. Mandat konstitusi untuk Polri tegas: menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat di bidang keamanan dalam negeri.
Kolaborasi dengan sektor lain sah-sah saja, asal tidak mengaburkan orientasi tugas utama ini. Batas yang kabur hanya akan melemahkan standar profesional dan memecah-belah akuntabilitas.
Arah perbaikannya pun bisa diukur. Pulihkan fokus pada tugas inti. Tertibkan kultur, dari yang arogan secara prosedural menuju keadilan yang substantif. Kerasankan akuntabilitas internal agar benar-benar memiliki taring. Tingkatkan standar penyidikan lewat supervisi berjenjang yang hidup. Disiplinkan komunikasi publik agar rendah hati dan faktual. Dan mulailah dari keteladanan pimpinan. Kultur tidak berubah oleh slogan, tapi oleh contoh nyata.
Pada akhirnya, kita kembali ke kalimat awal. Menjadi petani bukanlah jawaban. Jawaban atas krisis kepercayaan ini bukan perpindahan simbol atau permainan kata. Jawabannya adalah pertanggungjawaban. Jabatan publik tidak meminta metafora. Ia meminta kerja yang bisa diuji, keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan keberanian moral untuk membenahi yang salah.
Bangsa ini tidak kekurangan slogan. Yang kita perlukan adalah pemimpin yang paham, bahwa amanah itu beban yang harus dipanggul, bukan dialihkan. Jadi, "menjadi petani" bukan jawaban. Menjadi penjaga keadilan dengan sungguh-sungguh itulah jawabannya.






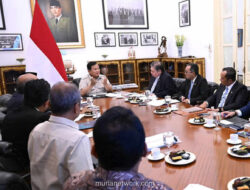




Artikel Terkait
Prabowo Panggil Menteri, Bahas Strategi Kuasai Kekayaan Alam
Darurat Lahan Sawah: 554 Ribu Hektare Beralih Jadi Perumahan dan Industri
Born to Run: Kisah Dua Keluarga yang Bangkit dari Reruntuhan Kecelakaan
Mimpi Buruk Berujung Maut: Remaja di Karawang Tewaskan Ayah Kandung