Angka-angka itu terpampang jelas. Indonesia, sekali lagi, mengklaim diri telah mencapai swasembada pangan. Menurut data BPS, produksi beras tahun 2025 menyentuh 34,71 juta ton. Jumlah itu jauh melampaui konsumsi nasional yang 'hanya' 31,19 juta ton. Hasilnya? Ada surplus sekitar 3,52 juta ton. Bahkan, stok beras nasional di awal 2026 diprediksi bakal membengkak hingga 12,5 juta ton lebih. Secara fisik, kita memang tak kekurangan beras.
Tapi tunggu dulu. Pencapaian statistik yang gemilang ini butuh pembacaan yang lebih hati-hati. Soalnya, keberhasilan di atas kertas belum tentu sama dengan keberhasilan di lapangan. Swasembada yang cuma dimaknai sebagai surplus produksi punya risiko besar: ia cuma jadi kedaulatan di atas administrasi, bukan di meja makan rakyat. Di sinilah paradoksnya mulai kelihatan. Angkanya meyakinkan, tapi pengalaman sehari-hari orang biasa bisa bercerita lain.
Paradoks itu paling nyata terlihat dari soal harga. Ambil contoh data inflasi Desember 2025. Inflasi pangan ternyata melesat hingga 4,58 persen, jauh di atas inflasi umum. Bahkan secara bulanan, kenaikannya cukup tajam. Intinya, meski stok beras di gudang negara aman, tekanan harga justru makin memberatkan konsumen. Ketersediaan ternyata tidak serta-merta menjamin keterjangkauan.
Yang menarik, tekanan harga ini rupanya bukan datang dari hulu. Indeks harga produsen justru menunjukkan tren melambat. Artinya, ketika harga di tingkat petani atau produsen cenderung landai, harga di pasar malah naik. Persoalannya jelas bergeser: dari urusan pasokan ke masalah distribusi, rantai pasok yang berbelit, dan struktur pasar yang timpang. Surplus pangan gagal total menjadi harga yang lebih murah buat rakyat.
Keadaan ini makin terasa ganjil bila melihat kekuatan ekonomi nasional secara keseluruhan. Secara agregat, ekonomi Indonesia itu besar. Tapi angka rata-rata yang bagus itu seringkali menipu. Ia tak bisa menutupi fakta bahwa bagi banyak rumah tangga, pengeluaran untuk pangan masih menghabiskan porsi besar dari pendapatan. Inflasi pangan yang bergerak lebih cepat daripada kenaikan upah memperparah keadaan. Jarak antara kekuatan makro dan realitas mikro jadi kian lebar.
Laporan Global Food Security Index punya gambaran serupa. Posisi Indonesia relatif kuat di aspek ketersediaan. Tapi kita tertinggal jauh soal keterjangkauan, kualitas gizi, dan keberlanjutan. Angka stunting masih memprihatinkan, keragaman makanan rendah, dan sistem pangan kita rentan terhadap perubahan iklim. Ini semua menegaskan satu hal: persoalan utama kita bukan krisis produksi, melainkan krisis akses dan kualitas.
Sayangnya, respons pemerintah kerap terasa reaktif. Impor dibuka saat stok menipis, operasi pasar baru digelar setelah harga melambung. Pola kerja seperti ini ibarat pemadam kebakaran, bukan strategi jangka panjang. Belum lagi, pangan sering direduksi jadi alat politik. Subsidi pupuk, janji harga murah, klaim swasembada semua seolah mengikuti siklus lima tahunan. Setelah itu, hilang sudah kesinambungannya.
Sejarah sebenarnya punya pelajaran berharga yang sering kita lupakan.






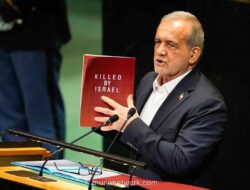




Artikel Terkait
DBMBK Sulsel Sebut Curah Hujan Tinggi Penyebab Kerusakan Dini Jalan Hertasning Makassar
Kapolri Lantik Brigjen Totok Suharyanto Pimpin Kakortas Tipidkor
Musisi AS Tuduh Serangan ke Iran sebagai Pengalihan dari Skandal Epstein
Pemimpin Tertinggi Iran Unggah Ayat Al-Quran, Bantah Klaim Kematian dari AS