Elite yang Diuntungkan, Rakyat yang Dibiasakan
Hingga detik ini, bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar seolah lenyap dari ingatan. Begitu pula dengan kasus penebangan liar yang memicu banjir. Tak ada kasus hukum yang jelas, apalagi tersangka yang dihadirkan. Rakyat menderita, korban berjatuhan ribuan, bahkan ada yang hilang. Tapi semuanya seperti ditutup-tutupi. Ada apa sebenarnya?
Politik Culas yang Dianggap Menyelamatkan?
Ada satu paradoks pahit dalam politik kita yang jarang diungkap terang-terangan. Pola politik yang justru paling sering menang, nyatanya kerap merusak kualitas bangsa itu sendiri.
Coba kita lihat. Selama lebih dari sepuluh tahun terakhir, politik Indonesia bukannya bergerak ke arah pendewasaan publik. Justru sebaliknya, ia bergerak ke arah penghalusan teknik memanipulasi emosi. Wataknya tak berubah, yang berubah cuma cara membungkusnya. Kalau dulu manipulasi dilakukan secara kasar dan terang-terangan, sekarang ia tampil lebih halus, seolah manusiawi, bahkan penuh moralitas.
Inilah yang belakangan disebut-sebut sebagai "politik culas yang dibenarkan". Strategi kekuasaan yang licik, tapi dianggap sah demi alasan "stabilitas", "keberlanjutan", atau "demi bangsa".
Lalu, pertanyaan besarnya: benarkah pola seperti ini masih bisa menyelamatkan bangsa?
Atau jangan-jangan, kita justru sedang diselamatkan dari kekacauan jangka pendek, tapi pelan-pelan dirusak dari dalam?
Di atas kertas, demokrasi menjanjikan kompetisi gagasan. Namun di ruang publik, yang terjadi adalah kompetisi perasaan. Politik kita hari ini tidak dimenangkan oleh argumen yang paling masuk akal, data yang paling kuat, atau rencana kerja yang paling matang.
Ia dimenangkan oleh siapa yang paling pandai memainkan citra. Siapa yang paling piawai berpose sebagai korban. Siapa yang paling lihai mengaduk rasa iba.
Ini bukan tuduhan tanpa dasar. Ini pola yang berulang. Setiap kali publik dihadapkan pada pilihan rasional, yang menang seringkali bukan yang paling siap, melainkan yang paling sukses membangun narasi "kami dizalimi". Bukan yang paling kompeten, tapi yang paling jago tampil sebagai "orang kecil" di panggung kekuasaan yang besar.
Ironisnya, pola ini malah dibela oleh sebagian elite dan komentator dengan argumen pragmatis.
Di sinilah keculasan politik berubah statusnya. Dari sebuah dosa, menjadi strategi yang sah. Dari manipulasi kasar, menjadi manipulasi yang beradab.
Politik culas di Indonesia tidak hilang. Ia berevolusi. Dulu, keculasan tampil vulgar lewat intimidasi atau kekerasan. Kini, ia dibungkus rapi dengan narasi kesederhanaan, dilapisi bahasa kerja keras, diselimuti simbol kerendahan hati.
Citra "tidak ambisius" justru menjadi alat ambisi yang paling ampuh.
Citra "tidak berpolitik" justru menjadi politik paling efektif.
Yang berbahaya sebenarnya bukan keculasannya. Politik di mana pun punya sisi gelap. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika keculasan itu dianggap sebagai sebuah kebajikan.
Saat manipulasi emosi diberi legitimasi moral, publik tidak lagi diajak berpikir. Mereka diajak untuk merasa. Dan ketika politik sepenuhnya pindah ke wilayah rasa, rasionalitas dianggap sebagai gangguan.
Pendukung pola lama punya satu pembelaan utama.
Argumen ini ada benarnya. Indonesia memang negara besar dan majemuk dengan sejarah konflik yang berat. Stabilitas adalah kebutuhan nyata.
Tapi pertanyaannya bukan lagi apakah stabilitas itu penting. Melainkan, bagaimana stabilitas itu dibangun? Stabilitas yang dibangun di atas manipulasi punya harga yang mahal.
Publik tidak pernah benar-benar dididik untuk berpikir kritis. Politik kehilangan fungsi edukasinya. Pemilih dibiasakan untuk bereaksi, bukan menilai.


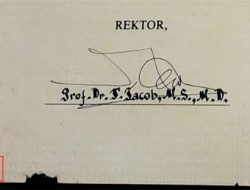








Artikel Terkait
Buka Puasa di Banjarmasin Hari Ini Pukul 18.43 WIB
KPK Tahan Pejabat Bea Cukai Terkait Kasus Suap dan Rp 5,19 Miliar di Apartemen
Es Teler Durian Jadi Primadona Buka Puasa di Makassar
Keong Rebus Jadi Primadona Buka Puasa di Banyumas, Penjualan Melonjak Drastis