Akibatnya, kritik lalu dilihat sebagai musuh. Padahal, kritik yang sehat adalah mekanisme koreksi semacam sistem imun bagi peradaban. Kritik berbasis data dan nalar justru sahabat negara, karena mencegah kesalahan jadi kebiasaan. Fitnah memang harus ditertibkan karena merusak. Tapi kritik harus dilindungi karena ia menyelamatkan kebijakan dari pembusukan. Negara yang kuat bukan yang menakuti warganya, melainkan yang berani dikoreksi dan lalu membuktikan perbaikan.
Pada titik paling getir, sebuah bangsa mengalami kemunduran moral: tahu mana yang benar, tapi memilih yang menguntungkan. Sumpah jabatan diucapkan khidmat, tapi amanah dipinggirkan. Nilai agama menghiasi pidato, tapi ditinggalkan di meja keputusan. Nama Allah disebut, tapi keadilan dilupakan. Keadaan ini melahirkan kelelahan kolektif. Rakyat letih berharap. Institusi letih dipercaya. Ruang publik penuh sandiwara.
Lalu, jalan pulangnya bagaimana? Harus dimulai dari mengembalikan takwa sebagai etika publik. Secara operasional, itu berarti membangun tata kelola yang menutup rapat ruang gelap. Ukurannya bisa konkret: transparansi anggaran, pengendalian konflik kepentingan, audit yang serius, perlindungan untuk pelapor, dan penegakan hukum yang konsisten tanpa tebang pilih.
Urutannya tak boleh terbalik. Pemegang kuasa dan elite negara harus memulai lebih dulu. Mereka pegang kunci kebijakan, anggaran, dan aturan. Keteladanan bukan hiasan, tapi syarat mutlak. Konflik kepentingan harus jadi aib, bukan keterampilan. Rente harus diputus, bukan dibagi. Elite yang menuntut rakyat beradab tapi menolak diaudit, sama saja meminta kepercayaan tanpa bukti.
Tapi peradaban tak akan hidup kalau cuma nunggu elite. Warga juga harus bergerak di levelnya masing-masing: menolak suap sekecil apa pun, menolak menjual suara, membangun literasi, mengawal kebijakan, dan menjaga kritik tetap berbasis fakta. Standar moral jatuh bukan cuma karena penguasa curang, tapi juga karena warga menganggap kecurangan sebagai hal yang normal.
Pendidikan harus jadi mesin utama pembentuk peradaban tempat ilmu, adab, dan keberanian moral bertemu. Pendidikan yang kuat melahirkan warga yang sulit dibodohi, dibeli, atau ditakut-takuti. Ekonomi harus diarahkan ke produktivitas dan inovasi, bukan rente. Hukum harus ditegakkan agar keadilan benar-benar terasa, bukan cuma terdengar. Keadilan yang dirasakan inilah fondasi kepercayaan. Dan kepercayaan adalah modal peradaban.
Konsekuensi jika pembenahan tak segera dimulai sangat nyata dan mahal harganya. Kuasa akan tetap jadi sesembahan halus. Mandat rakyat cuma jadi legitimasi semu. Kritik akan terus dicurigai, sehingga kesalahan berulang tanpa koreksi. Pendidikan tertinggal, ekonomi rente menguat, hukum dipelintir, ketimpangan diwariskan, dan kepercayaan publik runtuh. Negara mungkin tetap berdiri, tapi martabatnya menipis.
Seruannya sederhana: mulailah sekarang. Mulai dari mereka yang memegang kuasa, karena di situlah tanggung jawab terbesar berada. Lanjutkan oleh partisipasi warga. Kuatkan oleh institusi yang menjadikan koreksi sebagai kebiasaan. Jika Allah diakui sebagai Pengatur, maka takwa harus jadi kompas satu-satunya. Hanya dengan kompas itulah bangsa ini bisa berjalan keluar dari politik ekstraktif, menuju peradaban yang lebih adil dan manusiawi.








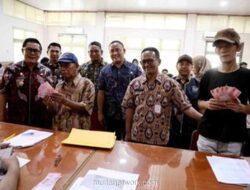


Artikel Terkait
Dua Advokat Gugat MK, Minta Syarat Calon Presiden Dilarang Berkeluarga dengan Petahana
KPK Periksa 14 Saksi Terkait Dugaan Pemerasan Bupati Pati
Larangan Truk Tiga Sumbu Saat Lebaran 2026 Ancam Pasokan Kemasan dan Pabrikan
Polri Dampingi Keluarga Korban dan Pastikan Proses Hukum Kasus Brimob Tewaskan Pelajar di Tual