Menurut data administratif energi AS, sekitar 20% minyak yang diperdagangkan setiap hari di dunia harus melewati Selat Hormuz. Gangguan kecil saja di titik ini bisa langsung melambungkan harga minyak global. Atas nama 'stabilitas', intervensi militer dan aliansi keamanan pun sering dibenarkan.
Tapi stabilitas yang dipertahankan seringkali hanya kulitnya. Dukungan pada rezim otoriter demi jaminan energi malah memperpanjang masalah politik dalam negeri negara-negara tersebut. Kini, bukan cuma AS. China dan Rusia juga makin aktif. China butuh minyak untuk industrinya, sementara Rusia memanfaatkan kerja sama energi sebagai alat pengaruh geopolitik, termasuk lewat OPEC .
Intinya, minyak telah mengubah Timur Tengah jadi arena perebutan kepentingan internasional. Ia bukan lagi sekadar panggung konflik lokal.
Persaingan Regional: Saat Minyak Jadi Senjata
Di tingkat regional, minyak memperkeruh persaingan, terutama antara Arab Saudi dan Iran. Persaingan ini bukan cuma soal pengaruh politik atau ideologi, tapi juga posisi di pasar energi dunia.
Serangan ke fasilitas minyak Arab Saudi di Abqaiq pada 2019 adalah buktinya. Serangan itu sempat memotong sekitar 5% pasokan minyak dunia. Aksi semacam ini tak selalu bertujuan memenangkan perang secara langsung, tapi lebih untuk menciptakan ketidakpastian ekonomi dan tekanan politik. Di sini, minyak berfungsi sebagai alat tawar yang ampuh. Siapa pun yang bisa mengganggu produksi atau distribusinya, punya leverage yang besar di panggung dunia.
Nasib yang Berbeda-beda
Meski sama-sama kaya minyak, nasib negara-negara di kawasan ini tidak seragam. Uni Emirat Arab dan Qatar, misalnya, relatif lebih stabil berkat cadangan keuangan yang besar dan institusi pemerintahan yang lebih mapan.
Sebaliknya, negara seperti Libya, Irak, dan Yaman yang dilanda fragmentasi politik dan konflik internal, justru melihat minyak berubah jadi sumber pertikaian yang tak berkesudahan.
Ada upaya untuk berubah. Visi Saudi 2030 yang ingin mendiversifikasi ekonomi menunjukkan kesadaran akan risiko ketergantungan ini. Tapi transisi ini tidak mudah. Seringkali, reformasi ekonomi justru dibarengi dengan pengetatan kontrol politik, yang berpotensi memicu ketegangan baru jika partisipasi publik dibatasi.
Intinya: Minyak adalah Politik
Jadi, mustahil memahami krisis di Timur Tengah hanya dari kacamata agama, identitas, atau persaingan ideologi semata. Ada faktor politik yang sangat konkret: minyak. Cara kekuasaan dibangun, alasan negara luar ikut campur, dan bagaimana konflik bisa bertahan lama semuanya dibentuk oleh persaingan memperebutkan sumber daya ini.
Selama minyak masih menjadi tulang punggung ekonomi dan alat kekuasaan, penyelesaian konflik yang menyeluruh akan sulit tercapai. Solusi jangka panjang butuh lebih dari sekadar aliran minyak yang stabil. Diperlukan perbaikan tata kelola sumber daya, diversifikasi ekonomi, dan yang paling sulit: mengurangi politisasi energi. Tanpa itu, minyak akan tetap jadi sumber krisis, bukan jalan menuju perdamaian.






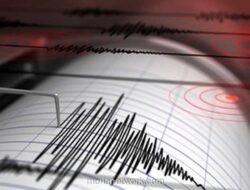




Artikel Terkait
Gunung Gede Pangrango Ditutup Total, Pendakian Baru Dibuka 2026
Cuaca Ekstrem Paksa Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup Sementara
Pidato Prabowo di Sentul Bikin Warganet Geleng-geleng
Satir Tere Liye Disalahartikan, Netizen: Mereka Tak Paham atau Kebanyakan MBG?