Kalau kita bicara konflik di Timur Tengah, satu kata hampir selalu muncul: minyak. Ini bukan rahasia lagi. Setiap kali ketegangan memanas, entah itu perang terbuka atau perang proksi yang melibatkan kekuatan asing, sumber daya hitam ini selalu jadi bagian dari cerita. Minyak bukan cuma urusan uang di sini. Ia adalah jantung dari banyak gejolak.
Soalnya, persoalannya lebih dalam dari sekadar cadangan besar yang tersimpan di perut bumi. Minyak punya cara tersendiri dalam membelokkan politik dalam negeri sebuah negara. Ia menarik perhatian dan campur tangan negara-negara besar yang punya kepentingan strategis. Bahkan, ia memicu persaingan sengit antar negara di kawasan itu sendiri. Pada akhirnya, minyak berubah wujud. Dari sekadar komoditas, ia jadi senjata politik, alat ekonomi, dan pemicu konflik yang nyata.
Negara Kaya Minyak dan Ketidakstabilan Politik
Mayoritas negara di kawasan ini hidup dari pendapatan minyak, bukan dari pajak rakyatnya. Model ini sering disebut rentier state. Ambil contoh beberapa negara Teluk, di mana data Bank Dunia menunjukkan kontribusi minyak dan gas bisa mencapai 80% dari pemasukan negara.
Karena tidak bergantung pada pajak, tekanan politik dari warga ke pemerintah pun cenderung lebih rendah. Kredibilitas pemerintah dibangun lewat subsidi energi, berbagai bantuan sosial, dan lapangan kerja di sektor publik. Memang, dalam jangka pendek, sistem ini terlihat kokoh. Tapi lama-kelamaan, ia justru melahirkan sistem politik yang tertutup dan minim akuntabilitas.
Kerapuhan model ini akan langsung terasa saat harga minyak anjlok, atau ketika ketimpangan dalam pembagian kekayaan sudah tak tertahankan lagi. Masalah keuangan dengan cepat berubah jadi masalah politik. Lihat saja Irak dan Libya. Perebutan ladang minyak dan fasilitas ekspor di sana sering berujung pada bentrokan bersenjata antar faksi. Dalam kondisi seperti itu, minyak bukannya mengonsolidasi kekuasaan, malah jadi bahan bakar kekerasan.
Minyak dan Perang Saudara
Banyak penelitian yang mengaitkan ketergantungan tinggi pada minyak dengan risiko perang saudara. Seperti yang ditunjukkan Michael Ross dalam bukunya, "The Oil Curse", lemahnya institusi politik dan tingginya peluang konflik internal punya kaitan erat dengan kekayaan minyak.
Yaman adalah contoh nyata. Sebelum konflik meledak, lebih dari 70% ekspornya digerakkan oleh minyak. Saat pemerintahan pusat melemah, akses ke sumber daya itu jadi rebutan bagi berbagai kelompok bersenjata.
Pola serupa terlihat di Suriah dan Irak. ISIS, pada puncaknya tahun 2014-2017, dengan sengaja menguasai ladang-ladang minyak untuk membiayai operasi militernya.
Ini membuktikan satu hal: minyak menjadi insentif finansial yang kuat bagi aktor-aktor kekerasan. Selama masih bisa dieksploitasi dan dijual dengan untung, konflik akan terus "dibakar" agar tak padam.
Mengapa Negara Luar Tak Pernah Berhenti Ikut Campur?
Minyak juga alasan utama mengapa Timur Tengah tak pernah lepas dari intervensi kekuatan global. Selama puluhan tahun, Amerika Serikat menjadikan keamanan pasokan minyak dari kawasan ini sebagai kepentingan strategis nasional. Meski sekarang AS lebih mandiri secara energi, wilayah ini tetaplah vital bagi pasar global.






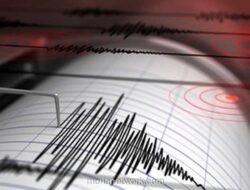




Artikel Terkait
Gunung Gede Pangrango Ditutup Total, Pendakian Baru Dibuka 2026
Cuaca Ekstrem Paksa Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup Sementara
Pidato Prabowo di Sentul Bikin Warganet Geleng-geleng
Satir Tere Liye Disalahartikan, Netizen: Mereka Tak Paham atau Kebanyakan MBG?