Di tengah hiruk-pikuk ini, Prabowo melakukan abolisi dan rehabilitasi. Apakah langkah itu benar? Secara hukum: iya. Secara politik: iya. Tapi secara moral? Itu menimbulkan pertanyaan lebih gelap.
Jika seorang warga negara memang dikriminalisasi, mengapa presiden baru bergerak setelah kasusnya viral? Mengapa abolisi untuk menghentikan proses hukum, tidak diberikan sejak awal dugaan ketidakadilan muncul? Apakah nasib seseorang kini bergantung pada seberapa kuat ia trending?
Inilah dilema besar republik kita: siapa sebenarnya yang memutuskan kebenaran hukum atau tekanan publik?
Di satu sisi, tekanan publik bisa mengoreksi kriminalisasi. Tapi di sisi lain, jika hukum selalu kalah oleh keramaian, demokrasi berubah menjadi arena gladiator: siapa paling bising, dia menang.
Negara yang diadili oleh netizennya sendiri memang bisa terasa lucu, tetapi dalam jangka panjang itu berbahaya. Sebab negara yang hanya bergerak karena viral dan algoritma adalah negara yang tidak lagi berpegang pada prinsip, tetapi pada popularitas.
Maka ke depan, POLRI, Kejaksaan Agung dan KPK harus menata ulang fondasi paling dasar dari pekerjaan mereka: konsistensi keadilan sejak awal, bukan koreksi setelah publik marah.
Penyidikan harus transparan sejak detik pertama. Tidak menunggu arahan politik untuk memastikan suatu dakwaan sah atau tidak. Tidak menjadikan publik watchdog utama karena seharusnya mereka sendiri yang punya mekanisme internal pengawasannya. Mengembalikan kepercayaan publik melalui pengakuan bahwa dalam beberapa kasus mereka memang keliru.
Kejujuran lembaga sering kali lebih memperbaiki martabat daripada kemenangan kasus.
Pada akhirnya, republik ini butuh sebuah sistem hukum yang berani berdiri tegak di tengah badai opini. Karena keadilan yang sehat bukan yang menang karena viral, tetapi yang tiba tepat waktu bahkan ketika tidak ada kamera merekamnya.
Sebab seperti kata Vaclav Havel, presiden Republik Ceko sekaligus penulis yang pernah hidup melawan sistem yang bengkok:
"Kebenaran bukan apa yang disukai banyak orang. Ia apa yang bertahan bahkan ketika tidak ada yang bertepuk tangan."
Jika para filsuf dulu bertanya, "Apa itu kebenaran?", di era kita pertanyaannya berubah:
"Berapa view yang dibutuhkan agar kebenaran dianggap penting?"
Mungkin itu yang sedang kita cari hari-hari ini: sebuah keadilan yang tidak menunggu viral untuk bekerja. Atau memang moral kekuasaan baru terpanggil setelah pintu istana digedor netizen?
Di negeri yang sibuk mengejar trending topic, keadilan kini seperti penumpang gelap yang baru turun dari mobil ketika kamera sudah siap merekam. Dua kasus besar Tom Lembong dan Ira Puspadewi kini membuka wajah baru republik: hukum yang bergerak bukan ketika kebenaran dipertaruhkan, tetapi ketika publik sudah mengetuk pintu dengan tagar dan kemarahan.








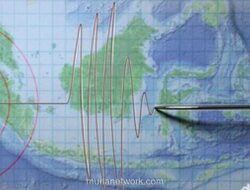


Artikel Terkait
Iran: Ratusan Ambulans Hancur, Kerugian Capai Jutaan Dolar
Jalur Peureulak-Lokop Kembali Dibuka, Akses Darurat Pulih Setelah Banjir Bandang
TNI-Polri Siapkan Petugas Haji 2026 dengan Gemblengan Semi-Militer
Trump Ancam Kolombia dengan Operasi Militer, Gelombang Protes Membanjiri Jalanan