Dari sekian banyak pesantren yang pernah saya kunjungi, ada dua yang benar-benar menancapkan tradisi menulis dalam DNA mereka. Yang pertama adalah Pesantren Elkisi di Mojokerto, Jawa Timur. Lalu ada juga Pesantren At-Taqwa di Depok, Jawa Barat. Keduanya punya cara masing-masing, tapi sama-sama serius membangun budaya literasi.
Di Elkisi, para santri SMA diwajibkan menulis buku. Bayangkan, anak kelas 12 digembleng habis-habisan oleh para guru sampai bisa menghasilkan karya utuh yang layak dibaca. Hasilnya? Karya-karya mereka kini menghiasi rak perpustakaan Elkisi, menjadi inspirasi untuk adik-adik kelas.
Sementara di At-Taqwa, pembinaan dimulai lebih awal. Santri sudah diajari menulis sejak SMP. Mereka dibina untuk membuat reportase, makalah ilmiah, dan berbagai jenis tulisan lainnya. Ketika sampai di tingkat SMA, tantangannya semakin berat: mereka harus menulis makalah ilmiah tentang keislaman yang dipresentasikan tidak hanya di sekolah lain, tapi bahkan sampai ke Malaysia. Kualitas tulisan mereka? Jangan ditanya, seringkali tidak kalah dengan karya para sarjana.
Kalau kita tilik sejarah, sebenarnya tradisi menulis di pesantren sudah berumur sangat tua. Jejaknya bisa dilacak sampai ke naskah-naskah kuno abad ke-12. Pesantren bukan cuma lembaga pendidikan tertua di Nusantara, tapi juga benteng ilmu pengetahuan yang melahirkan ribuan karya tulis.
Naskah-naskah tua dari Jawa, Sumatra, dan Kalimantan menjadi saksi bisu betapa pesantren sudah aktif berkontribusi dalam khazanah keilmuan Islam. Di abad ke-12 saja, Nusantara sudah mengenal karya-karya keagamaan beraksara Arab-Jawi. Ini menunjukkan dialog yang hidup antara ulama lokal dengan tradisi keilmuan Timur Tengah. Naskah Barus dan Samudera Pasai adalah contoh nyata yang masih bisa kita pelajari sampai sekarang.
Tradisi ini makin berkembang pesat antara abad 16 hingga 19. Pada masa ini, ulama Nusantara mulai menelurkan karya-karya monumental di berbagai bidang: tafsir, hadis, fikih, akhlak, tasawuf, sampai sejarah. Beberapa nama besar yang layak disebut antara lain:
- Syekh Abdurrauf As-Singkili di abad 17 dengan Tarjuman al-Mustafid-nya, tafsir Al-Qur'an pertama dalam bahasa Melayu.
- Syekh Nuruddin ar-Raniri, ulama Aceh yang produktif menulis ensiklopedia akidah dan tasawuf.
- Syekh Nawawi al-Bantani di abad 19, yang menghasilkan lebih dari 100 kitab yang bahkan diajarkan di Haramain.
- Syekh Ahmad Khatib Sambas, pelopor tarekat Qadiriyah-Naqsyabandiyah dengan karya-karya tasawufnya.
- KH Hasyim Asy'ari, yang warisan tulisannya seperti Adabul 'Alim wal-Muta'allim masih menjadi rujukan di pesantren hingga kini.
Karya-karya mereka membuktikan satu hal: pesantren tidak pernah absen dari tradisi literasi. Menulis bukan sekadar pelengkap, tapi bagian dari ibadah ilmiah yang memperkuat peradaban.
Mengapa Pesantren Kuat dengan Tradisi Menulis?
Ada beberapa alasan mendasar, baik historis maupun kultural, yang membuat pesantren tidak bisa dipisahkan dari aktivitas menulis.
Pertama, menulis menjadi sarana menjaga sanad keilmuan. Dalam Islam, ilmu diturunkan secara berantai dari guru ke murid. Nah, menulis inilah yang mengikat ilmu agar tidak hilang ditelan zaman.
Imam Syafi'i pernah bilang: "Ilmu itu ibarat binatang buruan, dan tulisan adalah tali pengikatnya."
Memang pesantren punya metode seperti halaqah dan sorogan, tapi tulisanlah yang mengabadikan semua itu.
Kedua, menulis dianggap sebagai bentuk ibadah. Banyak ulama yang tetap menulis sampai usia senja karena meyakini bahwa amal jariyah tidak hanya melalui pembangunan masjid atau wakaf, tapi juga melalui ilmu yang tertulis.
Imam Ghazali menyebut pena sebagai "senjata ulama" yang bisa menggerakkan perubahan sosial. Sementara Imam As-Suyuthi berpendapat bahwa menulis adalah "amal para nabi dan pewarisnya."
Alasan ketiga, menulis menjadi tradisi intelektual untuk menjawab tantangan zaman. Sejarah mencatat, ulama sering menulis untuk merespons persoalan sosial mulai dari perdebatan teologis, pertemuan dengan budaya lokal, sampai penjajahan. Karya-karya Syekh Nawawi al-Bantani, misalnya, bukan sekadar syarah biasa, tapi dialog dengan masalah pendidikan, akhlak, dan politik di abad 19.



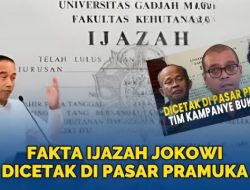







Artikel Terkait
Ketua Gema Bangsa Usul Ganti Parliamentary Threshold dengan Ambang Batas Fraksi
Kapolri Tegaskan Persatuan Nasional Kunci Hadapi Dampak Krisis Global
Dua Advokat Gugat MK, Minta Syarat Calon Presiden Dilarang Berkeluarga dengan Petahana
KPK Periksa 14 Saksi Terkait Dugaan Pemerasan Bupati Pati