Publik ramai memperbincangkan penunjukan Sabrang Mowo Damar Panuluh, yang lebih akrab disapa Noe Letto, sebagai Tenaga Ahli Madya di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Sorotan ini bukan cuma soal latar belakangnya di dunia musik. Lebih dari itu, posisi strategis ini muncul di tengah citra keluarga besarnya, Cak Nun (Emha Ainun Nadjib), yang selama puluhan tahun dikenal garang mengkritik kekuasaan. Forum Kenduri Cinta dan berbagai diskusi budaya jadi panggungnya.
Di sisi lain, Noe Letto sendiri bukan sosok biasa. Di balik panggung, ia adalah seorang intelektual. Pendidikannya cukup mentereng: ia menempuh studi sains di University of Alberta, Kanada, dengan mengambil dua jurusan sekaligus, matematika dan fisika. Belum cukup, ia juga merampungkan gelar Sarjana Hukum setelah kembali ke Indonesia. Modal akademik inilah yang kerap dijadikan dasar untuk membenarkan penunjukannya.
Tapi, bagi banyak pengamat, bau politik tercium kuat di sini. Mereka yang kritis melihat pola lama: jabatan negara sering jadi alat domestikasi. Sebuah cara yang halus untuk meredam suara-suara perlawanan tanpa konfrontasi terbuka. Apalagi, Cak Nun dan lingkaran Kenduri Cinta memang tak pernah sungkan melontarkan kritik tajam terhadap rezim, menyentuh isu keadilan sosial hingga arah pemerintahan.
Pertanyaan besarnya sederhana namun menusuk: ini murni soal profesionalisme, atau bagian dari taktik "merangkul agar sunyi"? Sejarah politik kita sudah sering mempertontonkan hal serupa. Intelektual dan budayawan yang vokal kerap diberi tempat di dalam sistem. Tujuannya? Agar kritik yang tadinya menggema di ruang publik berubah menjadi sekadar diskusi internal yang tertutup.



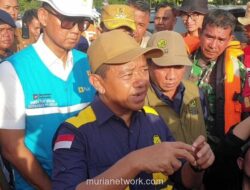







Artikel Terkait
Dua Aktivis Pati Bebas Bersyarat Usai Divonis 6 Bulan Penjara
Pemprov Sulsel Salurkan Bantuan untuk Korban Angin Puting Beliung di Takalar
Pengendara Motor Tewas Tabrak Truk yang Berhenti di Jalan Wates-Purworejo
Pemerintah Pastikan Kondisi Pekerja Migran Indonesia di Timur Tengah Masih Aman