✍🏻 Erizeli Bandaro
Dalam sebuah podcast yang diunggah di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Fahri Hamzah melontarkan pernyataan yang cukup menggelitik. Dia menyebut ada "shadow power" atau kekuatan bayangan yang memengaruhi kebijakan presiden. Fahri, yang kini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan dikenal sebagai pendamping setia Prabowo Subianto sejak 2014, menegaskan bahwa keputusan akhir tetaplah di tangan presiden. Tapi, ya, pernyataan soal kekuatan di balik layar itu yang bikin orang berpikir ulang.
Kalau didengar sekilas, pernyataannya terdengar agak bertentangan. Bagaimana mungkin ada kekuatan lain, tapi presiden tetap yang memutuskan? Namun, dalam kacamata politik dan ekonomi politik, justru gambaran itulah yang paling nyata. Presiden tidak pernah bekerja sendirian di ruang kosong. Dia adalah pembuat keputusan formal yang bergerak di tengah medan kekuasaan yang dipenuhi berbagai aktor non-negara. Mulai dari lingkaran oligarki, elite birokrasi, sampai jaringan bisnis lama yang sudah mengakar puluhan tahun.
Konsep ini sebenarnya bukan hal baru. Susan Strange, misalnya, pernah bicara soal "power beyond the state". Intinya, kekuasaan struktural sering bekerja di luar institusi formal negara, tapi justru sangat menentukan pilihan kebijakan yang diambil.
Karena itu, membayangkan presiden sebagai penguasa tunggal yang sepenuhnya otonom adalah penyederhanaan yang agak naif. Demokrasi lewat pemilu tidak serta-merta menghapus relasi kuasa yang sudah mengendap lama dalam ekonomi politik suatu negara. Seperti yang diungkap Acemoglu dan Robinson, institusi politik yang inklusif bisa dengan mudah dibajak oleh institusi ekonomi yang ekstraktif jika distribusi kekuatan material tidak benar-benar berubah.
Nah, dalam konteks Indonesia pasca satu dekade pemerintahan sebelumnya, tekanan utama yang saya amati justru bukan dari luar negeri. Melainkan dari kekuatan status quo domestik kelompok yang sudah nyaman mengakses sumber daya, proyek, dan rente selama sepuluh tahun terakhir. Mereka punya kepentingan rasional untuk mempertahankan struktur yang ada.
Di sisi lain, kelompok seperti ini di tingkat global kerap memanfaatkan "external alignment". Mereka menjalin hubungan dengan Amerika Serikat, China, atau kekuatan lain, bukan sebagai bentuk loyalitas ideologis, tapi lebih sebagai alat tawar-menawar terhadap penguasa domestik. Literatur tentang jaringan elite transnasional menyebut relasi semacam ini lebih bersifat oportunistik.
Masalahnya makin runyam ketika negara mengalami keterbatasan sumber daya fiskal. Dalam situasi seperti itu, solusi kebijakan sering direduksi jadi satu hal: mencari uang. Presiden pun berada di posisi rentan. Tawaran yang "terlalu bagus untuk ditolak" kerap muncul janji pendanaan besar, investasi kilat, solusi instan tanpa struktur yang jelas dan waktu yang pasti. Dalam teori "time inconsistency" (Kydland & Prescott), inilah momen ketika pengambil kebijakan kehilangan aset paling berharga: waktu.






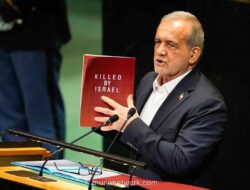




Artikel Terkait
DBMBK Sulsel Sebut Curah Hujan Tinggi Penyebab Kerusakan Dini Jalan Hertasning Makassar
Kapolri Lantik Brigjen Totok Suharyanto Pimpin Kakortas Tipidkor
Musisi AS Tuduh Serangan ke Iran sebagai Pengalihan dari Skandal Epstein
Pemimpin Tertinggi Iran Unggah Ayat Al-Quran, Bantah Klaim Kematian dari AS