Ini jelas sebuah belokan haluan yang drastis. Dari narasi “aset nasional”, tiba-tiba bergerak ke arah penegakan hukum yang represif. Banyak pengamat menyebutnya sebagai “putar haluan” politik.
Dan janji itu bukan omong kosong. Beberapa bulan setelahnya, tepatnya Oktober 2025, operasi penyitaan besar-besaran dimulai. Militer dan aparat dikerahkan. Sekitar 3,7 juta hektar lahan dinyatakan ilegal dan diambil alih. Yang menarik, sebagian besar lahan itu kemudian dikelola oleh perusahaan negara yang diisi oleh purnawirawan militer.
Langkah ini ibarat melempar batu ke kolam yang tenang. Industri sawit gempar, investor cemas, pasar global waspada. Tapi di sisi lain, bagi para pegiat lingkungan dan komunitas lokal, ini adalah secercah harapan. Ada peluang untuk restorasi, untuk mengembalikan lahan itu menjadi hutan atau setidaknya dikelola secara lebih berkelanjutan.
Lalu, apa yang mendorong perubahan sikap yang begitu ekstrem ini? Tampaknya, ada beberapa faktor yang berpadu.
Pertama, tekanan global. Regulasi seperti EUDR dari Uni Eropa memaksa Indonesia membersihkan rantai pasok sawitnya. Ekspor tak bisa lagi mengabaikan isu deforestasi. Kedua, kebutuhan legitimasi di dalam negeri. Kritik dan protes yang terus-menerus harus dijawab dengan tindakan nyata, kalau tidak, kepercayaan publik bisa anjlok. Ketiga, soal kedaulatan. Dengan menyita lahan ilegal, negara menunjukkan otoritasnya untuk mengontrol sumber daya. Terakhir, dan ini yang paling pelik, adalah dilema klasik antara mengejar pertumbuhan ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah sepertinya mencoba mencari titik kompromi di tengah situasi yang serba sulit.
Jika kebijakan ini dijalankan dengan baik, potensi manfaatnya besar. Lahan yang rusak bisa dipulihkan, citra Indonesia di mata dunia membaik, dan akses ke pasar ekspor yang lebih ketat pun terbuka. Namun, jalan menuju ke sana masih panjang dan berliku.
Pada akhirnya, perjalanan dari “sawit sebagai aset” menuju “sawit ilegal disita” ini mengungkap paradoks mendasar Indonesia. Di satu sisi, negara ini butuh sawit untuk menghidupi perekonomiannya. Di sisi lain, ia juga punya kewajiban besar untuk menjaga hutan dan lingkungan bagi generasi mendatang.
Perubahan kebijakan ini bukan sekadar ganti kata-kata. Ini soal arah bangsa. Bisa jadi titik balik menuju pengelolaan yang lebih adil dan bertanggung jawab. Tapi, bisa juga ia hanya menjadi alat bagi perpindahan kekuasaan dari satu kelompok elite ke kelompok lainnya, malah memicu konflik baru.
Masyarakat sipil, media, dan kita semua harus terus mengawasi. Apakah retorika “penegakan hukum” ini akan diterjemahkan menjadi kebijakan yang adil? Atau hanya akan jadi alat politik musiman? Pertanyaan ini harus dijawab dengan transparansi dan partisipasi publik yang nyata. Agar utang pada alam dan utang pada rakyat kecil tidak terus menumpuk.
Bencana banjir besar yang menelan ratusan korban jiwa dan membuat jutaan orang menderita, sepertinya juga ikut menguatkan tekad untuk berubah. Ada desakan yang kuat dari realitas itu sendiri. Jika izin untuk sawit tidak dibatasi dan hutan tidak dilestarikan, musibah tahunan mungkin akan jadi harga yang terus kita bayar.
Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.






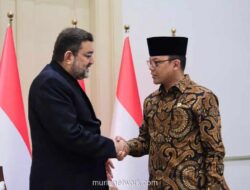




Artikel Terkait
KPK Bantah Pengakuan Bupati Fadia Soal Fokus Urusan Seremonial
Jonatan Christie Lolos ke 16 Besar All England Lewat Pertarungan Tiga Gim
Kampoeng Popsa di Losari Jadi Destinasi Favorit Sahur hingga Subuh
Menag: Peringatan Nuzulul Quran dan Zakat Pejabat Digelar di Istana Negara