Pembangunan di banyak negara berkembang ibarat lomba lari. Pemerintah mendambakan pertumbuhan, inovasi, teknologi tinggi, dan tentu saja, pengakuan internasional. Mereka memamerkan angka-angka statistik dan kurva yang terlihat ilmiah, seolah tanpa cela. Ambisi semacam itu sebenarnya wajar. Namun, ketika fokusnya cuma pada hal-hal yang kasat mata gedung pencakar langit, laboratorium supercanggih, atau jumlah publikasi ilmiah kita lupa bahwa pondasi masyarakat bukanlah mesin atau kabel. Pondasinya adalah manusia, dengan segala pola pikir, hubungan sosial, dan visi kolektif mereka tentang masa depan.
Saya jadi teringat John Keating, guru bahasa Inggris di sekolah elit dalam film Dead Poet Society. Bayangkan, dia mengajak murid-muridnya membaca puisi sesuatu yang dianggap tak berguna di dunia modern. Tapi justru di situlah letak pesannya.
Kutipan Keating bukan sekadar pujian untuk seni atau puisi, dua hal yang makin tersingkir dari kehidupan kita. Itu adalah pengingat bahwa hidup manusia tidak cuma soal bertahan hidup, tapi juga tentang hal-hal yang membuat hidup layak dijalani.
Menurut Keating, STEM seperti kedokteran, hukum, dan teknik memang menjadi fondasi biologis dan struktural masyarakat. Tapi puisi, gagasan, refleksi diri, dan imajinasi, yang menjadi inti dari ilmu sosial-humaniora, adalah ruang di mana manusia menemukan arah, nilai, dan makna hidup. Tanpa itu, kemajuan hanya akan melahirkan masyarakat yang sibuk, cepat, efisien, tapi kehilangan jiwanya.
Nah, karena gagasan semacam ini punya daya kritis yang dalam, tak heran kalau belakangan lembaga donor internasional dan program prestisius seperti LPDP lebih banyak menyalurkan dana ke bidang STEM. Pemerintah bilang ini "kebutuhan strategis negara." Tapi siapa yang mendefinisikan kata "strategis" itu? Kalau strategis cuma berarti pertumbuhan ekonomi yang belum tentu merata maka negara sedang membangun masa depan dengan kacamata kuda. Kita lupa bahwa masalah seperti korupsi, birokrasi lamban, media bias, dan ketimpangan sosial tidak bisa disembuhkan hanya dengan teknologi.
Lalu kenapa negara lebih memilih STEM? Jawabannya sederhana: STEM lebih mudah diukur. Outputnya jelas, kompetensinya langsung diserap industri, dan secara politik, bidang ini relatif aman. Tidak ada risiko mahasiswa pulang dari studi dengan membawa pertanyaan-pertanyaan kritis tentang kuasa, struktur sosial, atau ketidakadilan politik.
Sementara itu, mahasiswa sosial-humaniora yang seharusnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting justru sering dipinggirkan. Saya ingin menyampaikan dengan jelas meski mungkin tak dipahami sepenuhnya oleh para profesor yang kini jadi menteri atau dirjen bahwa keberhasilan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan kecanggihan teknologinya, tapi juga kedalaman cara berpikir masyarakatnya.
Di Bawah Naungan Modernisme, STEM Berkuasa
Tentu, tak ada yang menyangkal manfaat STEM. Dunia kerja butuh insinyur, programmer, ahli bioteknologi, dan analis data. Negara ingin bersaing global, dan STEM dianggap jalur tercepat. Setiap teknologi baru dianggap solusi: kemacetan diatasi dengan aplikasi transportasi, korupsi dilawan dengan digitalisasi seolah-olah masalahnya bukan pada mentalitas aparat yang bobrok.
Bagi pemerintah, ini investasi yang mudah dijual sebagai bukti kemajuan. Tapi di balik itu, kita sebenarnya sedang menelan mentah-mentah logika modernisme: keyakinan bahwa kehidupan sosial bisa diselesaikan lewat standarisasi teknis. Bahwa masalah manusia adalah soal efisiensi, bukan pemaknaan. STEM melahirkan "robot-robot" baru: manusia yang bekerja tanpa mempertanyakan makna pekerjaannya, hanya fokus pada tugas yang selesai, efektif, efisien, lalu menerima gaji dan mengejar kebahagiaan semu.
Struktur pendanaan penelitian di Indonesia pun ikut mendukung kecenderungan ini. Hibah penelitian lebih banyak dialirkan ke proyek-proyek yang aman secara politik: energi hijau, teknologi pangan, kecerdasan buatan, atau kesehatan digital.
Masalahnya makin runyam ketika kebijakan nasional menilai hampir semua proposal riset dengan standar Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT). Padahal, TKT adalah alat seleksi buatan NASA untuk menilai vendor bukan instrumen yang cocok untuk menangkap kedalaman analitis riset sosial-humaniora. Tapi di sini, TKT masih dipakai sebagai ukuran keberhasilan riset, memaksa SSH mengikuti logika yang bukan miliknya.
Akibatnya, penelitian SSH seperti analisis isi media atau studi etnografi sering dianggap "kurang matang" hanya karena tidak menghasilkan prototipe atau model teknologi. Ironisnya, ketika anggaran penelitian SSH tidak terserap karena sebagian besar dialokasikan untuk buku, perjalanan lapangan, dan waktu berpikir yang panjang, kesimpulan yang muncul bukan "format pendanaannya tidak cocok," melainkan "SSH tidak bekerja maksimal."

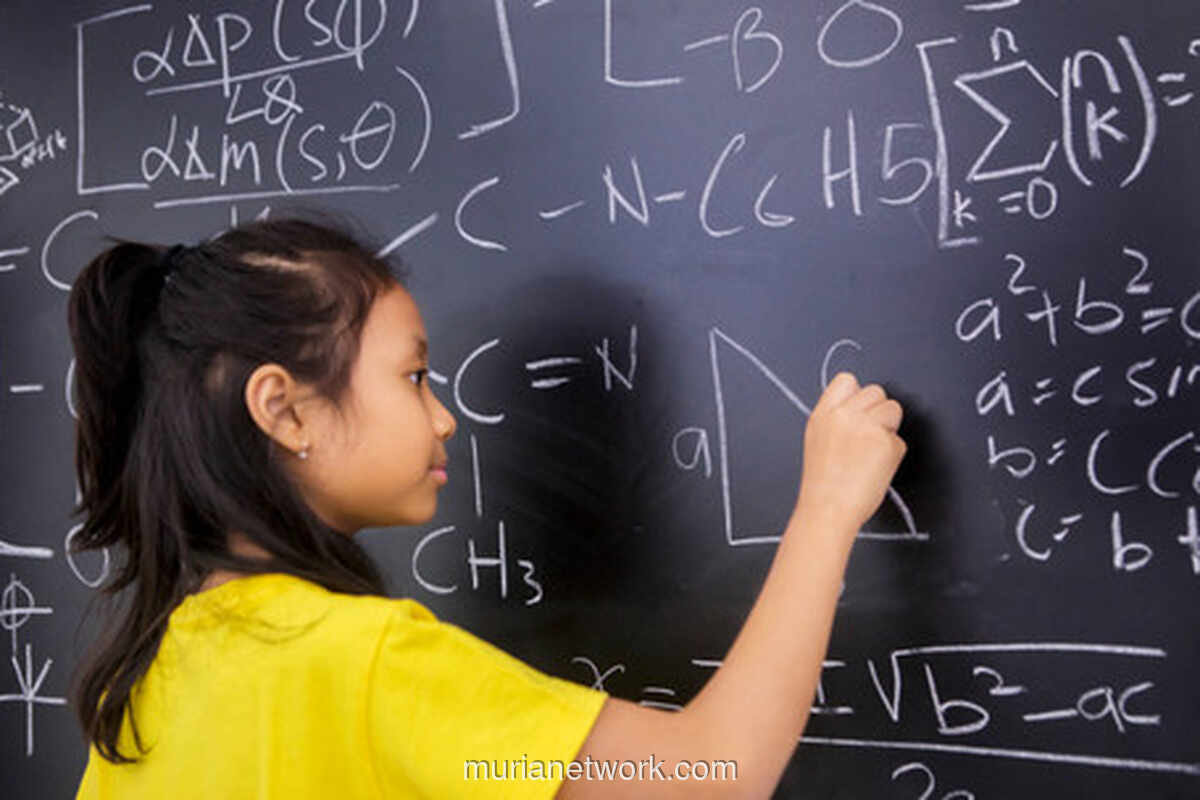









Artikel Terkait
Ratusan Ton Bawang Ilegal Berbakteri Digagalkan di Gudang Semarang
Jemaah Haji Khusus Dapat Bonus Rp10 Jutaan dari Pengelolaan Dana Awal
Papa Zola The Movie: Tiga Tahun dan Rp80 Miliar untuk Sebuah Spin-off
Bus Rute Lampung-Bekasi Hangus Terbakar di Jalan Diponegoro, Seluruh Penumpang Selamat