Suara-suara sumbang bermunculan menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang perwira aktif menduduki jabatan publik. Bagi sebagian kalangan, langkah ini dinilai terlalu drastis. Mereka bilang, keputusan ini mengabaikan kebutuhan praktis negara yang selama ini mengandalkan keahlian teknis, pengalaman intelijen, dan kapasitas manajerial para jenderal di lembaga strategis sesuatu yang jarang dimiliki pejabat sipil biasa.
Kekhawatiran terbesarnya? Fleksibilitas pemerintah dalam merespons ancaman keamanan nontradisional bisa terhambat. Ancaman semacam ini kan butuh penanganan lintas sektor yang lincah.
Nah, di sinilah pangkal persoalannya. Lihat saja siapa saja yang kena imbas: Komjen Setyo Budiyanto di KPK, Komjen Marthinus Hukom di BNN, lalu ada Komjen Eddy Hartono di BNPT, dan Komjen Albertus Rachmad Wibowo yang memimpin BSSN. Belum lagi Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho di Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Komjen Nico Afinta di Kemenkumham. Mereka semua ditugaskan di institusi yang memerlukan keahlian teknokratis tinggi.
Di sisi lain, melepas mereka begitu saja di saat lembaga-lembaga itu sedang menangani isu laten korupsi, narkotika, terorisme, keamanan siber, hingga potensi kejahatan kelautan bisa mengganggu kesinambungan kebijakan yang sudah berjalan. Bagi yang tidak setuju, putusan MK ini terkesan terlalu prinsipil, tapi abai terhadap realitas operasional di lapangan.
Perspektif Demokrasi dan Kebutuhan Reformasi
Tapi dalam negara demokrasi, prinsip pemisahan fungsi institusi keamanan dari jabatan politik dan birokrasi sipil itu fondasinya kokoh. Tidak bisa dikompromikan.
Samuel Huntington, ilmuwan politik Amerika yang teorinya tentang "objective civilian control" jadi rujukan global, menegaskan bahwa profesionalisme militer dan kepolisian justru berkembang kalau mereka tidak terjun ke dalam pengelolaan kekuasaan sipil.
Dalam kerangka teori itu, keberadaan perwira aktif di jabatan publik seberapa pun strategisnya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, bias institusional, dan ketidakseimbangan hubungan sipil–keamanan.
Konteks Indonesia pun makin memperkuat relevansi prinsip ini. Di bawah pemerintahan Jokowi, persoalan mendasar di tubuh Polri makin kentara. Mulai dari akuntabilitas, korupsi, pelanggaran HAM, sampai merosotnya kepercayaan publik. Puncaknya terjadi saat gelombang protes besar Agustus 2025 yang menewaskan sedikitnya 10 orang dan memicu penangkapan aktivis.
Dalam lanskap demokrasi, situasi semacam ini menunjukkan bahwa reformasi Polri bukan cuma urusan teknokratis. Ini soal koreksi struktural terhadap relasi kekuasaan yang bertahun-tahun mengalami distorsi.
Seperti ditegaskan editorial The Jakarta Post edisi 18 November 2025, reformasi ini mendesak. Soalnya menyangkut pemulihan kepercayaan publik dan penegakan prinsip negara hukum.
Implikasi Jika Putusan MK Tidak Dipatuhi
Lalu, apa jadinya kalau Polri lambat atau malah enggan menjalankan putusan MK? Setidaknya ada tiga implikasi serius yang mengintai demokrasi Indonesia.
Pertama, ketidakpatuhan akan melemahkan prinsip supremasi hukum. MK itu lembaga puncak penafsir konstitusi. Mengabaikan putusannya sama saja memberi sinyal bahwa institusi keamanan bisa jadi pengecualian. Bahaya, kan, dalam sistem demokrasi?
Kedua, kredibilitas Komisi Percepatan Reformasi Polri yang baru dibentuk bisa rusak. Komisi ini tidak akan bisa bekerja efektif jika syarat fundamental reformasi pemisahan tegas fungsi kepolisian dari jabatan strategis pemerintah tidak ditegakkan sejak awal. Reformasi yang setengah hati cuma akan jadi polesan kosmetik. Mengulang pola lama tanpa membenahi struktur dan budaya kekuasaan.
Ketiga, krisis kepercayaan publik terhadap Polri bisa makin panjang. Dalam demokrasi, kepercayaan itu modal politik utama bagi lembaga penegak hukum. Kalau publik melihat polisi sendiri mengabaikan konstitusi, upaya memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan penyelidikan pelanggaran internal akan kehilangan legitimasi moral.
Pada akhirnya, reformasi Polri yang sedang berjalan bakal menghadapi hambatan lebih keras. Bukan karena kurang komitmen teknis, tapi karena kerapuhan etika institusional.
Memang, keberatan sebagian pihak terhadap putusan MK bisa dimengerti dari sudut stabilitas kebijakan dan kebutuhan teknis lembaga strategis. Tapi dalam kerangka negara demokrasi, supremasi hukum dan profesionalisme kepolisian harus ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan pragmatis jangka pendek.
Patuh pada konstitusi bukan cuma kewajiban hukum. Itu prasyarat bagi lahirnya Polri yang modern, akuntabel, dan dipercaya publik. Reformasi mungkin terasa pahit sekarang. Tapi tanpa langkah tegas sejak dari fondasi, masa depan demokrasi dan keamanan Indonesia justru kian rapuh.



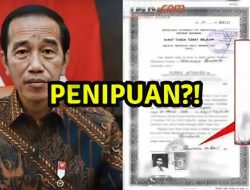







Artikel Terkait
Pelajar Tewas Diduga Dianiaya Oknum Brimob di Tual, Tersangka Sudah Ditahan
Nadiem Makarim Serukan Anak Muda Tak Putus Asa dengan Indonesia di Tengah Sidang Korupsi
Ketua BEM UGM Laporkan Teror Anonim Usai Kritik Pemerintah
Dasco Minta Pemerintah Tunda Rencana Impor 105 Ribu Pick Up India