Obsesi pada kampus elit juga menciptakan beban psikologis yang berat. Coba bandingkan dengan Finlandia. Di sana, sekolah terbaik ya yang paling dekat dengan rumah, karena kualitas pendidikan mereka merata. Lain cerita di sini. Seorang siswa yang diterima di jurusan akreditasi Unggul di kampus lapis kedua, bisa saja merasa dirinya 'gagal' hanya karena namanya tak setenar kampus papan atas.
Pengejaran gengsi ini seringkali membutakan hal-hal yang lebih substansial. Misalnya, akreditasi prodi, kurikulum yang update, atau jaringan industri yang dimiliki kampus. Kebutaan ini, jujur saja, dipicu juga oleh praktik di lapangan kerja. Banyak HRD yang masih menjadikan nama almamater sebagai filter utama cara yang dianggap lebih praktis ketimbang menilai portofolio keterampilan calon karyawan.
Tanpa ada perubahan dari sisi perekrutan ini, sulit mengharapkan kegilaan pada bimbel dan kampus ternama akan mereda.
Kita perlu memutar haluan. Lolos PTN harusnya dilihat sebagai garis start, bukan finish. Orang tua dan guru punya peran besar untuk membangun citra diri anak berdasarkan kompetensi dan kemampuan adaptasinya, bukan sekadar label almamater.
Kalau ketergantungan pada bimbel terus dibiarkan, universitas-universitas terbaik kita hanya akan diisi oleh para jagoan hafalan pola. Mereka mungkin ahli dalam ujian, tetapi akan mudah tersesat ketika dihadapkan pada kompleksitas masalah nyata yang solusinya tidak pernah tersedia di lembar jawaban komputer. Dan itu, tentu saja, merupakan kerugian bagi semua pihak.

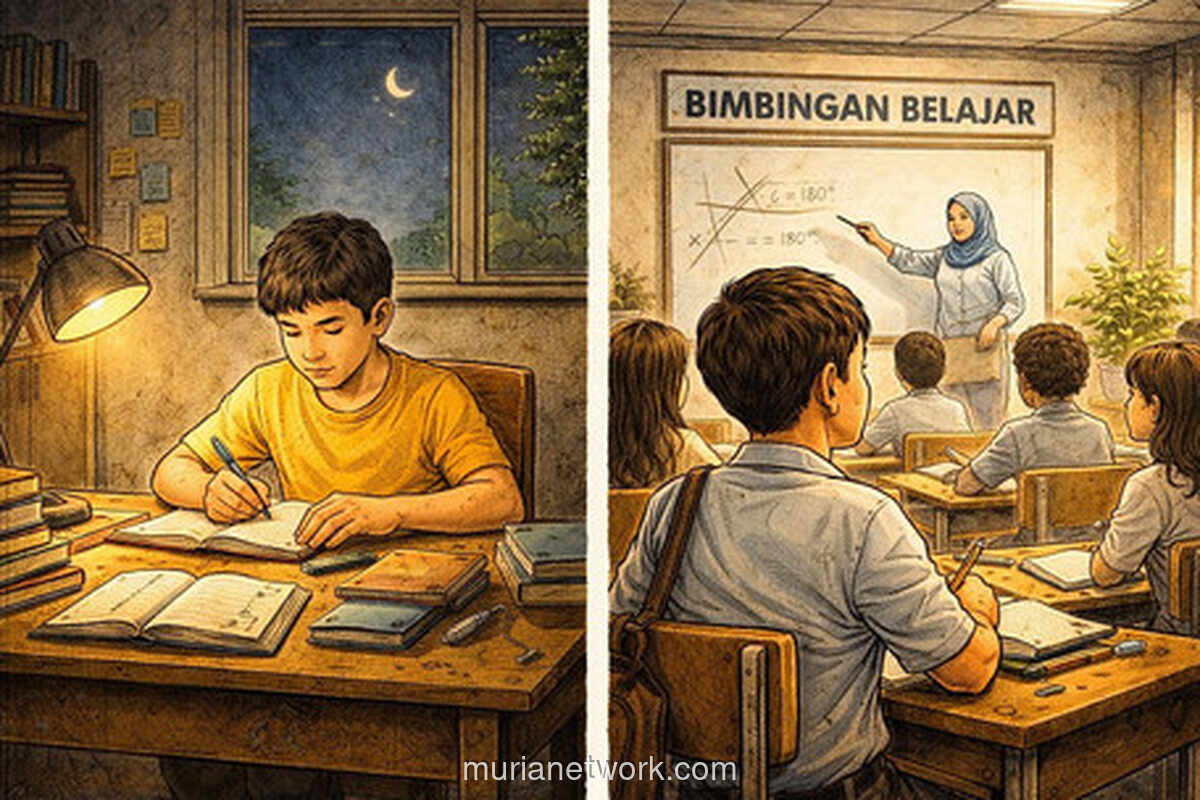









Artikel Terkait
Dari Balik Layar: Seorang Penulis Menjawab Skeptisisme dengan Kata sebagai Warisan
Apple Siapkan Skenario Suksesi, John Ternus Disebut Calon Pengganti Tim Cook
Indonesia Bergerak dari Soft Love ke Hard Love dalam Aturan Main AI
Jantung Tak Pernah Berbohong: Kenali 8 Sinyal Tubuh Sebelum Henti Jantung Mendadak