Sejarah kertas ternyata punya cerita yang panjang. Meski jejak arkeologis menunjukkan keberadaannya sejak abad kedua sebelum masehi, sosok yang kerap disebut sebagai penemunya adalah Cai Lun. Dia adalah seorang pejabat di masa Dinasti Han Timur, yang secara resmi mengumumkan penemuan ini di Lei-Yang, Tiongkok, tepatnya pada tahun 105 masehi.
Rahasia pembuatan kertas dijaga ketat oleh bangsa Tiongkok. Butuh waktu berabad-abad lamanya sebelum teknologi ini akhirnya merembet ke Jepang, lalu ke Timur Tengah, dan akhirnya sampai ke Eropa. Baru pada abad ke-8, pabrik kertas pertama di benua Eropa berdiri di Spanyol.
Perlahan, produksi kertas mulai meluas. Inggris, misalnya, baru memulai produksi besar-besaran di akhir abad ke-15. Sementara di Amerika Serikat, pabrik pertamanya baru didirikan di Pennsylvania pada tahun 1890. Sebelum kertas ditemukan, bayangkan betapa repotnya. Karya sastra, catatan filsafat, hingga tulisan akademik harus ditorehkan di media yang ada: kulit binatang, batang pohon, batu, bahkan daun lontar yang digunakan untuk naskah-naskah Melayu kuno.
Evolusi Pembelajaran
Keterbatasan media tulis itu sama sekali tidak mematahkan semangat para pencari ilmu zaman dulu. Mereka punya cara lain: kekuatan penuturan lisan. Itulah mengapa pertemuan langsung antara guru dan murid menjadi satu-satunya jalan untuk menimba ilmu.
Lihat saja para filsuf Yunani abad ke-6 SM, seperti Thales atau Anaximander. Mereka rela menempuh perjalanan ribuan kilometer, menghabiskan ratusan hari, hanya untuk belajar langsung pada para bijak di pusat peradaban seperti Babilonia atau Mesir. Perjalanan seperti itu jelas butuh tekad baja, fisik kuat, dan bekal yang cukup. Makanya, wajar jika seorang guru hanya punya segelintir murid. Ilmu diajarkan hanya pada orang-orang pilihan.
Memasuki abad ke-8 dan seterusnya, hingga awal tahun 2000-an, budaya mencatat mulai berkembang pesat. Ini sejalan dengan penemuan kertas, tinta, dan mesin cetak. Di era ini, seorang pembelajar mengandalkan kekuatan membaca, menghafal, menulis, dan menganalisis.
Kita mengenal Imam Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam, yang konon hafal 300.000 hadits beserta sanad dan matannya. Bahkan ada yang menyebut angka 500.000. Karya monumentalnya, Ihya Ulumuddin, dalam versi aslinya terdiri dari 12 jilid tebal. Ini menunjukkan kemampuan baca-tulis yang luar biasa.
Tradisi serupa terjadi hampir pada semua ilmuwan besar, baik di Timur maupun Barat. Di era itu, menjadi pintar berarti memiliki kekuatan untuk meneliti karya-karya besar berjilid-jilid, lalu menganalisis dan menuliskannya kembali. Ilmu ada di dalam kepala, bukan sekadar di buku. Seperti pepatah pesantren, 'al-'ilmu fish-shudur laisa fish-thurur'. Imam Ali RA juga pernah berpesan, 'ikatlah ilmu dengan tulisan'.
Saya masih ingat, tahun 1986 saat saya kuliah tingkat satu. Seorang dosen fisika mengajar tanpa membawa buku sama sekali. Dengan kapur di tangan, ia menuliskan penjelasannya di papan tulis secara rapi dan sistematis. Tugas kamilah, para mahasiswa, untuk menyalinnya dengan teliti. Saat itu, guru adalah sumber ilmu utama. Murid yang pintar adalah yang rajin membaca dan menulis.
Semuanya berubah di awal tahun 2000-an. Revolusi teknologi informasi meledak. Internet mulai masuk kampus, dunia terhubung, dan informasi terkumpul di dunia maya. Mesin pencari seperti Yahoo dan Google menjadi gerbang ilmu baru. Jurnal ilmiah dan textbook dalam bentuk e-book bisa diakses dengan lebih mudah, kadang meski harus 'dibobol' dulu.
Hirarki pengetahuan pun berubah. Dosen dan mahasiswa bisa 'balapan' mencari informasi. Siapa yang jago memasukkan kata kunci di mesin pencari, dialah yang lebih dulu dapat ilmu. Kemampuan membaca tetap penting, tapi sekarang untuk menelusuri dan menyaring lautan informasi yang tersedia.
Kini, kita menghadapi babak baru: era kecerdasan buatan atau AI. Mesin ini bisa menyimpan dan memproses jutaan data, menjawab pertanyaan rumit dalam hitungan detik. Lebih dari itu, AI bisa menuliskan puisi, menyusun artikel ilmiah, hingga membuatkan pidato. Modal utamanya cuma satu: kejelasan prompt.
Maka, skill yang dibutuhkan seorang pembelajar di era ini bergeser. Bukan lagi sekadar pandai membaca, tapi pandai bertanya dan merangkai perintah untuk AI. Kalau dulu banyak pelatihan menulis, sekarang marak pelatihan membuat prompt.
Evolusi inilah yang bikin banyak pegiat pendidikan was-was. Mereka berada di persimpangan. Peran guru dan dosen dikhawatirkan akan diambil alih AI. Faktanya, di beberapa kampus di luar negeri, AI sudah mulai masuk kelas. Dan yang bikin gregetan, penyampaian materinya terkadang lebih sistematis ketimbang dosen yang kurang persiapan.
Ini dianggap sebagai ancaman serius, terutama bagi pendidikan tinggi. Banyak kampus kemudian kalang kabut mendaur ulang kurikulum dan metode pembelajaran agar tetap relevan. Lantas, perlukah kita khawatir?
Esensi Pendidikan
Sebelum AI menjadi buah bibir, kita sudah lebih dulu akrab dengan robot. Robot modern pertama, Unimate, dibuat tahun 1954 untuk keperluan industri. Dari sana, perkembangannya makin pesat. Robot diciptakan untuk mengerjakan tugas berulang agar lebih akurat dan minim kesalahan.
Seiring kemajuan komputer dan informatika, robot jadi makin 'pintar'. Mereka mulai bisa berinteraksi dengan lingkungan dan mengambil keputusan sederhana. Kini, di era AI, hadirlah robot humanoid yang menyerupai cara berpikir manusia. Mereka dipakai di rumah sakit, industri jasa, dan ya, di dunia pendidikan.
Dengan aplikasi AI seperti Gemini atau DeepSeek, produksi karya akademik yang dulu jadi otoritas eksklusif ilmuwan, kini bisa dihasilkan mesin. Ini sekaligus ancaman dan peluang. Lalu bagaimana kita harus menyikapinya?
Pertama, kita perlu sadar. Menyadari bahwa ada pergeseran tujuan dari teknologi. Dari yang awalnya untuk memudahkan manusia, kini cenderung ingin menggantikan manusia sepenuhnya. Alasannya klasik: manusia dianggap kurang efisien dan produktif. Di balik ini, ada logika kapitalisme yang mengutamakan keuntungan, seringkali mengabaikan aspek kemanusiaan.
Nah, di titik inilah pendidikan tinggi harus punya kesadaran dan keberanian untuk mengarahkan ulang pengembangan teknologi. Kembali ke khittahnya: untuk solusi dan kesejahteraan manusia, bukan sekadar memuaskan nafsu kapital.
Kedua, manusia punya keunggulan yang tak akan pernah bisa direplikasi mesin. Robot mungkin bisa menggantikan fungsi raga dan otak kita mereka lebih kuat dan cepat menghitung. Tapi manusia punya hati, tempat mengolah rasa dan kebijaksanaan.
AI tak akan punya algoritma untuk itu. Karena itu adalah paket lengkap ciptaan Tuhan, yang di dalamnya ada ruh. Pendidikan yang sejati, karena itu, harus tetap melatih olah rasa. Tanpanya, kita hanya akan menghasilkan manusia tanggung: bentuknya manusia, tapi kosong rasa dan kebijaksanaannya.
Jadi, jawabannya, kita tak perlu panik. Dengan kesadaran akan tujuan pendidikan yang sebenarnya, serta komitmen untuk tetap memanusiakan manusia, pendidikan tinggi akan tetap punya tempat. Yang penting, rileks saja menyikapinya. Insya Allah, pendidikan yang berdampak dan bermanfaat bukan sekadar slogan.
Begitukah, Pak Menteri?
Aceng Hidayat. Dekan Sekolah Vokasi IPB.

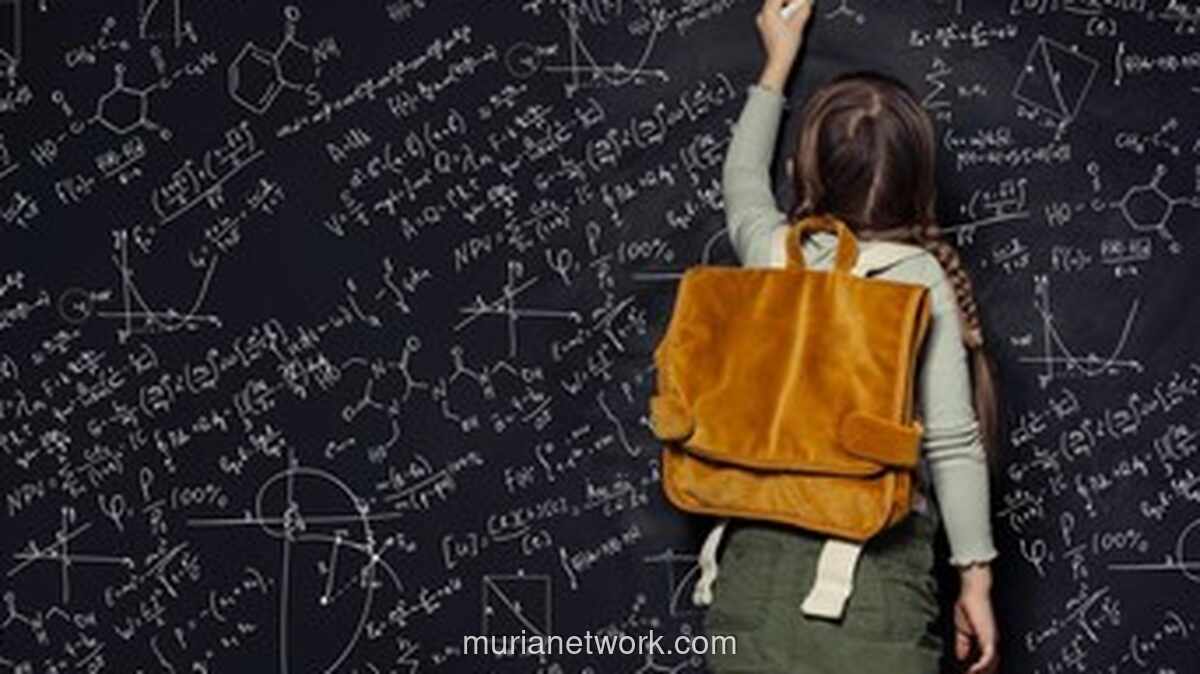









Artikel Terkait
Ketua MK Yakin Adies Kadir Bisa Independen Pasca Mundur dari Golkar
Mantan Stafsus Nadiem Baru Tahu Gaji Konsultan Chromebook Lebih Tinggi di Sidang Korupsi
Normalisasi Kali Ciliwung Kembali Digiatkan, Pembongkaran Bangunan di Bantaran Dimulai
Pengadilan AS Vonis Seumur Hidup untuk Pelaku Rencana Pembunuhan Donald Trump