Bayangkan sebuah dunia yang tidak pernah tunggal. Itulah inti dari ungkapan Zapatista yang terkenal: "a world where many worlds fit." Ungkapan ini menegaskan bahwa ada begitu banyak cara hidup, begitu banyak pengetahuan, dan begitu banyak relasi dengan alam yang sah untuk tumbuh berdampingan.
Namun begitu, dunia modern justru sering memaksakan satu cara berpikir dan satu model pembangunan untuk semua orang. Ironisnya, rezim iklim global saat ini pun terjebak dalam logika yang sama. Alih-alih membuka ruang bagi banyak dunia untuk menentukan jalannya sendiri, mereka terus memaksakan satu resep solusi untuk semua.
COP 30 di Belém, sekali lagi, menghadirkan janji-janji yang sudah tak asing lagi. Ekonomi hijau, net zero, pembangunan berkelanjutan semua jargon itu terus diulang. Tapi sementara itu, suhu bumi tak kunjung turun. Dunia terlihat sibuk menyelamatkan planet, tapi kenyataannya, kita justru mempercepat pemanasannya.
Banyak pihak masih percaya bahwa krisis iklim bisa diselesaikan dengan standar teknis, indikator kinerja, dan model-model rapi di atas kertas. Seakan-akan ini cuma soal administrasi, bukan persoalan hidup dan mati. Padahal, perubahan cuaca, ketahanan pangan, dan pengelolaan lahan punya wajah yang berbeda bagi setiap komunitas. Ketika semua dipaksa mengikuti satu formula, yang hilang adalah kebijaksanaan lokal yang justru punya kemampuan adaptasi lebih cepat.
Di sisi lain, apa yang disebut ekonomi hijau juga membawa risiko kolonialisme versi baru. Banyak proyek konservasi berkedok penyelamatan bumi justru meminggirkan masyarakat adat dan petani dari tanah yang telah mereka rawat turun-temurun. Hutan dan tanah tiba-tiba berubah jadi "aset karbon" global, sementara komunitas yang paling menjaga alam malah harus meminta izin untuk mengakses ruang hidupnya sendiri. Jika begini caranya, yang berubah cuma warnanya dari kolonialisme cokelat menjadi kolonialisme hijau.
Salah satu penyebabnya adalah cara kerja rezim iklim global yang masih mengandalkan logika pasar. Ambil contoh mekanisme pasar karbon. Sistem ini memungkinkan perusahaan besar membeli "kredit karbon" dari proyek hutan di negara-negara Selatan, sambil tetap mempertahankan model bisnis intensif emisi di negara-negara Utara. Intinya, mereka masih boleh mencemari, asal bayar.
Sementara itu, komunitas lokal justru kehilangan ruang hidup karena wilayahnya dijadikan "penyerap karbon dunia." Dalam banyak kasus, proses ini berubah menjadi green grabbing: perampasan ruang hidup yang dibungkus dalih konservasi. Hutan, tanah, bahkan udara diklaim sebagai aset hijau untuk kepentingan pasar global.
Skema pembiayaan hijau pun tak kalah rumit. Dana "transisi energi" dari negara maju sering hadir sebagai pinjaman atau investasi bersyarat. Akibatnya, negara-negara berkembang tetap bergantung pada teknologi dan standar yang ditetapkan dari luar. Tambang nikel, kobalt, dan litium menggeliat demi industri hijau, tapi dampaknya ditanggung masyarakat yang jauh dari ruang ber-AC konferensi iklim.
Di sinilah pemikiran dekolonial Arturo Escobar menjadi relevan. Menurutnya, akar krisis ekologis bukan cuma soal teknologi atau emisi, tapi cara kita memandang dunia.
Dunia modern terjebak dalam logika "one-world world" sebuah dunia tunggal yang menyatakan hanya ada satu cara hidup yang benar: efisien, produktif, dan bisa dijual.










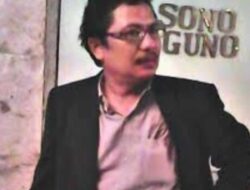
Artikel Terkait
Polisi dan Warga Megamendung Gelar Doa Bersama untuk Jaga Keamanan
Sekolah Rakyat Prabowo Tembus 104 Titik, Targetkan 200 Gedung pada 2027
Angkot Ugal-ugalan Tabrak Ojol di Bogor, Sopir Kabur Usai Serempet Korban
Korban Tewas Bencana Sumatera Tembus 1.182 Jiwa, Ratusan Ribu Masih Mengungsi