Feodalisme pendidikan ini makin menjadi-jadi karena kurikulum sering diperlakukan bagai dogma. Guru cuma diposisikan sebagai pelaksana teknis, bukan sebagai intelektual publik. Murid dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem, bukan diajak untuk merundingkan sistem itu.
Dalam situasi seperti ini, pendidikan kehilangan daya pembebasannya. Deliberative Curriculum Education hadir sebagai kritik langsung. Ia menempatkan dialog sebagai fondasi pedagogis, bukan sebagai hiasan atau metode tambahan semata.
Kelas tidak lagi dipahami sebagai ruang transmisi satu arah, melainkan sebagai arena komunikasi setara. Di sini, otoritas diuji oleh kekuatan argumen, bukan dilanggengkan hanya karena jabatan.
Pemikiran Neil Postman juga menemukan relevansinya di sini. Dia pernah bicara soal hilangnya tujuan moral dari sekolah. Sekolah yang hanya mengejar efisiensi dan capaian teknis akan kehilangan jiwa dan makna publiknya.
Pendidikan deliberatif justru berusaha mengembalikan sekolah sebagai ruang pembentukan nilai. Tapi nilainya itu lahir dari perdebatan yang sehat, bukan dari indoktrinasi.
Dalam pendidikan demokratis model begini, konflik tidak dihindari. Ia dikelola. Perbedaan pendapat tidak dibungkam, melainkan difasilitasi. Murid belajar satu hal penting: demokrasi bukan soal selalu sepakat, tapi tentang bagaimana caranya tidak sepakat secara bermartabat.
Jadi, meruntuhkan feodalisme pendidikan bukan berarti menghilangkan semua struktur. Ini tentang mengganti sumber legitimasi. Otoritas tidak lagi bersumber dari posisi atau titel, tetapi dari kualitas argumen dan integritas moral seseorang.
Mencari Poros di Tengah Kerumitan
Kalau kita lihat sekilas, pendidikan Indonesia hari ini seperti tenggelam dalam tumpukan agenda. Literasi, numerasi, pendidikan karakter, kompetensi global semuanya penting. Tapi semuanya berjalan tanpa poros yang jelas, tanpa sumbu pemersatu.
Deliberative Curriculum Education mengajukan satu usul: jadikan pendidikan politik sebagai porosnya. Tapi tunggu dulu, pendidikan politik di sini bukan berarti indoktrinasi ideologi negara. Ini tentang pendidikan bagaimana kekuasaan bekerja dan bagaimana warga bisa mengontrolnya. Tanpa pemahaman ini, demokrasi cuma akan dipahami secara dangkal sebagai ritual lima tahunan ke bilik suara.
Nah, di sinilah seharusnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memainkan peran sentral. Namun kenyataannya, PPKn justru terjebak jadi mata pelajaran normatif. Penuh definisi, hafalan, tapi kehilangan daya kritisnya. Pancasila diajarkan sebagai mantra yang harus dihafal, bukan sebagai pisau analisis untuk membedah realitas sosial-politik kita.
Pendekatan deliberatif bisa mentransformasi PPKn secara radikal. Bayangkan kelas menjadi ruang simulasi demokrasi. Murid membahas kebijakan publik yang nyata, menguji argumen moral, memahami konflik kepentingan yang konkret. Politik jadi tidak abstrak lagi. Ia hidup dalam pengalaman belajar sehari-hari.
Dengan cara ini, pendidikan politik melampaui loyalitas simbolik. Ia bergerak menuju literasi kekuasaan. Murid belajar mengenali manipulasi, memahami ketidakadilan yang terstruktur, dan mengartikulasikan kepentingannya dengan nalar yang tajam.
Tapi dekonstruksi sistem ini menuntut satu hal: keberanian negara untuk memandang pendidikan sebagai proyek demokrasi jangka panjang. Bukan sekadar proyek pembangunan yang diukur dari angka-angka semata. Tanpa keberanian itu, PPKn akan tetap jadi pelajaran yang penting di kertas, tapi tidak berpengaruh dalam kehidupan nyata.
Di Mana Posisinya?
Jadi, di mana sebenarnya Deliberative Curriculum Education ini berdiri? Ia berada di persimpangan yang menarik. Dari Anderson, ia mengambil semangat tentang komunitas terbayang dan pentingnya narasi bersama. Tapi ia menolak narasi yang kaku dan final.
Dari Freire, ia menyerap semangat pembebasan dan kritik terhadap relasi kuasa yang timpang. Moralitas, dalam pandangan ini, selalu bersifat sosial dan politis. Pendidikan deliberatif menjadikan konflik moral sebagai bahan bakar pembelajaran, bukan sebagai hal tabu.
Dari Postman, ada peringatan tentang hilangnya tujuan besar pendidikan. Pendidikan deliberatif menolak kolektivitas yang dipaksakan. Sebaliknya, kebersamaan dibangun melalui kesepakatan yang lahir dari dialog, bukan dari paksaan ideologis.
Dalam dialog dengan semua pemikiran kritis itu, Deliberative Curriculum Education pada akhirnya menegaskan satu hal: pendidikan adalah praktik pembebasan. Tujuannya bukan cuma membentuk pribadi yang bermoral, tetapi juga warga negara yang mampu berpartisipasi secara sadar dan kritis dalam ruang publik.
Di tengah krisis demokrasi dan kelelahan institusi pendidikan kita, pendekatan ini menawarkan arah. Sebuah arah yang tegas: pendidikan harus kembali menjadi ruang latihan untuk demokrasi. Bukan demokrasi prosedural yang kering, tapi demokrasi deliberatif yang hidup, bernafas, dan penuh pergulatan.
Di sanalah tempatnya. Sebagai sebuah imajinasi pendidikan yang berani, politis, dan sungguh-sungguh mendesak untuk masa depan Indonesia.

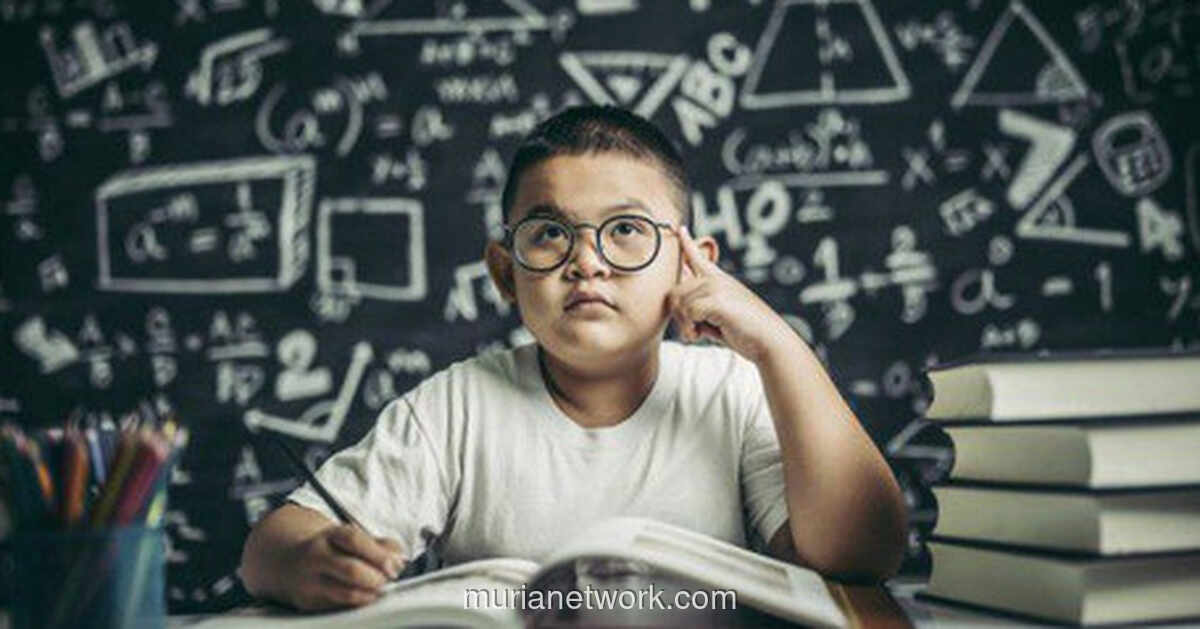









Artikel Terkait
Brimob Tembak Warga di Tambang Ilegal Bombana, Empat Personel Diperiksa Propam
Iran Padamkan Internet, Tuding AS dan Israel Picu Kerusuhan dari Aksi Damai
Dentuman Kembali di Aleppo, 22 Nyawa Melayang dalam Bentrokan
Gaji Dua Digit: Simbol Prestasi atau Jerat Kecemasan?