Pendidikan di Indonesia memang kerap dibicarakan dengan penuh harapan. Tapi, coba lihat praktiknya. Semua serba teknokratis. Setiap ganti kebijakan, muncul istilah baru, akronim baru, janji pembaruan yang mentereng. Ujung-ujungnya? Hanya jadi tumpukan dokumen dan laporan yang memenuhi rak.
Di ruang kelas, perubahan yang dijanjikan itu sering kali tak lebih dari ganti format. Cara berpikir? Masih sama. Relasi kuasa antara guru dan murid? Tetap kaku, bahkan beku. Sekolah terus berjalan, ya. Tapi mau dibawa ke mana sebenarnya? Apakah tujuannya membentuk warga negara yang kritis, atau sekadar mencetak tenaga kerja yang patuh dan mudah beradaptasi dengan pasar?
Pertanyaan itu makin penting di tengah situasi politik kita sekarang. Polarisasi, wacana publik yang dangkal, rasionalitas demokratis yang melemah. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan seharusnya jadi benteng terakhir untuk menumbuhkan nalar kritis. Sayangnya, kenyataannya justru berkebalikan.
Alih-alih jadi ruang diskusi, sekolah sering berubah jadi ruang netral palsu. Konflik gagasan dihindari atas nama ketertiban. Pertanyaan-pertanyaan politik diredam demi stabilitas. Akibatnya, demokrasi diajarkan sebagai sistem yang sudah jadi, sempurna, tak perlu diutak-atik lagi. Bukan sebagai proses hidup yang penuh perdebatan dan pergulatan.
Di sinilah krisis orientasi itu muncul. Pendidikan kita terlalu sibuk mengurusi "bagaimana cara mengajar", sampai lupa menjawab pertanyaan paling mendasar: "untuk apa sebenarnya kita mendidik?"
Tanpa visi politik yang jelas, pendidikan dengan mudah direduksi jadi proyek manajerial belaka. Ia tunduk pada logika efisiensi dan tuntutan pasar. Padahal, di balik setiap kurikulum, selalu tersembunyi asumsi tertentu tentang manusia, tentang masyarakat, dan tentang kekuasaan.
Nah, gagasan Deliberative Curriculum Education lahir dari kegelisahan ini. Ini bukan cuma metode belajar aktif biasa. Lebih dari itu, ini adalah sebuah imajinasi tentang sistem pendidikan yang menempatkan deliberasi perdebatan rasional, dialog setara, pengambilan keputusan bersama sebagai jantung dari proses belajar.
Dalam kerangka ini, pendidikan dipahami sebagai proyek politik dalam arti yang paling mulia: membentuk warga negara yang mampu berpikir, berselisih paham, dan akhirnya bersepakat, semua dilakukan dengan penuh martabat.
Membayangkan (Kembali) Sebuah Bangsa
Dulu, Benedict Anderson punya istilah menarik: "imagined communities" atau komunitas terbayang. Bangsa, katanya, adalah komunitas yang dibayangkan karena anggotanya tak mungkin saling kenal semua. Kesadaran sebagai satu bangsa itu hidup lewat simbol, bahasa, dan narasi yang diproduksi secara sistematis oleh institusi-institusi modern.
Dan pendidikan, dalam hal ini, adalah mesin utamanya. Mesin yang membentuk imajinasi kolektif kita tentang siapa itu "kita" dan siapa "yang lain".
Masalahnya, selama ini pendidikan Indonesia membayangkan bangsa sebagai sesuatu yang sudah final, selesai. Narasi kebangsaan disajikan bagai kebenaran tunggal yang wajib diterima. Bukan sebagai konstruksi sejarah yang lahir dari konflik, kompromi, dan perdebatan panjang.
Sekolah jadi ruang untuk mensakralkan nasionalisme, bukan ruang untuk merefleksikannya secara kritis. Alhasil, rasa kebangsaan itu terasa jauh dari kehidupan nyata. Di sisi lain, ia jadi mudah sekali dimanipulasi untuk kepentingan politik praktis.
Dalam imajinasi yang beku ini, perbedaan sering dilihat sebagai ancaman. Bukan sebagai sumber belajar yang berharga. Kurikulum pun cenderung menghindari ketegangan sosial-politik yang nyata. Seolah-olah harmoni bisa dijaga dengan menyapu konflik dari bawah karpet ruang kelas. Padahal, bangsa justru dibentuk melalui kemampuan warganya mengelola perbedaan secara rasional dan adil.
Deliberative Curriculum Education menolak logika kebangsaan yang steril semacam itu. Gagasan ini memandang sekolah sebagai ruang publik awal. Tempat di mana warga negara muda belajar membayangkan bangsanya melalui perdebatan yang terkelola, bukan melalui indoktrinasi satu arah. Kebangsaan tidak lagi cuma diajarkan sebagai slogan, tetapi dirundingkan sebagai pengalaman bersama yang terus berubah.
Dengan konfigurasi seperti ini, sejarah tak lagi dipelajari sebagai dongeng heroik yang disucikan. Melainkan sebagai medan tarik-menarik kepentingan dan ideologi. Identitas nasional tidak dipaksakan sebagai keseragaman, tapi dibangun lewat dialog antar pengalaman sosial yang beragam. Murid tidak lagi disuruh menghafal arti persatuan, tetapi dilatih untuk memproduksi persatuan itu sendiri.
Masyarakat berbayang yang dibentuk oleh pendidikan deliberatif adalah komunitas yang sadar akan keterbatasannya sendiri. Ia tidak mengklaim kebenaran tunggal. Sebaliknya, ia membuka ruang bagi negosiasi makna. Kesatuan lahir bukan dari penyeragaman, melainkan dari kesediaan untuk mendengar dan berargumen.
Di Indonesia yang plural dan rapuh oleh politik identitas, imajinasi kebangsaan semacam ini bukan lagi sekadar pilihan. Ini kebutuhan mendesak. Tanpa pendidikan yang deliberatif, bangsa akan terus dibayangkan secara sempit mudah dibelah, gampang diprovokasi, dan miskin daya refleksi.
Meruntuhkan Feodalisme di Ruang Kelas
Kritik Paulo Freire terhadap "pendidikan gaya bank" sudah sangat terkenal. Pendidikan yang menjadikan murid sebagai bejana kosong yang hanya diisi guru adalah instrumen penindasan. Ia melanggengkan ketimpangan kuasa.
Di Indonesia, kritik ini masih terasa sangat relevan. Sekolah sering kali masih memelihara struktur feodal yang rapi dan nyaris tak tergugat. Relasi guru-murid kerap mencerminkan relasi atasan-bawahan. Bertanya kritis bisa dianggap membangkang. Sementara kepatuhan tanpa reserve dipuja sebagai sikap terpuji.
Ini paradoks yang memilukan. Demokrasi diajarkan di buku teks, tapi justru dilarang dalam praktik sehari-hari di kelas. Sekolah jadi institusi yang bicara tentang kebebasan, tetapi ketakutan pada kebebasan berpikir.
Feodalisme pendidikan ini makin menjadi-jadi karena kurikulum sering diperlakukan bagai dogma. Guru cuma diposisikan sebagai pelaksana teknis, bukan sebagai intelektual publik. Murid dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem, bukan diajak untuk merundingkan sistem itu.
Dalam situasi seperti ini, pendidikan kehilangan daya pembebasannya. Deliberative Curriculum Education hadir sebagai kritik langsung. Ia menempatkan dialog sebagai fondasi pedagogis, bukan sebagai hiasan atau metode tambahan semata.
Kelas tidak lagi dipahami sebagai ruang transmisi satu arah, melainkan sebagai arena komunikasi setara. Di sini, otoritas diuji oleh kekuatan argumen, bukan dilanggengkan hanya karena jabatan.
Pemikiran Neil Postman juga menemukan relevansinya di sini. Dia pernah bicara soal hilangnya tujuan moral dari sekolah. Sekolah yang hanya mengejar efisiensi dan capaian teknis akan kehilangan jiwa dan makna publiknya.
Sekolah yang hanya mengejar efisiensi dan capaian teknis akan kehilangan makna publiknya.
Pendidikan deliberatif justru berusaha mengembalikan sekolah sebagai ruang pembentukan nilai. Tapi nilainya itu lahir dari perdebatan yang sehat, bukan dari indoktrinasi.
Dalam pendidikan demokratis model begini, konflik tidak dihindari. Ia dikelola. Perbedaan pendapat tidak dibungkam, melainkan difasilitasi. Murid belajar satu hal penting: demokrasi bukan soal selalu sepakat, tapi tentang bagaimana caranya tidak sepakat secara bermartabat.
Jadi, meruntuhkan feodalisme pendidikan bukan berarti menghilangkan semua struktur. Ini tentang mengganti sumber legitimasi. Otoritas tidak lagi bersumber dari posisi atau titel, tetapi dari kualitas argumen dan integritas moral seseorang.
Mencari Poros di Tengah Kerumitan
Kalau kita lihat sekilas, pendidikan Indonesia hari ini seperti tenggelam dalam tumpukan agenda. Literasi, numerasi, pendidikan karakter, kompetensi global semuanya penting. Tapi semuanya berjalan tanpa poros yang jelas, tanpa sumbu pemersatu.
Deliberative Curriculum Education mengajukan satu usul: jadikan pendidikan politik sebagai porosnya. Tapi tunggu dulu, pendidikan politik di sini bukan berarti indoktrinasi ideologi negara. Ini tentang pendidikan bagaimana kekuasaan bekerja dan bagaimana warga bisa mengontrolnya. Tanpa pemahaman ini, demokrasi cuma akan dipahami secara dangkal sebagai ritual lima tahunan ke bilik suara.
Nah, di sinilah seharusnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memainkan peran sentral. Namun kenyataannya, PPKn justru terjebak jadi mata pelajaran normatif. Penuh definisi, hafalan, tapi kehilangan daya kritisnya. Pancasila diajarkan sebagai mantra yang harus dihafal, bukan sebagai pisau analisis untuk membedah realitas sosial-politik kita.
Pendekatan deliberatif bisa mentransformasi PPKn secara radikal. Bayangkan kelas menjadi ruang simulasi demokrasi. Murid membahas kebijakan publik yang nyata, menguji argumen moral, memahami konflik kepentingan yang konkret. Politik jadi tidak abstrak lagi. Ia hidup dalam pengalaman belajar sehari-hari.
Dengan cara ini, pendidikan politik melampaui loyalitas simbolik. Ia bergerak menuju literasi kekuasaan. Murid belajar mengenali manipulasi, memahami ketidakadilan yang terstruktur, dan mengartikulasikan kepentingannya dengan nalar yang tajam.
Tapi dekonstruksi sistem ini menuntut satu hal: keberanian negara untuk memandang pendidikan sebagai proyek demokrasi jangka panjang. Bukan sekadar proyek pembangunan yang diukur dari angka-angka semata. Tanpa keberanian itu, PPKn akan tetap jadi pelajaran yang penting di kertas, tapi tidak berpengaruh dalam kehidupan nyata.
Di Mana Posisinya?
Jadi, di mana sebenarnya Deliberative Curriculum Education ini berdiri? Ia berada di persimpangan yang menarik. Dari Anderson, ia mengambil semangat tentang komunitas terbayang dan pentingnya narasi bersama. Tapi ia menolak narasi yang kaku dan final.
Dari Freire, ia menyerap semangat pembebasan dan kritik terhadap relasi kuasa yang timpang. Moralitas, dalam pandangan ini, selalu bersifat sosial dan politis. Pendidikan deliberatif menjadikan konflik moral sebagai bahan bakar pembelajaran, bukan sebagai hal tabu.
Dari Postman, ada peringatan tentang hilangnya tujuan besar pendidikan. Pendidikan deliberatif menolak kolektivitas yang dipaksakan. Sebaliknya, kebersamaan dibangun melalui kesepakatan yang lahir dari dialog, bukan dari paksaan ideologis.
Dalam dialog dengan semua pemikiran kritis itu, Deliberative Curriculum Education pada akhirnya menegaskan satu hal: pendidikan adalah praktik pembebasan. Tujuannya bukan cuma membentuk pribadi yang bermoral, tetapi juga warga negara yang mampu berpartisipasi secara sadar dan kritis dalam ruang publik.
Di tengah krisis demokrasi dan kelelahan institusi pendidikan kita, pendekatan ini menawarkan arah. Sebuah arah yang tegas: pendidikan harus kembali menjadi ruang latihan untuk demokrasi. Bukan demokrasi prosedural yang kering, tapi demokrasi deliberatif yang hidup, bernafas, dan penuh pergulatan.
Di sanalah tempatnya. Sebagai sebuah imajinasi pendidikan yang berani, politis, dan sungguh-sungguh mendesak untuk masa depan Indonesia.

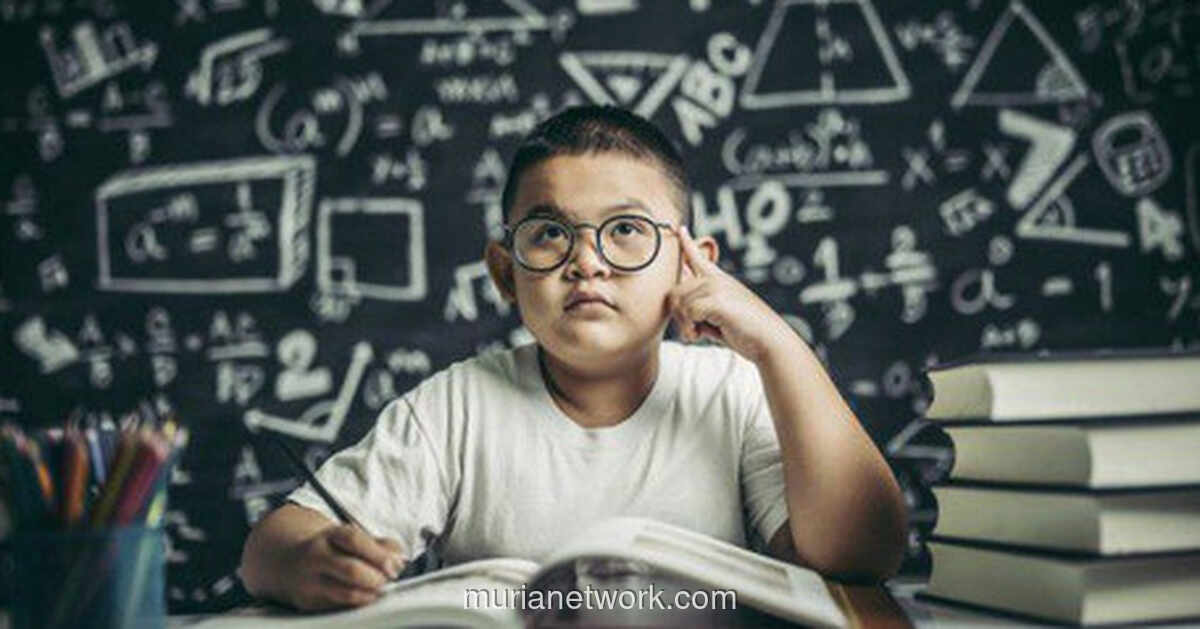









Artikel Terkait
Air Terjun Kali Jodoh di Pinrang: Pesona Alam dan Mitos Pencarian Jodoh yang Ramai Dikunjungi
Tiga Buronan KKB Yahukimo Dibawa ke Jayapura untuk Proses Hukum
Dasco Minta Pemerintah Tunda Rencana Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India
OSO Ungkap Kedekatan dengan Mahfud MD Berawal dari Persahabatan Lama dan Kesamaan Visi