Kita mungkin jarang memerhatikan font di spanduk atau baliho di jalan. Tapi coba lihat di kantor-kantor pemerintahan. Saat ada pejabat baru masuk, seringkali ada keinginan untuk mengubah tampilan visual mulai dari layout, margin, sampai jenis huruf yang dipakai.
Itu bukan sekadar soal selera. Penggunaan font pilihan sang pimpinan bisa jadi penanda loyalitas, sebuah cara untuk "mengiyakan" visi baru. Nantinya, sang pejabat bisa berujar, "Di era saya, pakai font ini karena yang lama boros kertas dan kurang rapi."
Simpelnya, ini soal penanda kekuasaan. Para pegawai pun lambat laun akan menganggap font era pimpinan lama sebagai sesuatu yang usang. Seperti pernah diungkapkan pemikir seperti Ludwig von Mises atau James Q. Wilson, birokrat memang punya kecenderungan menyukai hal-hal baru meski kadang itu hanya perubahan di permukaan.
Nah, persoalannya di mana?
Baik di AS maupun di Indonesia, simbol administratif seperti font bisa berubah jadi alat kekuasaan yang ideologis. Birokrat yang seharusnya netral tiba-tiba terjebak dalam perang simbol. Waktu dan energi yang seharusnya dipakai untuk melayani masyarakat, terkuras hanya untuk mengurusi format, margin, dan jenis huruf.
Konsekuensinya jelas: birokrasi jadi tidak produktif. Yang muncul malah semangat "era saya" yang individual, bukan "era kita" yang kolektif. Lebih parah lagi, hal remeh seperti pilihan font bisa jadi alat untuk menegakkan hierarki dan menghukum yang tidak patuh. Sungguh situasi yang berbahaya, karena fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan akhirnya terabaikan.

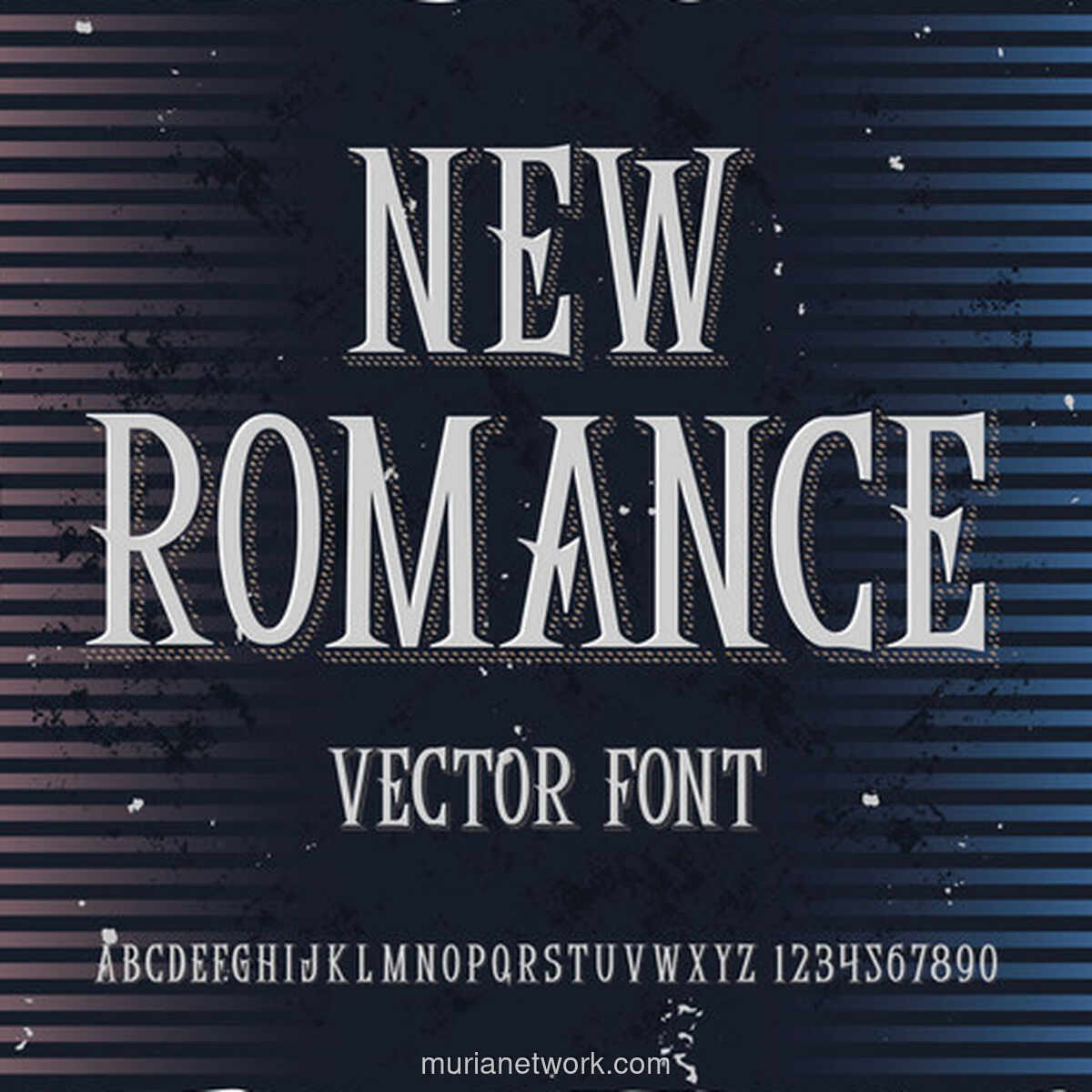









Artikel Terkait
Pernyataan Prabowo Soal Israel Viral, Ternyata Ada Syarat yang Terpotong
Gelombang Mundur di OJK dan BEI, Isu Free Float Diduga Jadi Pemicu
Kaesang Menangis di Panggung Rakernas, Janjikan PSI Akan Jadi Partai Besar
Botol Pink Kosong dan Misteri N2O dalam Kasus Lula Lahfah