Menyamakan keramahan dengan kesejahteraan adalah kekeliruan yang berbahaya. Rakyat kita punya budaya santun yang mengakar. Sejarah mencatat, bahkan di masa revolusi dulu, penduduk desa tetap menghormati tamu meski diri sendiri kekurangan.
Membaca senyum dan salam sebagai tanda bahwa semuanya baik-baik saja? Itu namanya kenaifan. Pemimpin seharusnya mampu menembus batas seremoni, bertanya apa yang sebenarnya tersembunyi di balik lambaian tangan itu. Jangan sampai justru ketulusan rakyat membuat yang berkuasa lengah.
Ketiga, Romantisasi yang Toksik
Ucapan “rakyat masih tegar” terduhnya simpatik, tapi hati-hati. Di baliknya ada narasi yang menormalisasi penderitaan. Seolah-olah rakyat yang diam dan sabar adalah kondisi ideal. Padahal, dengan melabeli korban sebagai “orang sabar”, beban pemulihan bisa bergeser dari pundak pemerintah ke pundak rakyat yang sedang terluka.
Ini jelas keliru. Tugas pemerintah adalah memastikan rakyat tak perlu bersabar terlalu lama dalam kesulitan. Kesabaran rakyat adalah ujian keimanan mereka, tapi kecepatan penanganan adalah ujian kinerja presiden. Dua hal ini jangan sampai dicampur aduk.
Keempat, Jarak dan Empati yang Hilang
Ketika seorang penguasa masih mengira-ngira perasaan rakyatnya, itu pertanda jarak yang menganga lebar. Jarak antara istana yang nyaman dengan tenda pengungsian yang lembap. Trauma pascabencana itu rumit dan sering tersembunyi, tidak bisa dipahami hanya lewat kunjungan protokoler beberapa jam.
Mengira-ngira ketegaran seseorang yang baru kehilangan segalanya adalah penyederhanaan yang kejam. Rakyat tidak butuh ditebak. Mereka butuh didengar dan dilihat secara nyata. Pernyataan “saya kira” justru mengungkapkan ketiadaan kepekaan terhadap luka yang mungkin tak terucap.
Pada akhirnya, mitigasi bencana menuntut kepastian. Bukan asumsi. Rakyat butuh pemimpin yang berkata, “Saya tahu kondisinya berat, dan ini langkah konkret kami,” bukan yang berujar, “Saya kira… saya kira…”
Mencampurkan perasaan subjektif dengan tugas negara bukanlah empati. Itu kegagalan membaca prioritas. Dan dalam situasi darurat, kegagalan seperti itu bisa berakibat fatal.






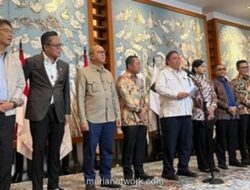




Artikel Terkait
Utusan AS dan Rusia Gelar Pembicaraan Rahasia di Florida, Bahas Jalan Damai Ukraina
Balita 4 Tahun di Cilacap Tewas Dibunuh dan Dilecehkan oleh Tetangga Sendiri
Serangan Udara di Gaza Tewaskan 28 Warga, Seperempatnya Anak-anak
Drama dan Kebaikan di Balik Sesaknya Gerbong KRL