Lampu-lampu kendaraan besar melaju cepat, menyisakan siluet seorang perempuan hamil yang berjalan sendirian di jalur Pantura. Malam itu, Sartika tokoh dalam film "Pangku" (2025) berjalan bukan karena ia ingin, melainkan karena hidup mendesaknya untuk terus bergerak. Dunia di sekelilingnya seperti tak peduli apakah ia sanggup mengejar atau tidak. Nafasnya berat, langkahnya pelan. Tatapannya kosong, seolah memikirkan hal yang jauh lebih dalam dari sekadar kata-kata yang sempat ia ucapkan di layar. Pada momen itu, ia bukan sekadar karakter. Ia mewakili jutaan perempuan yang terjebak di ruang antara: bukan miskin secara statistik, tapi tak pernah cukup aman untuk benar-benar hidup.
Fenomena "kopi pangku" yang diangkat film ini sebenarnya lebih dari sekadar catatan sosial yang eksotis. Ini adalah buah dari sistem ekonomi yang gagal membangun tangga bagi mereka yang paling membutuhkan. Sektor informal di Indonesia, mau tak mau, menjadi penampung bagi perempuan-perempuan yang tak punya akses ke pendidikan tinggi, modal usaha, atau jaringan profesional. Sebuah penelitian sosiologis tahun 2020 bahkan menyoroti bagaimana tubuh perempuan di ruang-ruang seperti ini perlahan berubah menjadi semacam bahasa transaksi. Bukan lagi tentang identitas atau aspirasi, melainkan alat tukar belaka.
Menurut data Badan Pusat Statistik 2023, sekitar 59% pekerja perempuan ada di sektor informal. Angka itu mungkin terasa dingin dan abstrak sampai kita meletakkan wajah Sartika di baliknya. Ia bekerja, tapi tak tercatat dalam regulasi ketenagakerjaan. Ia berkontribusi pada perputaran uang, tapi dianggap tak layak dapat jaminan sosial. Ia ada di mana-mana: di pasar, di pinggir jalan, di warung tapi nyaris tak diakui oleh negara.
Di sisi lain, sejarah kita justru dipenuhi nama-nama perempuan yang dielu-elukan. Sebut saja Cut Nyak Dien. Namanya menghiasi buku pelajaran, jalan raya, hingga patung. Tapi perayaan semacam itu rasanya lebih seperti penghormatan pada legenda, bukan pada warisan strategi perjuangannya. Cut Nyak Dien dulu memimpin dengan jaringan, strategi, dan negosiasi. Sekarang? Perempuan seperti Sartika cuma dapat slogan motivasi. Diberi teladan, tapi tanpa metode.
Memang, pemerintah punya segudang inisiatif untuk perempuan. Ada program kredit mikro, pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, dan bantuan sosial. Beberapa penelitian kebijakan mencatat bahwa ada perempuan yang berhasil keluar dari kemiskinan lewat akses permodalan komunitas. Tapi banyak juga evaluasi yang menunjukkan pola yang sama berulang: program cuma mentok di permukaan. Pelatihan diberikan, foto-foto diambil, laporan disusun lalu para perempuan itu kembali sendiri menghadapi pasar yang tak sabar, persaingan brutal, dan birokrasi yang berbelit.
Model pemberdayaan semacam ini ibarat rumah yang punya fondasi, tapi tanpa dinding. Kelihatannya seperti struktur, tapi tak bisa dihuni. Perempuan diberi arahan, tapi tanpa perlindungan. Dapat pelatihan, tapi tanpa jaminan pasar. Diberi modal awal, lalu dilepas begitu saja saat masalah datang. Akhirnya, banyak yang balik lagi ke jalur lama: jadi pekerja warung kopi pangku, buruh rumahan tanpa jaminan, atau malah pekerja migran di sektor berisiko tinggi.






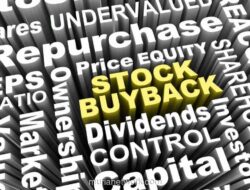




Artikel Terkait
Teh Hijau vs Air Lemon: Mana yang Lebih Baik untuk Kesehatan?
Hari ke-10 Ramadhan, Momentum Memperkuat Doa di Fase Penuh Rahmat
Dadang Berusaha Alihkan Perhatian, Soleh Terima Ancaman di Banyak Jalan Menuju Rumah
Video Bocah Papua Bingung Minum Susu Kotak Soroti Kesenjangan dan Tantangan Distribusi