OLEH: DENNY JA
PADA awal Januari 2012, Presiden Goodluck Jonathan mengumumkan penghapusan subsidi bahan bakar bensin. Maka harga yang selama ini sangat murah, sekitar ?65, naik menjadi ?141 per liter.
Kenaikan harga ini memicu kemarahan publik. Terutama ibu-ibu dan keluarga miskin protes. Mereka mengandalkan transportasi murah untuk kebutuhan dasar seperti pergi ke pasar atau ke puskesmas.
Seorang ibu di Lagos, Antonia Arosanwo, menggambarkan efeknya dengan jelas:
“Saya marah. Biaya perjalanan saya di bus melambung dua kali lipat sejak subsidi dihapus.”
Gerakan ini meluas menjadi protes nasional yang dikenal sebagai Occupy Nigeria (2?"14 Januari 2012).
Unjuk rasa besar dilakukan. Bus dihentikan, jalan diblokir. Dan puluhan orang tewas akibat bentrokan dengan aparat .
Hanya dalam dua minggu, pemerintah tersentak, mengembalikan harga bensin ke level sekitar ?97 per liter.
Ketika pencabutan subsidi menentukan nasib pemimpin, apakah ini jenis demokrasi yang sehat?
Dalam sejarah negara-negara berkembang, subsidi energi adalah candu politik. Ia menenangkan protes, menekan inflasi, dan membeli loyalitas instan.
Di Mesir, revolusi Arab Spring dipicu bukan hanya oleh otoritarianisme, tapi juga pencabutan subsidi bahan pokok.
Di Venezuela, rezim Chávez bertahan bertahun-tahun di atas fondasi bensin gratis. Di Indonesia, lebih dari Rp500 triliun anggaran pernah dikucurkan hanya untuk menjaga harga BBM tetap “terasa murah”.
Padahal, data membongkar ilusi itu. Menurut Bank Dunia, 70% subsidi BBM di Indonesia justru dinikmati oleh 30% kelompok terkaya.
Pemilik mobil SUV mendapat porsi lebih besar dibanding pengayuh becak atau nelayan. Subsidi ini bukan keadilan sosial.
Melainkan ini hadiah politik untuk kelas menengah urban yang paling vokal di media sosial dan paling menentukan di TPS kota.
Kita dimenangkan hari ini. Tapi esok hari, sekolah anak kita kekurangan guru. Puskesmas tak punya vaksin. Jalan desa tetap berlubang.
Inilah ironi: energi memberi panas yang cepat, tapi meninggalkan arang yang panjang. Subsidi memang populis. Tapi ia seringkali memiskinkan.
Jauh di balik kampanye dan baliho, ada sumber uang yang lebih berkuasa daripada rakyat: sumur minyak dan tambang batu bara.
Kita hidup di era ketika industri energi bukan sekadar penggerak ekonomi, tapi pendonor utama pesta demokrasi.
Contoh paling vulgar adalah Brasil: skandal Petrobras menyeret presiden, anggota parlemen, hingga eksekutif top ke penjara.
Di Nigeria, “oil bunkering” ilegal melahirkan tentara bayaran yang lebih setia pada pengusaha energi daripada konstitusi.
Dan Indonesia? Kita punya cerita sendiri: Petral, anak usaha Pertamina yang pernah menjadi ladang mafia impor minyak.
Ada juga permainan tender yang membiayai koalisi politik. Surat izin tambang berubah menjadi mata uang politik: siapa mendukung siapa, akan dapat konsesi dimana.
Banyak suara rakyat ditukar satu kontrak blok migas. Itulah mata uang baru demokrasi.
Negara yang hidup dari rente minyak kerap menjadi negara yang malas. Pajak tak lagi dikembangkan secara adil.




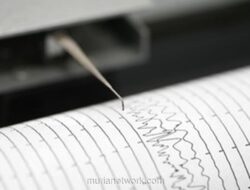






Artikel Terkait
Sepertiga Petugas Haji Tahun Depan Perempuan, Angka Tertinggi Sepanjang Sejarah
Terdakwa Narkoba Nyaris Mati Kabur dari Sidang, Diduga Dibantu Motor Penunggu
Masjid Raya Pase Kembali Ramai, Meski 124 Masjid Lainnya Masih Rusak Berat
Prabowo Panggil Menteri, Bahas Strategi Kuasai Kekayaan Alam