Hidup sebagai pelajar di era sekarang ini memang unik. Kita dikelilingi oleh kecerdasan buatan yang bisa menjawab hampir semua pertanyaan dalam sekejap. Tapi, ada efek sampingnya. Daya juang intelektual kita, perlahan tapi pasti, mulai tergerus. Kita merasa serba tahu, padahal yang kita miliki seringkali cuma pemahaman yang dangkal. Menurut Chegg Global Student Survey 2025, mayoritas pelajar di berbagai belahan dunia sudah memakai AI generatif untuk belajar dan ngerjain tugas. Angkanya tinggi, dan itu menunjukkan adopsi teknologi ini berjalan sangat cepat. Namun begitu, kecepatan ini belum tentu berbanding lurus dengan kemampuan berpikir kritis yang kita miliki.
Nah, di tengah derasnya arus teknologi ini, pendidikan punya tugas besar. Ia harus kembali ke akarnya: mempertajam kemampuan manusia untuk memahami, menimbang, dan memutuskan sesuatu dengan kepala dingin. Ada paradoks yang lahir dari kecepatan digital. Informasi tanpa batas memang membuka pintu belajar lebar-lebar, tapi di sisi lain, ia juga menciptakan budaya instan. Pelajar yang tumbuh di lingkungan serba cepat ini mulai kehilangan kesabaran untuk proses yang butuh ketelitian. Kalau pendidikan diam saja, risikonya jelas: kita akan melahirkan lulusan yang mungkin piawai secara teknis, tapi rapuh saat harus berpikir sendiri.
Memang, revolusi yang dibawa AI itu luar biasa. Jurnal ilmiah terbaru, materi kuliah terbaik, semua bisa diakses dengan sekali klik. Tapi justru di sinilah jebakannya. Sebuah survei perilaku digital dari Snapcart mengungkap fakta menarik: pengerjaan tugas sekolah dan kuliah jadi alasan utama para pelajar menggunakan AI generatif. Angka ini mengindikasikan sesuatu. AI kini menjadi sumber pertama yang dicari ketika butuh jawaban cepat, seringkali menggeser upaya untuk menelusuri sumber aslinya. Akibatnya? Banyak yang merasa sudah paham suatu materi, padahal cuma karena bisa mengulang poin-poin yang dihasilkan mesin.
Lahirlah ilusi penguasaan. Kondisi ini terlihat nyata saat pelajar sekadar copy-paste kesimpulan dari AI tanpa mengecek kebenarannya, atau tak mampu menjelaskan ulang argumen yang disodorkan. Padahal, pemahaman sejati itu lahir dari proses mengurai argumen dan mempertanyakan asumsi. Bukan dari kesimpulan instan yang ditawarkan algoritma. Perlahan-lahan, pendidikan bergeser dari ruang untuk mengasah penalaran, menjadi sekadar tempat konsumsi informasi kilat. Ketika proses berpikir tak lagi diasah, jadilah pelajar yang pengetahuannya luas tapi terpecah-pecah, kaya informasi tapi miskin struktur.
Sebenarnya, ancaman semacam ini bukan hal baru. Sejarah sudah sering memberi peringatan. Setiap revolusi teknologi selalu menggeser pola kompetensi manusia. Dulu, Revolusi Industri mengurangi keterampilan tangan saat mesin ditemukan. Lalu, revolusi digital menggerus fungsi ingatan karena internet menyediakan segalanya. Sekarang, Revolusi AI datang dengan tantangan yang lebih dalam: proses penalaran kita sendiri mulai bisa diambil alih oleh mesin yang justru kita latih.
Tanpa pendidikan yang tegas menjaga disiplin intelektual, lembaga pendidikan berisiko besar. Mereka bisa saja mencetak lulusan yang serba cepat, tapi tak bisa bernalar tanpa bantuan AI. Lembaga pendidikan tidak boleh cuma merayakan kemudahan akses. Mereka harus menjaga martabat berpikir sebagai inti dari segala proses belajar.








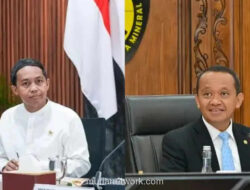


Artikel Terkait
Gelombang Pelapor WNI Korban Sindikat Kamboja Mulai Mereda
Prabowo Langsung Gelar Rapat Maraton di Bogor Usai Tur Dunia
Kanopi Kelurahan Terbang, Lalu Lintas Kereta Yogyakarta-Solo Lumpuh Sementara
Kiai Didin Pertanyakan Niat AS Bentuk Dewan Perdamaian Palestina