✍🏻 Erizeli Jely Bandaro
Presiden Prabowo Subianto memang benar. Indonesia itu sangat besar. Coba bayangkan, bentang geografisnya lebih panjang dari Amerika Serikat. Dari sudut pandang Eropa, jaraknya setara London hingga Moskow. Tiga zona waktu, ribuan pulau, ratusan budaya ini bukan bangsa yang kecil.
Tapi tunggu dulu. Di ekonomi abad ke-21 ini, ukuran luas wilayah bukan lagi patokan utama. Pertanyaannya sekarang adalah: seberapa dalam pengetahuan yang kita miliki?
Di sinilah paradoks Indonesia muncul dengan gamblang. Kita adalah negara yang sangat besar, namun nilai industrinya justru kecil. Ini terutama terlihat jika kita mengukur kapasitas riset di bidang rekayasa material.
Lihat saja Singapura. Negara kota itu tak punya tambang, tak punya hutan mineral, dan wilayahnya sangat sempit. Namun, dalam berbagai indeks riset internasional seperti Nature Index dan publikasi di bidang material science mereka jauh meninggalkan Indonesia. Rahasianya bukan sumber daya alam, melainkan kesadaran akan arti nilai tambah.
Kita menggali nikel, bauksit, tembaga, dan pasir silika dalam jumlah masif. Sayangnya, penguasaan kita seringkali berhenti di titik material mentah atau setengah jadi. Bidang material engineering yang mengurusi struktur, sifat, dan fungsi material belum jadi fondasi industrialisasi kita. Alhasil, nilai tambah ekonomi itu menguap ke negara lain yang menguasai paten dan teknologi.
Makna kebesaran sebuah negara perlu kita baca ulang. Luas wilayah tak otomatis memberi daya saing. Kekayaan alam juga tak serta-merta jadi kekuatan industri. Yang menentukan adalah kemampuan mengubah material mentah menjadi teknologi.
Singapura paham betul soal ini. Mereka menempatkan material science sebagai tulang punggung industri: dari baterai, semikonduktor, hingga aerospace. Negara kecil itu tidak menjual tanah, tapi menjual pengetahuan. Dari situlah muncul pricing power dan kedaulatan industri yang sebenarnya.
Di sisi lain, Indonesia masih terjebak pada logika lama. Membangun smelter dan kawasan industri dianggap sudah cukup. Padahal, tanpa riset material yang mendalam, industrialisasi hanya memperpanjang rantai ekstraksi belaka. Kita mungkin terlihat sibuk dengan pabrik dan ekspor, tapi kendali atas nilai tetap di tangan orang lain.
Pernyataan Presiden tentang kebesaran Indonesia mestinya jadi titik tolak, bukan akhir perjalanan. Negara seluas London-Moskow semestinya punya ekosistem riset material kelas dunia. Bukan sekadar jadi lumbung bahan baku global. Kalau tidak, kebesaran geografis cuma jadi latar belakang bagi ekonomi bernilai rendah.
Sejarah memberi pelajaran. Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan Singapura membangun kekuatan bukan dari luas wilayah, tapi dari laboratorium, universitas riset, dan insinyur material. Mereka kecil di peta, tapi besar dalam nilai.
Indonesia sudah besar secara fisik. Yang masih tertinggal adalah kebesaran dalam pengetahuan. Selama riset material engineering tidak jadi prioritas nasional setara dengan pembangunan infrastruktur kita akan tetap berdiri di pinggir rantai nilai global. Kebesaran sejati bukan diukur dari jarak London ke Moskow, tapi dari sejauh mana kita bisa mengubah batu jadi peradaban industri.
Namun begitu, ada ironi lain yang menggelitik. Indonesia secara geografis memang raksasa. Kekayaan alamnya berlapis: hutan tropis, mineral strategis, laut luas, ditambah bonus demografi. Tapi di balik semua itu, ada kenyataan pahit: negara seluas ini seolah dibonsai oleh sikap korup elite dan mentalitas cari rente.
Bonsai adalah seni mengecilkan pohon besar agar jinak dan mudah dikendalikan. Dalam politik-ekonomi Indonesia, nasib serupa menimpa potensi bangsa. Potensi yang mestinya tumbuh tinggi justru dipangkas terus oleh korupsi, perburuan rente, dan kebijakan jangka pendek yang melayani kepentingan sempit.
Masalahnya bukan cuma korupsi dalam arti kriminal. Yang lebih berbahaya adalah korupsi cara berpikir. Mentalitas rente membuat kekuasaan dilihat bukan sebagai amanah membangun bangsa, melainkan akses untuk membagi-bagi konsesi: tambang, hutan, lahan, proyek. Negara tak lagi jadi organisasi pembelajar, melainkan ladang panen cepat.
Akibatnya, kebijakan publik kehilangan visi jangka panjang. Industrialisasi direduksi jadi sekadar ekstraksi. Hilirisasi cuma dipahami sebagai pemanjangan rantai komoditas, bukan penguasaan teknologi. Riset dianggap biaya, pendidikan dilihat sebagai pengeluaran sosial. Dalam ekosistem rente, nilai tidak diciptakan hanya dipindahkan dari ruang publik ke kantong pribadi.
Inilah mengapa negara yang luas justru tampak kecil di rantai nilai global. Kita ekspor bahan mentah, lalu impor produk jadi. Kita bangga pada pertumbuhan, tapi rapuh saat harga komoditas jatuh. Kita bicara kedaulatan, sementara anggaran negara habis untuk bayar bunga utang akibat keputusan masa lalu yang miskin nilai tambah.
Korupsi elite tak selalu tampak sebagai suap kasar. Seringkali ia lebih halus: regulasi yang dilonggarkan untuk investor "strategis", pembiaran kerusakan ekologi yang dibungkus sebagai pembangunan, atau pembingkaian kritik sebagai ancaman stabilitas. Di sinilah negara benar-benar dibonsai bukan oleh kurangnya sumber daya, tapi oleh absennya keberanian moral dan intelektual.
Negara besar butuh elite yang besar pula: besar dalam visi, bukan dalam kekayaan. Tanpa itu, luas wilayah cuma jadi dekorasi peta. Kekayaan alam berubah jadi kutukan. Demokrasi pun menjelma prosedur rutin yang melegitimasi pembagian rente.
Indonesia tidak kekurangan potensi. Yang langka adalah kemauan keluar dari ekonomi rente menuju ekonomi nilai. Selama kekuasaan dipahami sebagai kesempatan menguasai sumber daya, bukan membangun kapasitas manusia dan teknologi, negara ini akan tetap besar di peta namun kecil dalam peradaban. Negara tidak runtuh karena kurang tanah. Ia menyusut karena elitnya memilih memotong cabang masa depan demi buah sesaat.
Lalu, bagaimana dengan kondisi fiskal? Indonesia adalah negara besar. Penduduknya lebih dari 270 juta jiwa, sumber daya alamnya melimpah. Tapi dalam praktik fiskal hari ini, ruang geraknya justru sempit.

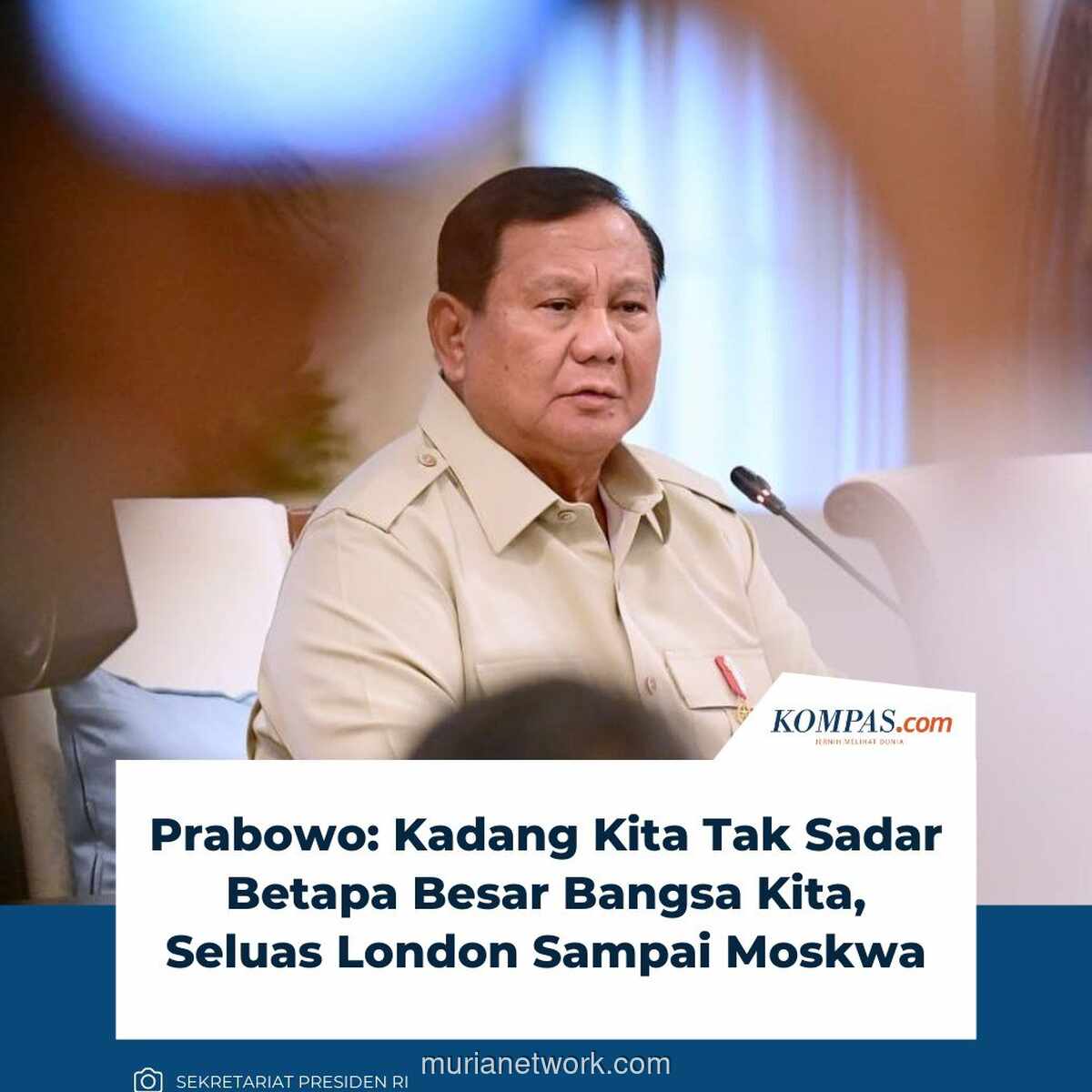









Artikel Terkait
SMA Siger Lampung Gagal Kantongi Izin, Siswa Diarahkan Pindah
Kantong Penipuan di Perbatasan Kamboja: Studio Kantor Polisi Palsu untuk Teror Korban via Video Call
Cak Imin dan Jajaran PKB Bertemu Presiden Prabowo Bahas Rakernas dan Aspirasi Rakyat
Gus Aam Wahib Wahab: Board of Peace Tanpa Palestina Hanyalah Ilusi