Penyebabnya bukan cuma soal penerimaan pajak. Beban utama justru datang dari belanja bunga utang dan pembayaran pokok utang yang terus membesar. Di tahun 2025, negara diproyeksikan membayar sekitar Rp 550 triliun untuk bunga utang. Kalau ditambah cicilan pokok sekitar Rp 450–500 triliun, maka lebih dari Rp 1.000 triliun penerimaan negara tersedot hanya untuk melayani utang masa lalu.
Dengan penerimaan pajak sekitar Rp 2.300 triliun, angka tadi berarti sekitar 43–46% pajak kita habis sebelum negara sempat memutuskan kebijakannya sendiri. Ini bukan sekadar statistik. Ini adalah indikator nyata hilangnya kedaulatan fiskal.
Kita sering ditenangkan dengan rasio utang terhadap PDB yang "masih aman" di kisaran 40%. Tapi indikator itu bisa menyesatkan. Yang menentukan kemampuan negara bertindak bukanlah stok utang, melainkan berapa besar penerimaan rutin yang terkunci untuk bayar bunga dan cicilan. Dalam ekonomi publik, inilah wujud nyata crowding out fiskal.
Bandungkan dengan negara lain. Jepang punya rasio utang di atas 230% PDB, tapi beban bunganya cuma sekitar 14% dari penerimaan pajak. Singapura bahkan lebih baik, belanja bunganya hanya 5%. Jerman cuma 4%. Indonesia? Kita berada di posisi paradoks: utang relatif kecil, tapi mahal sekali secara fiskal.
Konsekuensinya terasa di mana-mana. Anggaran untuk pendidikan, kesehatan, riset, dan industrialisasi bukan lagi soal visi, melainkan soal sisa anggaran setelah utang dibayar. Setiap program baru harus cari pembiayaan tambahan, yang seringkali berarti utang baru lagi. Siklus ini menjebak kita dalam debt service trap, di mana kebijakan publik lebih sibuk membayar masa lalu daripada menyiapkan masa depan.
Ironisnya, belanja bunga dan cicilan itu tidak menciptakan nilai tambah ekonomi. Ia tidak memperluas basis pajak, tidak meningkatkan produktivitas. Ia cuma transfer dari generasi sekarang kepada kreditor sebagai harga dari keputusan pembangunan yang terlalu lama mengandalkan ekonomi rente.
Inilah paradoks Indonesia hari ini: negara besar dengan anggaran sempit. Kedaulatan politik ada, tapi kedaulatan fiskal menyusut. Negara boleh pilih menteri dan program, tapi pilihan anggarannya sudah dibatasi kewajiban utang. Kedaulatan fiskal hanya ada jika negara punya ruang untuk menentukan prioritas tanpa dipaksa kewajiban masa lalu. Selama hampir setengah penerimaan pajak habis untuk bunga dan cicilan, Indonesia akan tetap besar di peta namun kecil dalam kemampuan menentukan nasibnya sendiri.
"
Ada satu lagi paradoks yang menyakitkan. Indonesia tercatat sebagai negara dengan cadangan emas geologis terbesar ke-4 di dunia, sekitar 3.800 ton emas masih di perut bumi.
Tapi dalam statistik cadangan emas moneter emas yang benar-benar disimpan negara di cadangan devisa posisi kita jatuh ke peringkat ke-43 dunia.
Perbedaan ini bukan cuma angka. Ini adalah cermin kegagalan struktural mengelola sumber daya.
Dalam teori moneter, emas di cadangan devisa adalah aset tanpa risiko pihak lawan instrumen lindung nilai saat krisis mata uang atau gejolak geopolitik terjadi. Negara-negara besar seperti AS, Jerman, Rusia, dan Tiongkok paham ini. Mereka aktif mengakumulasi emas sebagai asuransi kedaulatan moneter.
Indonesia? Tidak.
Di sini, emas lebih banyak diperlakukan sebagai komoditas ekstraktif, bukan aset strategis. Ia ditambang, diekspor, lalu diuangkan hasilnya mengalir ke laba korporasi dan dividen pemegang saham. Negara cuma dapat royalti dan pajak. Pola ini selaras dengan apa yang disebut resource curse: negara kaya sumber daya justru mengalami pertumbuhan rapuh dan ketimpangan tinggi.
Dalam kerangka ekonomi-politik, terjadi apa yang disebut state capture, di mana kebijakan negara dibajak kepentingan pemilik modal. Dalam konteks SDA, negara berubah dari pemilik aset menjadi pemberi izin belaka. Kekayaan nasional tidak diakumulasi sebagai aset publik, tapi dialirkan ke sektor privat, seringkali lintas negara.
Akibatnya paradoks ini terus berulang: SDA diekstraksi, devisa dikuasai asing, sementara struktur fiskal tetap lemah dan bergantung pada utang. Padahal, negara kaya SDA seharusnya bisa membangun sovereign balance sheet yang kuat mengubah sumber daya alam menjadi aset keuangan jangka panjang, seperti yang dilakukan Norwegia. Indonesia memilih jalur sebaliknya. Likuiditas jangka pendek diutamakan, akumulasi aset strategis diabaikan.
Itulah sebabnya, walau kaya sumber daya, Indonesia tetap rentan pada gejolak nilai tukar, bergantung pada dolar AS, dan terjebak dalam siklus utang. Dalam bahasa yang lebih gamblang, kekayaan tidak mengalir ke negara karena struktur kepemilikannya dirancang agar akumulasi modal berada di tangan segelintir pemilik aset. Ketimpangan bukan kecelakaan, melainkan hasil desain.
Emas jadi simbol paling telanjang dari kegagalan ini. Ia ada di tanah Indonesia, tapi tidak tinggal di neraca negara. Ia menghasilkan nilai, tapi bukan kedaulatan. Ia memperkaya pemilik modal, tapi tidak memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Selama Indonesia mengelola sumber daya alam dengan logika rente bukan logika kepemilikan strategis maka ironi ini akan terus berulang: kaya SDA, miskin negara.
Emas ada di bumi Indonesia. Namun kekayaannya hidup di neraca korporasi.
Dan selama itu tidak diubah, negeri ini akan terus bertanya dengan jujur tapi mungkin sudah terlambat mengapa kita tetap miskin di tengah kelimpahan? Mengapa kita bangsa besar tetapi terkutuk oleh SDA dan terjajah oleh utang?

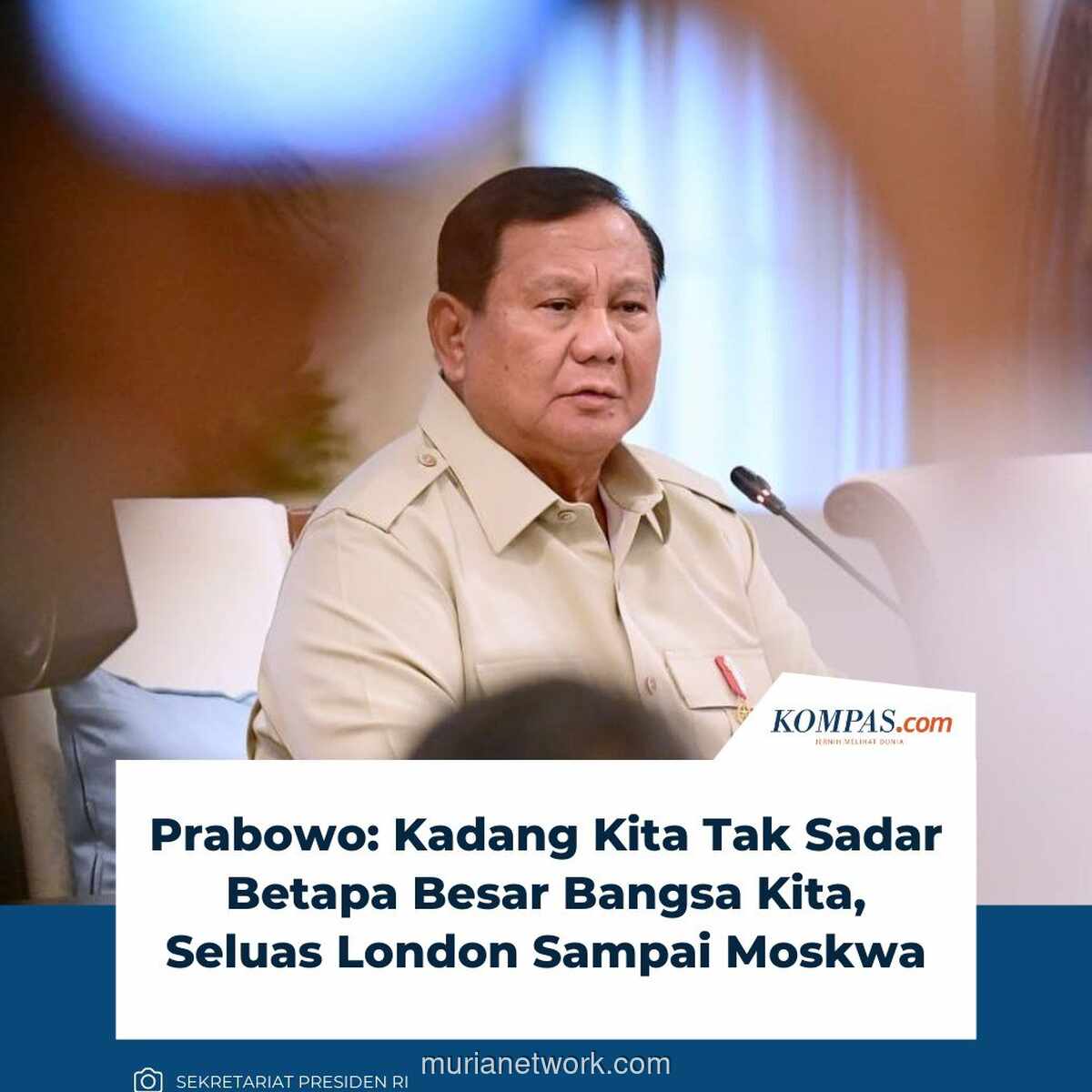









Artikel Terkait
Tiga Jaksa di HSU Dicopot Usai Dijerat KPK dalam Kasus Pemerasan
5 Ide Kado Natal untuk Balita yang Seru dan Sarat Manfaat
Kajari HSU Dicopot Usai KPK Tangkap Basih Kasus Pemerasan
Presiden Prabowo Turunkan Tito, Huntap Korban Bencana Sibolga Mulai Dibangun