Di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/12) lalu, hakim Djuyamto akhirnya mendengar vonis yang menantinya: sebelas tahun penjara. Ia terbukti menerima suap untuk membebaskan tiga terdakwa korporasi dalam kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah. Usai sidang, sikapnya tampak tenang.
"Kita hormati putusan majelis hakim," ucap Djuyamto singkat.
Nominal suap yang diterimanya tak main-main, mencapai Rp 9,2 miliar. Tujuannya jelas: mempengaruhi putusan pengadilan agar tiga perusahaan pelaku korupsi CPO itu divonis lepas. Uang sebesar itu mengalir melalui jaringan yang cukup rumit.
Pemberi suap adalah para advokat yang mewakili kepentingan korporasi raksasa: Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Nama-nama seperti Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih, dan M. Syafe'i disebut dalam berkas perkara.
Mereka menyalurkan uangnya melalui eks Ketua PN Jakarta Selatan, M Arif Nuryanta, serta Panitera Muda Wahyu Gunawan. Dari sanalah, dana itu kemudian dibagikan, dengan Djuyamto sebagai salah satu penerimanya. Atas perbuatannya, ia terbukti melanggar Pasal 6 ayat 2 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sebuah Ironi yang Pahit
Di sinilah ironinya terasa begitu menusuk. Selama ini, Djuyamto justru dikenal sebagai sosok yang vokal memperjuangkan independensi hakim. Bahkan, ia menulis buku tentang perjuangan itu. Kini, ia harus duduk di kursi pesakitan karena menggerogoti independensi yang ia perjuangkan.


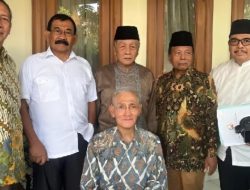








Artikel Terkait
Valverde Cetak Gol Telat, Real Madrid Taklukkan Celta Vigo 2-1
Valverde Selamatkan Real Madrid dengan Gol Dramatis di Menit Akhir
Valverde Cetak Gol Telat, Real Madrid Curi Kemenangan Dramatis di Markas Celta Vigo
Napoli Kalahkan Torino 2-1 dalam Laga Sengit di Maradona