Di hadapan anggota Komisi III DPR, Kapolri menanggapi wacana penataan posisi institusinya. Tanggapannya jelas: penolakan. Tapi yang kemudian mencuri perhatian justru pernyataan penutupnya yang langsung menyebar. Intinya, jika dalam skema baru itu ia diminta jadi menteri, lebih baik memilih "menjadi petani".
Kalimat itu, di permukaan, terdengar sangat rendah hati. Namun begitu, di situlah letak persoalannya. Bukan soal merendahkan profesi petani justru sebaliknya. Petani itu terlalu mulia untuk dijadikan sekadar metafora pelarian dari sebuah pertanyaan publik yang serius.
Masalah utamanya adalah konteks. Pernyataan simbolik itu muncul di saat yang salah, ketika kepercayaan publik sedang haus dan kritisisme terhadap Polri menumpuk. Persepsi tentang penegakan hukum yang tak adil, respons yang defensif, dan fokus yang terkesan melenceng: ramai di hal-hal pinggiran, tapi rapuh di urusan inti.
Reaksi masyarakat pun beragam. Ada yang cuma geleng-geleng, tak sedikit yang geram, sinis, atau sekadar lelah. Di tengah keriuhan itu, satu hal yang jelas: publik tidak sedang meminta perumpamaan. Mereka meminta keadilan yang benar-benar bekerja, yang bisa dirasakan.
Nah, di sinilah ujian sesungguhnya bagi seorang pejabat. Jabatan bukan panggung untuk bermain kata-kata indah. Itu adalah amanah konstitusional yang menuntut kapasitas nyata, nyali moral, dan kedewasaan untuk menerima koreksi.
Jadi, ketika kinerja dipertanyakan, jawaban yang dibutuhkan bukan metafora yang mengalihkan pembicaraan dari institusi ke preferensi pribadi. Yang dibutuhkan adalah pembenahan. Yang kasat mata.
Tesisnya sederhana: "jadi petani" bukanlah jawaban. Petani menunaikan amanahnya di sawah dan ladang. Seorang pemimpin menunaikan amanahnya di jabatannya. Keduanya sama-sama mulia jika dijalani dengan penuh tanggung jawab. Yang tidak mulia adalah ketika profesi yang mulia itu dipakai sebagai tirai, untuk menutupi pertanyaan-pertanyaan penting tentang kinerja dan keadilan.
Coba lihat petani. Ia bekerja dengan disiplin yang sunyi. Salah benih, gagal panen. Salah mengairi, tanaman mati. Nilainya ada pada proses, bukan sensasi. Justru karena kemuliaan kerja semacam itulah, kalimat "lebih baik jadi petani" terasa janggal saat dipakai sebagai tameng menghadapi kritik. Ia terdengar merendah, tapi fungsinya mengalihkan. Ia terdengar bijak, tapi menghindari substansi.
Kepemimpinan yang amanah tidak alergi pada kritik. Kritik justru diperlakukan sebagai data, sebagai alarm. Respons yang lahir bukan klarifikasi yang berbelit, melainkan koreksi yang menyentuh inti persoalan.
Energinya tidak dihabiskan untuk menjaga gengsi pribadi, tapi untuk merawat martabat institusi. Keluhan warga dibaca sebagai peringatan dini. Sikap seperti inilah yang bisa menutup celah arogansi kecenderungan memakai hukum cuma sebagai alat untuk menang, bukan sebagai jalan menuju keadilan.
Lalu, mengapa wacana restrukturisasi Polri bisa membesar? Menurut sejumlah pengamat, karena publik merasa mekanisme koreksi dari dalam sudah tidak cukup menggigit. Dalam kondisi seperti ini, pertanyaan "Polri harus di bawah siapa?" muncul bagai tombol darurat. Padahal, struktur seringkali cuma kulit luarnya saja. Penyakitnya biasanya bersarang di dalam: pada arah kepemimpinan, kultur kerja, disiplin etik, dan kualitas pertanggungjawaban.
Penilaian publik itu lahir dari pengalaman sehari-hari, bukan teori. Dari rasa aman yang rapuh. Dari rasa adil yang terus terluka. Dari kepercayaan yang menipis karena pola yang dianggap tebang pilih. Kekeliruan sekali dua kali mungkin bisa dimaklumi, tapi pola yang berulang? Tidak. Di situlah persepsi kolektif terbentuk: ada yang tidak beres dalam cara kekuasaan ini dimaknai.








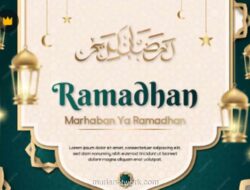


Artikel Terkait
BGN Hentikan Sementara Ratusan Dapur MBG di Indonesia Timur karena Tak Miliki Sertifikat Higiene
Bayer Leverkusen dan Bayern Munich Imbang 1-1 dalam Laga Panas Penuh Drama VAR
Putri Kusuma Wardani Amankan Tiket Final Swiss Open 2026
Polri Gunakan Drone dan AI untuk Pantau dan Atur Arus Mudik Lebaran 2026