Dalam obrolan sehari-hari, anak tunggal kerap jadi bahan pembicaraan. Bukan sebagai sosok yang didengar, tapi lebih sebagai objek penilaian. Stigma yang melekat itu selalu sama: manja, kurang empati, atau sulit berbagi. Narasi ini terus berulang, seakan-akan status 'tunggal' itu sudah cukup untuk menilai karakter seseorang. Padahal, kalau mau jujur, pengalaman hidup kami jauh lebih kompleks dan berlapis dari sekadar label itu.
Saya sendiri merasakannya. Tumbuh tanpa saudara kandung, saya sadar bahwa menjadi anak tunggal bukan cuma soal jumlah orang di rumah. Ini tentang bagaimana kamu belajar memahami dunia dari sebuah ruang yang terbatas. Tidak ada kakak yang jadi panutan atau adik yang harus dilindungi. Banyak proses pendewasaan justru terjadi dalam kesunyian tanpa perbandingan langsung, tanpa persaingan di dalam rumah, dan seringkali tanpa tempat berbagi yang benar-benar setara.
Memang, di satu sisi, perhatian orang tua bisa terfokus penuh. Tapi jangan salah, perhatian yang utuh ini biasanya dibayar dengan harapan yang sama besarnya. Kamu jadi satu-satunya tumpuan, penerus, dan tolak ukur kesuksesan keluarga. Tekanan semacam ini sering tak terlihat, karena terselubung dalam anggapan bahwa kami "beruntung". Padahal, nggak semua orang sanggup menggendong ekspektasi sebesar itu sendirian.
Lalu ada soal kesepian. Bukan yang dramatis, tapi lebih pada kebiasaan untuk sendiri. Banyak dari kami tumbuh dengan dunia batin yang kaya penuh dialog internal, imajinasi, dan refleksi. Kami terlatih mengisi waktu sendiri, memutuskan sesuatu sendiri, bahkan menyelesaikan masalah tanpa perantara saudara. Proses ini membentuk kemandirian, ya, tapi juga butuh ketahanan mental yang nggak main-main.
Begitu masuk dunia kampus, semua diuji lagi. Dunia yang menuntut kerja sama, kompromi, dan kecakapan membaca situasi sosial. Bagi anak tunggal, ini bukan hal baru, tapi kerap melelahkan. Harus beradaptasi dari pola individual ke komunal. Tak jarang, sikap mandiri kami disalahartikan sebagai enggan bergaul, atau kebiasaan berpikir sebelum bicara dianggap sebagai sikap tertutup.
Namun begitu, ada kepekaan yang justru terasah. Karena terbiasa bergaul dengan orang dewasa sejak kecil, banyak anak tunggal punya kemampuan mendengar yang cukup baik. Kami cenderung mengamati dulu sebelum ikut bicara, menimbang sebelum bereaksi. Dalam diskusi kelompok, sikap ini sering tampak sebagai kehati-hatian. Bukan karena tidak percaya diri, tapi lebih karena kami terbiasa memahami batas.







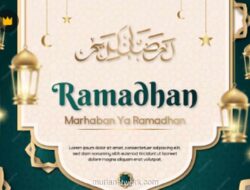



Artikel Terkait
Inter Milan Hadapi Tekanan Berat di Laga Penentu Lawan Bodo/Glimt
Imsak Surabaya Hari Ini Pukul 04.08 WIB, Berbuka 17.53 WIB
Warga Makassar Diingatkan Imsak Hari Ini Pukul 04.43 WITA
Atletico Madrid Hadapi Club Brugge di Laga Penentu Tiket 16 Besar Liga Champions