Oleh Shahed Abu AlShaikh
Perang itu datang tepat di tahun ketiga saya kuliah jurusan terjemahan Inggris. Semua berubah dalam sekejap. Warna-warni hidup memudar, impian-impian hancur berantakan, dan semangat itu seperti patah sama sekali. Dunia saya yang berpusat pada kampus dan cita-cita mendadak terhenti. Dan Gaza? Gaza sendiri terperangkap dalam kehancuran yang sulit diungkapkan dengan kata-kata.
Keluarga saya tak beda dengan yang lain di sini. Dua tahun genosida ini merenggut kesehatan dan rasa aman kami. Kami sudah mengungsi sepuluh kali, terombang-ambing dari utara Gaza ke Khan Younis, lalu ke Rafah, kemudian ke Deir el-Balah. Setelah lebih dari setahun, kami sempat kembali ke Kota Gaza, hanya untuk diusir lagi ke Khan Younis delapan bulan kemudian. Rumah kami rusak parah. Sekarang, kami terpaksa tinggal di dalamnya dengan dinding yang digantikan terpal.
Di musim panas 2024, kampus-kampus buka lagi, tapi cuma lewat daring. Saya mendaftar. Bukan karena masih yakin bisa jadi asisten dosen seperti yang saya cita-citakan dulu, tapi lebih karena ingin menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Rasanya ada kewajiban untuk itu.
Jadilah tahun ketiga itu saya lalui dari dalam tenda, bergantung pada koneksi internet yang suka hilang-hilang. Tahun yang mestinya membentuk saya jadi pengajar, dihabiskan di antara kepungan ketidakpastian.
Memasuki tahun terakhir di Februari, bencana lain datang: kelaparan. Kesehatan saya merosot drastis. Kurang makan, terusir, ditambah ketakutan bom yang tiada henti. Berat badan saya anjlok hampir 15 kilogram dalam waktu singkat. Badan lemas, pusing-pusing tak karuan. Pernah sampai titiknya kami cuma makan sekali sehari, itu pun porsinya tak cukup untuk mengenyangkan bayi. Tulang selangka saya menonjol, jadi pengingat nyata betapa parahnya keadaan.
Saya juga lihat hal yang sama pada keluarga, terutama ibu. Ada momen-momen menakutkan di mana saya khawatir kami hampir kehilangan dia. Seringkali saya takut untuk tetap terjaga lewat jam 8 malam, cuma karena tak tahan menahan lapar yang menggerogoti.
Tapi, di tengah semua itu, ada tekad yang bertahan. Saya tak mau perang ini yang menulis akhir cerita saya. Gaza adalah tanah segala kemungkinan, dan fokus saya cuma satu: bertahan hari ini.
Lalu suatu malam, muncul ide. Kalau saya tak bisa mencerahkan pikiran dengan ilmu, setidaknya saya bisa menyalakan ponsel mengisi dayanya. Saya ajukan rencana buka usaha kecil isi daya ponsel pakai panel surya ke keluarga. Mereka mendukung penuh. Besoknya, selembar kertas bertuliskan "Titik Pengisian Daya Ponsel" saya gantung di luar tenda. Dan dimulailah karir baru saya.
Saya buat kartu bernomor untuk setiap ponsel, biar tak ada yang tertukar. Sehari-hari diisi teriakan, "Shahed, nomor 7 sudah belum?" Di luar saya tersenyum jawab, tapi dalam hati perihnya minta ampun. Siapa sangka tahun terakhir kuliah akan berujung seperti ini.
Rintangannya banyak. Cuaca mendung, ponsel numpuk, ditambah tekanan ujian akhir. Setiap awan yang lewat dan tutupi matahari langsung matikan pasokan listrik, karena saya tak punya baterai besar untuk cadangan. Di saat-saat itu, air mata kerap menetes sendiri. Capek dan putus asa campur aduk.
Tapi usahanya lumayan. Setiap hari saya dapat sekitar 10 dolar. Cukup buat beli kuota internet dan hal-hal kecil yang dulu saya anggap sepele, seperti sebungkus keripik atau sekotak jus. Sering saya duduk memandangi deretan ponsel yang sedang ngecas, pikiran melayang: Ini seharusnya waktu saya berdiri di depan kelas sebagai asisten dosen.
Ujian akhir di bulan Oktober saya jalani dengan kondisi yang ironis. Saya dikelilingi ponsel-ponsel yang tak bisa diisi karena langit mendung, sementara air mata mengalir di pipi. Sebuah kontras yang pedih.
Saya cuma satu dari ratusan ribu pemuda Gaza yang menolak ditaklukkan. Bagi kami, pendidikan adalah bentuk perlawanan. Mungkin itu juga sebabnya mengapa pihak pendudukan berusaha keras menghancurkannya. Mereka ingin kami tenggelam dalam kegelapan: kebodohan, keputusasaan, dan pasrah.
Tapi kami tak semudah itu. Pemuda Gaza tetap tak terkalahkan. Kami kejar pendidikan lewat daring, meski internet sering mati. Kami cari cara untuk menopang keluarga; ada yang jualan makanan di pinggir jalan, ada yang ngasih les privat, atau buka usaha kecil-kecilan seperti saya. Banyak juga yang berjuang mengajukan beasiswa untuk bisa kuliah di luar negeri.
Semua ini buktinya: kami cinta hidup, cinta tanah air ini, dan bertekad untuk membangunnya kembali. Bukan sekadar pulih, tapi jadi lebih baik.
Saat ini, saya sedang mengajukan beasiswa untuk studi S2 di luar Gaza. Saya ingin keluar, belajar, dan nanti kembali bukan untuk mengisi daya ponsel, tapi untuk mengisi daya pikiran. Kalau diterima, usaha isi daya kecil ini akan saya serahkan ke adik laki-laki saya, Anas. Dia bercita-cita jadi jurnalis, untuk menceritakan kebenaran tentang Gaza dan orang-orangnya.
Dia dan saya, bersama teman-teman sebaya di sini, kami memilih untuk terus maju. Kami menolak untuk menyerah.
Penulis berasal dari Gaza dan merupakan lulusan sarjana Penerjemahan Bahasa Inggris.




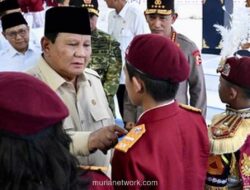






Artikel Terkait
BMKG Imbau Warga Sulsel Waspada Hujan dan Angin Kencang Seharian
Pengamat Soroti Reformasi Kultural sebagai Inti Perubahan di Tubuh Polri
KPK Dalami Aliran Dana Kasus Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid
Istri Tersangka Korupsi Bupati Bekasi Diperiksa KPK