Langit di atas Sumatra seakan robek. Hujan yang turun bukan lagi hujan biasa, melainkan amukan siklon tropis yang langka, memuntahkan air dalam volume yang tak terkira. Tapi, sebenarnya, bencana ini sudah lama dipersiapkan di tanah. Air dari langit itu hanya pemicu akhir.
Lihatlah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sepanjang 2015 hingga 2024, hutan-hutan yang dulu berfungsi sebagai spons raksasa perlahan-lahan sirna. Penyebabnya beragam. Ada kebakaran, perladangan, perluasan pemukiman. Namun, yang paling signifikan adalah ekspansi perkebunan skala besar, seperti sawit dan kakao, yang menggerogoti daerah aliran sungai. Ketika hujan ekstrem datang, tak ada lagi yang menahan. Air langsung meluncur deras, menggerus tanah, membawa gelondongan kayu, dan berubah menjadi banjir bandang yang menghancurkan apa saja di depannya.
Angka-angka yang muncul kemudian sungguh memilukan. Lebih dari seribu nyawa melayang. Rumah yang rusak mencapai 186.488 unit, dengan mayoritas rusak berat. Bencana ini melanda 52 kabupaten dan kota, merusak ribuan fasilitas umum. Peta ini dengan jelas menunjukkan luka yang dalam, sekaligus mengingatkan fakta pahit: Indonesia adalah negara ketiga paling rawan bencana di dunia.
Namun begitu, tanggapan kita terhadap risiko ini, ternyata, jauh dari memadai.
Ambil contoh anggaran. Dari pusat, dana untuk penanggulangan risiko bencana alam hanya sekitar Rp3,1 triliun per tahun. Coba bandingkan dengan kerugian tahunan akibat bencana yang mencapai Rp22,8 triliun. Selisihnya nyaris tujuh kali lipat! Di level daerah, situasinya lebih memprihatinkan. Dana untuk hal tak terduga, termasuk bencana, nyaris tak dianggarkan. Ambil contoh Aceh Tamiang, salah satu wilayah yang terpukul. Mereka cuma menyisihkan 0,24 persen dari total belanja daerah untuk pos Belanja Tidak Terduga di 2025. Sungguh ironis.
Inilah paradoks yang mematikan. Kita hidup di cincin api, dihantui ancaman hidrometeorologi, tapi seolah membiarkan diri terbuka tanpa perlindungan yang berarti.
Lalu, apa yang mesti dilakukan sekarang, ketika bencana sudah terjadi dan ancaman pengulangan selalu menghantui?
Institute for Economic and Social Research (LPEM) FEB UI baru-baru ini melontarkan tujuh rekomendasi. Tiga langkah bersifat mendesak, sisanya empat langkah sistemik. Ini bukan sekadar respons krisis, tapi lebih seperti cetak biru untuk membangun ketahanan jangka panjang.
Pertama, bentuk Task Force Penanganan Bencana Sumatra sekarang juga. Koordinasi yang selama ini tumpang-tindih dan lambat harus disatukan di bawah satu komando yang kuat. Libatkan kementerian, BNPB, pemda, dan para ahli. Bencana seluas ini butuh kepemimpinan yang jelas, titik.
Kedua, mobilisasi sumber daya nasional harus lebih cepat. Dana darurat APBN, personel, logistik mulai dari pangan, air bersih, hingga tenda dan layanan kesehatan, harus digerakkan dengan skala yang masif. Status bencana nasional bukan lagi wacana, melainkan keharusan untuk memotong birokrasi dan memusatkan respons.
Ketiga, kolaborasi dengan semua pihak. Filantropi, lembaga internasional, swasta, dan tentu saja masyarakat. Semua harus digerakkan, tapi dengan koordinasi yang transparan agar bantuan tepat sasaran dan tidak berantakan di lapangan.
Tapi, berhenti pada respons darurat saja jelas tidak cukup. Bencana tahun 2025 ini harus jadi titik balik.
Di sinilah rekomendasi sistemik bekerja. Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana yang sebenarnya sudah diluncurkan sejak 2018 harus segera dihidupkan. Ada Pooling Fund Bencana yang termaktub dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2021, sayangnya masih "tidur panjang". Dana bersama semacam ini penting sebagai penyangga keuangan saat bencana menerpa. Asuransi bencana untuk masyarakat juga perlu didorong lebih serius.
Lebih jauh lagi, kita harus berani membongkar akar masalahnya. Audit menyeluruh terhadap pemanfaatan daerah aliran sungai, izin konsesi, dan izin lingkungan wajib dilakukan. Setiap pelanggaran yang mempercepat deforestasi dan degradasi DAS harus ditindak tegas. Momentum kelam ini harus jadi cambuk untuk mereformasi tata kelola sumber daya alam yang selama ini sering abai terhadap daya dukung lingkungan.
Terakhir, semua rencana pembangunan kita dari RPJMN hingga RTRW harus diselaraskan dengan peta risiko iklim. Selama ini, ketidakselarasan itu yang bikin permukiman dan industri malah masuk ke daerah rawan banjir dan longsor. Data risiko, lingkungan, dan kebencanaan yang masih tercecer di berbagai lembaga harus diharmonisasikan. Sistem peringatan dini yang akurat hanya bisa lahir dari data yang terkumpul baik dan terpercaya.
Laporan LPEM FEB UI itu ditutup dengan sebuah pertanyaan yang menggugah.
"Apakah menurut teman-teman, pemerintah akan mampu menjadikan rekomendasi penanganan mendesak dan perbaikan sistemik ini sebagai prioritas?"
Jawabannya tak tertulis di dokumen manapun. Jawabannya sedang diuji oleh hujan yang pasti akan datang lagi, oleh siklon tropis berikutnya yang mungkin lebih dekat dari yang kita duga. Jawabannya ada pada pilihan kita hari ini. Apakah bencana besar ini hanya akan menjadi duka kolektif yang perlahan terlupakan, atau justru jadi pembuka mata terakhir yang memaksa kita semua untuk berubah sebelum Sumatra, dan mungkin nusantara lainnya, benar-benar tenggelam oleh kesalahan yang terus kita ulang.









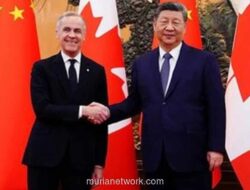

Artikel Terkait
Timnas Indonesia U-17 Dibantai China 0-7 dalam Uji Coba Pahit
Thomas Aquinas Dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia
Ketua MA Kecewa Dua Hakim Depok Jadi Tersangka KPK
Angka Anak Tidak Sekolah di Bone Turun Drastis Berkat Validasi Data dan Program Jemput Bola