"Borobudur itu sakral, Bung! Dibandingkan dengan Batu Caves, itu tidak apple to apple!"
Begitulah salah satu komentar yang menghujam di kolom saya. Seolah-olah membandingkan kedua situs itu adalah sebuah kesalahan fatal. Tapi, coba kita pikirkan lagi. Apakah Batu Caves cuma tempat biasa yang kebetulan ada patung dewa?
Bagi umat Hindu, gua kapur di Selangor itu punya nilai kesucian yang sama tingginya dengan Borobudur bagi umat Buddha. Yang membedakan sebenarnya cuma satu: cara mengelolanya. Kita di Indonesia kerap bersembunyi di balik tameng 'kesakralan' yang justru membuat candi terasa jauh dan berjarak. Sementara Malaysia, lihat saja, mereka berhasil menyelaraskan spiritualitas dengan kegiatan komersial. Tanpa keributan.
Di Batu Caves, eskalator modern dan tangga warna-warni yang instagramable itu hidup berdampingan dengan area peribadatan yang khusyuk. Sebuah tamparan halus bagi kita. Ini membuktikan bahwa pariwisata tidak selalu menodai kesucian. Justru bisa menjadi penopangnya.
Tapi, mari kita kesampingkan dulu perdebatan 'apple to apple' tadi. Kisah Batu Caves itu baru pembuka. Pengalaman saya selanjutnya di Kuala Lumpur, ini yang bener-bener bikin tersentil.
Setelah meliput Festival Thaipusam, rencana saya cuma satu: pulang. Koper sudah siap. Eh, tapi Helmi, teman saya orang Malaysia yang ceplas-ceplos itu, membatalkan niat saya.
"Jangan balik dulu, Fit," katanya sambil nyengir. "Kamu belum sah ke KL kalau belum ke Bukit Bintang."
"Duit tinggal sedikit, Hel. Tempat mahal kan situ?"
"Santai. Ada sepupu aku yang jadi 'Sultan' di sana. Namanya Rizal Hakim."
Dengar nama 'Hakim', saya langsung membayangkan sosok tua galak berkumis tebal. Ternyata dugaan saya meleset total.
Rizal muncul cuma pakai kaos oblong dan celana pendek. Pendiam. Bicara seperlunya, sangat kontras dengan Helmi yang cerewet. Tapi omongannya... pedasnya minta ampun.
"Oh, ini jurnalis Indonesia tu? Yang negaranya luas tapi jalannya macet melulu?" sapanya datar.
Darah saya naik seketika. Baru ketemu, langsung dihajar.
Ya sudahlah. Akhirnya saya ikut mereka menginap dua malam di Bukit Bintang. Dan di situlah saya melihat sebuah kegilaan tata kota yang membuat saya tercengang. Tempat itu ajaib, sungguh.
Coba bayangkan. Anda ambil semua vibe khas kota-kota besar Indonesia. Kemewahan Plaza Indonesia, suasana Braga, keramaian Malioboro, semrawut Pasar Semawis, estetika Tunjungan, dan kemeriahan Legian. Campur jadi satu. Itulah Bukit Bintang.
Semua ada di sana. Berjejalan. Tanpa jarak.
Sore itu, Rizal mengajak saya ke Pavilion KL. Dingin, mewah, penuh dengan toko-toko branded. Orang-orang berjalan cepat dengan penampilan sempurna.
"Ini kalau di Jakarta kayak Bundaran HI ya," ucap saya.
Rizal cuma angguk. "Tunggu lima menit. Kita pindah alam."
Dan benar. Hanya dengan jalan kaki lima menit, kami sampai di Jalan Alor. Dunia berubah seratus delapan puluh derajat.
Aroma parfum mahal hilang, digantikan asap sate, bawang goreng, dan bau got yang 'khas'. Lampion merah bergantungan. Ini persis Pasar Semawis di Semarang! Bedanya, Jalan Alor ini beroperasi tiap hari, nonstop. Asapnya ngebul tak ada henti.
Rizal menunjuk sebuah kursi plastik. "Duduk sini. Pesan Sayap Ayam. Jangan mikirin kolesterol. Lagi libur nih."





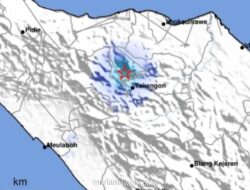





Artikel Terkait
Mari Elka Pangestu Peringatkan Dampak Konflik AS-Israel-Iran ke Ekonomi Indonesia
Pemerintah Larang Truk Besar di Jalan Tol dan Arteri Utama Saat Mudik Lebaran 2026
Gubernur DKI Khawatir Konflik Timur Tengah Picu Gejolak Harga, Siapkan Langkah Antisipasi
APINDO dan Produsen Listrik Swasti Khawatir Pemangkasan Produksi Batu Bara Ancam Pasokan Listrik Nasional