Dari Akuntabilitas ke Komedikrasi
Fenomena-fenomena tadi memperlihatkan pola yang konsisten. Kritik teknis dijawab dengan tuduhan moral. Pertanyaan anggaran dibalas pengalihan isu. Bencana direduksi jadi sekadar “ramaian di medsos”. Keputusan strategis dipentaskan atas nama harga diri, lalu dikoreksi tanpa penjelasan yang jelas. Akibatnya, pernyataan pejabat jadi simpang siur, saling menegasikan. Publik pun merespons bukan dengan kemarahan lagi, tapi dengan tawa sinis.
Lihat saja kasus penolakan bantuan kemanusiaan. Awalnya dibingkai sebagai upaya menjaga martabat bangsa. Lalu diakui sebagai kekeliruan. Inkonsistensi komunikasi seperti ini sulit dipertanggungjawabkan.
Atau keluhan pejabat tinggi yang bilang tak bisa tidur karena baut jembatan darurat “dilepas”. Lalu muncul klarifikasi bahwa yang dimaksud “hanya sebaut”. Persoalan teknis tiba-tiba bergeser jadi bahan olok-olok. Julukan “jenderal baut” itu tidak lahir dari niat merendahkan. Ia muncul karena absennya penjelasan yang jernih dan konsisten dari penguasa.
Rangkaian “kelucuan” dari inkonsistensi inilah yang melahirkan istilah baru: komedikrasi. Suatu keadaan di mana kekuasaan sibuk merespons, tapi gagal menjelaskan; ramai berbicara, tapi gagap mendengar; lebih fokus menata kesan ketimbang membenahi substansi.
Komedikrasi ini berbahaya. Ia menggerus kepercayaan secara perlahan. Koreksi kebijakan jadi lambat. Ruang publik dipenuhi kebisingan. Warga akhirnya belajar bahwa argumen dan data tidak cukup; yang didengar cuma yang viral. Negara sibuk mengelola kesan, tapi tertinggal dalam mengelola substansi.
Jalan Keluar yang Beradab
Sebenarnya jalan keluarnya tidak rumit. Tapi ia menuntut kedewasaan moral dalam menggunakan kuasa. Kekuasaan yang dewasa tidak sibuk membungkam. Ia justru membangun standar respons yang jernih dan bisa diuji. Menjadikan audit dan verifikasi sebagai kebiasaan, bukan ancaman. Serta menata bahasa kekuasaan agar berjarak dari ego dan dekat dengan empati.
Dalam iklim seperti itu, kritik tidak perlu ditakuti. Sebab sudah disediakan kanal yang tertib dan bermakna untuk menyalurkannya. Sementara intimidasi ditolak tegas ia adalah pengkhianatan terhadap mandat demokrasi itu sendiri. Koreksi dinormalkan sebagai tanda kekuatan, bukan aib yang harus ditutupi.
Pada hakikatnya, mandat adalah sumber kuasa. Tapi martabat adalah cara kuasa itu dijalankan. Demokrasi tidak butuh pemimpin yang kebal kritik. Ia butuh pemimpin yang tahan uji: tenang saat dipuji, jernih saat dikritik, sigap membenahi sebelum ketidakpercayaan menjelma jadi kerusakan sosial yang lebih luas. Ketahanan semacam ini tidak lahir dari retorika atau kepiawaian mengelola citra. Ia lahir dari disiplin etika yang menempatkan rakyat sebagai pemilik sah mandat, dan kekuasaan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, kepercayaan publik tidak dibangun oleh pidato yang memukau. Tapi oleh kerja yang jujur, respons yang beradab, dan konsistensi menjaga etika kekuasaan dalam situasi apa pun. Di situlah demokrasi menemukan kekuatannya yang paling sunyi namun paling kokoh: ketika kekuasaan bersedia mendengar dengan rendah hati, dan rakyat benar-benar merasakan perbaikan dalam keseharian mereka.
Wallahualam bishawab.







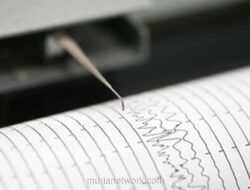



Artikel Terkait
Trump: Iran di Ambang Kejatuhan, Rakyat Mulai Kuasai Kota
Akreditasi Tinggi, Layanan Sepi: Ilusi Mutu Perpustakaan yang Tersandera Angka
Swasembada Pangan: Dari Target Ambisius Menjadi Kenyataan yang Terukur
Brimob Tembak Warga di Tambang Ilegal Bombana, Empat Personel Diperiksa Propam