Oleh: Elvani Ayuningsih Gulo
Kita semua pasti pernah melakukannya. Mengabaikan. Sikap itu muncul dalam bentuk-bentuk yang sederhana, bahkan seringkali luput dari perhatian kita sendiri. Intinya, ini adalah sikap di mana kita memilih untuk tidak memberi perhatian, tidak peduli, dan enggan merespons orang lain atau situasi di sekitar.
Contohnya? Banyak sekali. Tidak membalas senyuman atau sapaan, misalnya. Atau, cuek saja saat ada yang berbagi pendapat. Persoalan di lingkungan sekitar pun dibiarkan mengambang, seolah bukan urusan kita. Hal-hal remeh seperti ini ternyata punya efek yang tak remeh. Kalau dibiarkan terus dan dianggap biasa, sikap acuh tak acuh yang awalnya cuma tindakan personal lama-lama bisa berubah jadi kebiasaan bersama.
Alasan klasiknya biasanya kesibukan. Hidup serba cepat, tekanan kerja menumpuk, ditambah lagi dengan tuntutan ekonomi. Wajar saja kalau akhirnya fokus kita cenderung ke dalam, hanya pada kepentingan diri sendiri. Dalam kondisi seperti itu, memberi perhatian ke orang lain sering terasa seperti beban tambahan yang melelahkan.
Di sisi lain, perkembangan teknologi bukannya memperbaiki keadaan, malah sering memperparah. Meski kita terhubung 24 jam lewat gawai, kualitas perhatian justru merosot. Pesan chat dibaca tapi dibiarkan tanpa balasan. Status keluhan di media sosial cuma jadi tontonan, tanpa ada respons yang berarti. Percakapan digital pun bisa terputus begitu saja, tanpa penutup. Ironis, bukan? Alat yang seharusnya mendekatkan, justru membuat kita makin acuh.
Budaya ini merembet ke ruang sosial yang lebih luas. Berbagai persoalan publik sering kita sambut dengan diam, selama itu tidak mengganggu kepentingan pribadi. Sikap masa bodoh semacam ini perlahan-lahan menggerogoti rasa kebersamaan. Ikatan sosial jadi renggang, kepekaan kita terhadap sesama pun ikut tumpul.
Namun begitu, kita juga perlu memahami akar masalahnya. Budaya mengabaikan ini tidak tumbuh dari ruang hampa. Ia lahir dari kelelahan sosial yang nyata, tekanan hidup, dan ritme kehidupan yang serba instan. Dalam kadar tertentu, menjaga jarak bahkan bisa jadi bentuk pertahanan diri untuk bertahan.
Tetapi, bahayanya muncul ketika sikap ini menjadi kebiasaan yang kita pelihara. Dampaknya mengikis hal-hal mendasar dalam hidup bermasyarakat: empati, solidaritas, kepedulian. Efeknya mungkin tidak langsung terasa, tapi perlahan-lahan ia membentuk ulang kualitas hubungan kita. Komunikasi jadi hambar, rasa saling percaya menipis. Masalah kecil bisa membesar karena tak ada yang peduli untuk menyelesaikannya sejak awal. Jangka panjangnya? Solidaritas sosial melemah, dan kita terbiasa hidup berdampingan tanpa ikatan emosional yang kuat.
Jadi, apa yang bisa dilakukan? Langkah pertama tentu saja dengan menyadarinya. Perubahan tidak harus dimulai dari hal-hal besar. Cukup dengan membalas sapaan dengan tulus, mendengarkan saat orang lain bicara, atau sekadar menaruh perhatian pada keadaan sekitar. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, kehadiran yang tulus justru sesuatu yang langka dan sangat berharga.
Pada akhirnya, kehidupan sosial yang sehat tidak cuma diukur dari kemajuan teknologi atau kesuksesan individu. Tapi lebih pada kemauan kita untuk saling memandang dan memperhatikan. Dengan mengurangi sikap mengabaikan, kita memberi ruang bagi empati untuk bernapas kembali. Dari situlah, dari perhatian-perhatian kecil yang konsisten, kepedulian sosial bisa tumbuh dan menjaga kemanusiaan kita tetap utuh.
Penulis adalah Mahasiswa Universitas Katholik Santo Thomas Medan, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika.



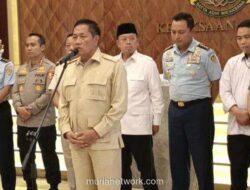







Artikel Terkait
17 Februari dalam Catatan Sejarah: Dari Tsunami Maluku 1674 hingga Kelahiran Buya Hamka dan Michael Jordan
Rooney Ingatkan Risiko Euforia United Strands, Cunha Tegaskan Fokus Hanya pada Poin
Tyler Morton Ungkap Kurangnya Kepercayaan dari Arne Slot Sebabkan Hengkang ke Lyon
Persib Dikabarkan Intip Kiper Belanda Ronald Koeman Jr.