Gelar dosen sering dilihat sebagai lambang kemapanan. Baik secara intelektual maupun ekonomi. Tapi coba lihat lebih dalam, jauh di balik ruang kuliah dan tumpukan jurnal ilmiah. Realitasnya, banyak dosen di Indonesia hidup dalam kondisi yang jauh dari kata sejahtera. Ini ironi yang pahit, terutama bagi dosen muda, mereka yang berstatus non-PNS, dan yang mengabdi di perguruan tinggi swasta. Padahal, secara normatif, negara sudah menjanjikan perlindungan dan penghargaan yang layak untuk mereka.
Persoalan ini bukan cuma urusan personal. Ini adalah problem struktural yang nyentuh jantung kebijakan pendidikan tinggi kita. Bayangkan, ketika dosen terus-menerus bergulat dengan urusan hidup, bagaimana mungkin mereka bisa fokus? Kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pun akhirnya terancam.
Ketimpangan yang Menganga
Menurut teori, pendidikan adalah investasi jangka panjang sebuah bangsa. Dosen sebagai aktor utamanya, semestinya dipandang sebagai aset strategis. Logikanya sederhana: investasi pada kesejahteraan dosen seharusnya berbanding lurus dengan kualitas lulusan dan kemajuan riset.
Namun begitu, teori kerap tak sejalan dengan fakta. Di lapangan, kesejahteraan dosen sangat terfragmentasi. Dosen PNS di PTN mungkin masih punya payung yang relatif lebih aman, meski beban kerjanya makin berat. Di sisi lain, nasib rekan-rekan mereka di PTS yang jumlahnya justru lebih besar seringkali jauh lebih rentan.
Banyak dari mereka bergaji di bawah standar hidup layak. Jaminan kesehatan? Minim. Kepastian pensiun? Belum tentu. Kontrak kerja pun kadang tak jelas. Yang ironis, tuntutan terhadap mereka justru makin tinggi: meneliti, menulis di jurnal bereputasi, mengejar angka kredit, mengabdi pada masyarakat. Semua harus tetap berjalan.
Kondisi ini menciptakan ketegangan peran yang luar biasa. Tuntutan profesional yang tinggi tak didukung oleh dukungan struktural yang memadai. Akibatnya, kelelahan akademik atau academic burnout menjadi hal yang umum. Bukan hal aneh lagi jika banyak dosen terpaksa mencari pekerjaan sampingan hanya untuk sekadar bertahan hidup.
Secara hukum, sebenarnya posisi dosen cukup kuat. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan tegas menyebut dosen sebagai tenaga profesional. Mereka berhak mendapat penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. PP No. 37 Tahun 2009 juga mengatur detail penghasilan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan, dan penghargaan lainnya.
Di atas kertas, regulasinya terlihat ideal. Tapi kita semua tahu, hukum yang bagus harus hidup dalam praktik. Dan di sinilah jurangnya menganga lebar. Regulasi tadi seperti tak punya taring ketika berhadapan dengan realitas di lapangan.
Tri Dharma yang Berubah Beban
Tri Dharma Perguruan Tinggi sejatinya adalah fondasi. Tapi dalam tekanan ekonomi, ia bisa berubah wujud menjadi beban administratif belaka. Mengajar jadi rutinitas, penelitian sekadar untuk memenuhi kewajiban, pengabdian masyarakat kehilangan roh transformasinya.
Belum lagi sistem penilaian kinerja yang kerap hanya mengagungkan angka. Jumlah publikasi, sitasi, indeks. Semua serba kuantitatif, sering mengabaikan kondisi riil yang dihadapi dosen sehari-hari. Institusi seolah menuntut produktivitas tinggi tanpa mau memastikan prasyarat dasarnya terpenuhi dulu.
Masalah ini makin runyam dengan kecenderungan komersialisasi pendidikan tinggi. Kampus dipaksa beroperasi dengan logika pasar, sementara peran negara dalam pendanaan makin berkurang. Dalam logika bisnis seperti ini, dosen sering kali cuma dilihat sebagai pos biaya yang harus ditekan, bukan sebagai subjek utama pencerdasan bangsa.
Padahal, amanat konstitusi jelas. Pasal 31 UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat ini harusnya diterjemahkan dalam kebijakan afirmatif yang nyata untuk kesejahteraan dosen, bukan cuma jadi jargon dalam pidato atau target peringkat universitas dunia.
Lalu, apa yang harus dilakukan?
Pertama, negara perlu berani menetapkan standar penghasilan minimum nasional untuk dosen, terutama di PTS. Kedua, pengawasan implementasi UU Guru dan Dosen harus diperketat. Jangan sampai aturan bagus hanya jadi dokumen mati.
Ketiga, orientasi kebijakan pendidikan tinggi harus diubah. Dari yang berlogika pasar, beralih ke logika keadilan sosial. Keempat, perlakukan dosen sebagai profesional seutuhnya. Mereka punya hak ketenagakerjaan yang jelas, bukan sekadar pengabdi yang diharapkan berkorban tanpa batas.
Pada akhirnya, kesejahteraan dosen bukanlah sebuah hak istimewa. Itu adalah hak yang dijamin undang-undang. Jika negara abai, yang terancam bukan cuma martabat para pendidik, tapi masa depan ilmu pengetahuan dan kualitas generasi penerus bangsa. Pendidikan tinggi tak akan pernah benar-benar maju jika pilar-pilarnya hidup dalam ketidakpastian. Pilihannya sekarang ada di tangan kita: menjadikan dosen sebagai tiang peradaban, atau membiarkan mereka sekadar jadi angka dalam statistik.










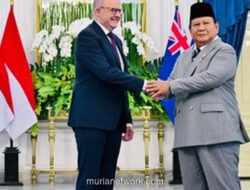
Artikel Terkait
KPK Periksa Rini Soemarno Terkait Dugaan Korupsi Jual Beli Gas PGN
Gerindra Syukur 18 Tahun, Dasco Tekankan Kaderisasi dan Kedekatan dengan Rakyat
Program Makan Bergizi Tetap Berjalan di Bulan Puasa dengan Mekanisme Disesuaikan
MK Gelar Sidang Uji Materi Pasal KUHP Baru yang Dikhawatirkan Kriminalisasi Kritik