Beberapa benda terlihat begitu biasa saja. Karung beras, misalnya. Atau sebatang cerutu. Tusuk sate bekas makan pun begitu. Kita lihat setiap hari, tanpa pikir panjang. Tapi coba perhatikan, dalam situasi tertentu benda-benda tiba-tiba punya nyawa. Ia berubah. Dari sekadar benda mati jadi sebuah tanda. Dan tanda yah, kita semua tahu bicaranya kerap lebih blak-blakan ketimbang pidato resmi.
Ambil contoh karung beras. Sudah lama jadi bahasa visual kekuasaan di sini. Saat negara kesulitan menjelaskan kebijakan yang ruwet, ia mengulurkan beras. Beras dianggap jawaban paling pas untuk persoalan kemiskinan yang kompleks. Ia mengisi perut untuk sementara dan menciptakan kesan bahwa masalah sudah ditangani. Logikanya sederhana: lapar itu soal perut kosong, bukan soal ketimpangan yang sistemik.
Kita jadi sering menyaksikan adegan yang itu-itu lagi. Karung beras diangkut, dibagi-bagikan, lalu difoto. Senyum mengembang dari pemberi dan penerima. Kamera mengabadikannya dengan keyakinan penuh, seolah di dalam karung itu tersimpan bukan cuma gabah, tapi juga keadilan dan janji kesejahteraan.
Padahal, mari kita jujur, beras ya tetap beras. Ia tak akan pernah bisa menjawab pertanyaan mendasar: mengapa kemiskinan itu bisa diwariskan turun-temurun?
Lalu, bagaimana dengan cerutu? Benda ini kecil, tapi sarat makna. Ia tak pernah netral. Cerutu selalu membawa serta aroma kelas dan privilege. Ia hadir di ruang-ruang yang longgar, menandai waktu senggang dan jarak yang aman dari hiruk-pikuk kesulitan hidup. Mengisap cerutu seperti menyatakan bahwa segalanya baik-baik saja, tak ada yang perlu dikejar.
Masalahnya, cerutu jadi bermasalah saat muncul di tempat yang salah. Di tengah lokasi bencana, misalnya. Ia menjadi terlalu jujur. Tanpa perlu kata-kata, cerutu itu menyampaikan pesan yang mungkin tak disadari pemegangnya: bahwa penderitaan orang lain adalah sesuatu untuk diamati dari jarak aman, bukan untuk dirasakan bersama. Bahwa musibah adalah item dalam agenda kerja, bukan sebuah luka kolektif.
Di sinilah ia berubah. Dari barang pribadi jadi simbol publik. Dan sekali jadi simbol publik, niat baik si pemilik tak lagi berarti. Yang berbicara adalah tafsir orang banyak.
Nah, sekarang kita sampai pada sate. Makanan rakyat yang merakyat ini, hangat dan beraroma bara. Tak ada kesan elit. Justru karena itulah, kehadirannya bisa terasa ganjil dalam situasi tertentu. Sate yang disantap di area bencana bukan lagi sekadar makanan. Ia berubah menjadi sebuah pertunjukan.
Bayangkan tusuk-tusuk sate itu, satu persatu, seolah menunjuk ke sebuah jurang yang tak terucap. Jurang antara si peninjau dan yang ditinjau. Yang satu mengunyah, yang lain menonton. Yang satu duduk nyaman, yang lain berdiri di atas lumpur. Secara biologis, semua orang butuh makan, tak ada yang salah. Tapi politik bukan cuma soal kebutuhan biologis, kan? Politik juga hidup dari rasa kepantasan.
Dan rasa kepantasan itu, sayangnya, tidak bisa diatur dengan sekadar peraturan atau surat edaran.
Seringkali kekuasaan lupa, publik sekarang ini membaca gestur seperti membaca buku. Bahkan lebih teliti. Di era di mana setiap orang punya kamera di genggaman, satu adegan singkat bisa menghapus ingatan tentang laporan setebal ribu halaman. Masyarakat mungkin tak hafal angka-angka statistik makro, tapi mereka punya naluri tajam untuk mencium ketimpangan. Mereka bisa merasakan kejanggalan, meski tak selalu bisa merumuskannya dalam teori yang njelimet.
Pada akhirnya, karung beras, cerutu, dan tusuk sate merajut sebuah narasi yang tak pernah dirancang, namun terbaca jelas. Narasi tentang negara yang masih lebih suka berkomunikasi lewat simbol dan benda, ketimbang kehadiran yang tulus dan menyeluruh. Negara merasa cukup dengan menuntaskan prosedur, tapi gagal menangkap etika dalam situasi.
Yang menyedihkan sebenarnya bukan bendanya. Bukan beras, cerutu, atau satenya. Tapi ketenangan bahkan kenyamanan saat semua itu dilakukan. Tak ada keraguan, tak ada rasa canggung. Seolah semua wajar-wajar saja. Seolah penderitaan yang dialami orang banyak cuma latar belakang foto, bukan peristiwa utama yang harus diutamakan.
Dalam dunia ideal, kekuasaan punya kepekaan. Ia paham estetika dan etika: kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan sebaiknya menunda acara makan. Bukan demi pencitraan, tapi karena sadar bahwa setiap sikap tubuh adalah pernyataan politik.
Di negeri kita, justru simbol-simbol kecil seperti inilah yang kerap membocorkan watak sesungguhnya. Kekuasaan tak selalu kejam. Ia seringkali cuma terlalu nyaman. Tidak jahat, hanya kurang peka. Dan dalam politik, ketidakpekaan bisa lebih menyakitkan daripada niat buruk sekalipun.
Tusuk sate itu kini tertancap di memori kolektif kita. Bentuknya kecil, sepele. Tapi seperti luka kecil yang diabaikan, ia bisa menimbulkan infeksi yang berkepanjangan. Mungkin di situlah letak ironi terbesarnya. Bukan pada kebijakan besar yang gagal, tapi pada simbol-simbol sehari-hari yang tak disadari telah meninggalkan bekas yang dalam.



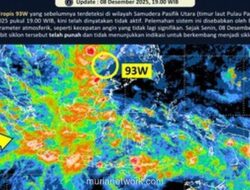

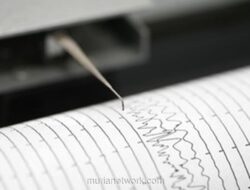





Artikel Terkait
Adies Kadir Segera Dilantik sebagai Hakim MK di Hadapan Presiden Prabowo
Main Hakim Sendiri Berujung Buntung: Korban Pencurian Malah Jadi Tersangka
Persoalan Kertas yang Merenggut Nyawa: Bocah 10 Tahun Bunuh Diri Usai Keluarga Tak Kebagian Bansos
Akhir Tragis Sang Raja Penipuan Online di Perbatasan Myanmar