Potret Buram Pendidikan Indonesia di Tahun 2025
Edisi 14 November 2025
Negara yang Absen di Jam Pelajaran: Sebuah Realita
Di pedalaman Sikka, Nusa Tenggara Timur, ruang kelas sebuah sekolah dasar hanya berdinding papan dan berlantai tanah. Papan tulis retak dan kapur putih hampir habis. Sementara itu, di Manggarai Barat, sebuah SMK di atas bukit harus bertahan tanpa aliran listrik, membuat mesin praktik otomotif tak pernah bisa menyala. Ini bukan cerita lama, melainkan gambaran nyata sistem pendidikan Indonesia di tahun 2025.
Bagi para guru di daerah terpencil, mengajar bukan hanya soal mentransfer ilmu, tetapi juga perjuangan untuk bertahan hidup. Banyak dari mereka harus bercocok tanam sepulang sekolah atau menjadi tukang ojek demi memenuhi kebutuhan keluarga. Honor yang kerap terlambat dibayar berbulan-bulan, tunjangan yang tak menentu, serta status kepegawaian yang tak jelas semakin memperparah kondisi mereka.
Rekrutmen guru kini semakin jauh dari nilai panggilan jiwa. Banyak yang memilih profesi ini karena keterbatasan pilihan, bukan karena kecintaan pada dunia mendidik. Akibatnya, martabat profesi guru semakin memudar. Marak terjadi kasus guru yang memukul murid, mempermalukan siswa di depan umum, hingga pelanggaran etika yang merusak fondasi kepercayaan dalam proses belajar-mengajar.
Seperti dikatakan Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh sesuai kodratnya, dan pendidik hanya berperan sebagai penuntun. Namun, kini rasa hormat siswa terhadap guru telah banyak berkurang. Di era digital, otoritas moral seringkali lebih dipegang oleh para influencer media sosial daripada guru di kelas. Teguran dianggap sebagai penghinaan, hukuman ringan berpotensi dilaporkan ke pihak berwajib. Orang tua murid kerap emosi, kepala sekolah merasa tertekan, dan guru terancam mutasi hanya karena berusaha menegakkan kedisiplinan. Otoritas pun menjadi rapuh di dalam kelas, mengubah hubungan belajar-mengajar menjadi sekadar transaksi formal, bukan lagi proses dialog yang membangun karakter.
Dunia politik dan birokrasi juga turut membebani para guru. Mereka yang tidak mengikuti acara partai penguasa bisa disingkirkan, sementara yang berani menyuarakan ketidakadilan dalam penyaluran dana BOS akan mendapat "peringatan". Di sejumlah daerah, tunjangan guru kerap ditahan bagi mereka yang dianggap tidak loyal. Kondisi ini membuat guru lebih fokus pada menjaga posisinya daripada mempertahankan integritas dan nurani dalam mendidik.
Berbagai program reformasi pendidikan yang dijanjikan pemerintah pusat seolah mandek di meja birokrasi. Sekolah tetap kekurangan dana, sementara belanja daerah masih sangat bergantung pada pusat. Ketika daerah dinilai gagal mengelola pendidikan, pusat pun turun tangan dengan proyek-proyek baru seperti digitalisasi sekolah, bantuan tablet, dan program literasi. Sayangnya, program-program ini seringkali hanya berhenti pada pencapaian kuantitas serapan, bukan peningkatan kualitas pembelajaran yang substantif.
Istilah "bonus demografi" kerap digaungkan, namun di banyak pelosok negeri, yang muncul justru beban generasi muda yang tidak terurus dengan baik. Anak-anak harus belajar dengan guru yang kelelahan, di dalam ruang kelas yang nyaris rubuh, dan menggunakan kurikulum yang lebih sering berganti daripada harapan untuk memperbaiki nasib mereka.
Pada akhirnya, krisis pendidikan Indonesia bukan hanya persoalan anggaran atau kebijakan, tetapi juga cerminan dari moralitas bangsa yang retak. Negara hadir dengan membanggakan proyek infrastruktur besar, tetapi absen di setiap jam pelajaran yang menentukan masa depan anak bangsa. Negara bangga memiliki kereta cepat, tetapi lupa memperbaiki jalan berlumpur yang setiap hari dilalui guru honorer untuk sampai ke sekolah. Kehadiran negara di dunia pendidikan seringkali hanya lewat proyek, bukan melalui jiwa dan semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.








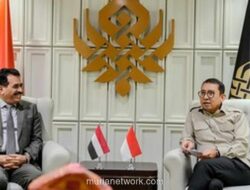


Artikel Terkait
KPK Buka Ruang Klarifikasi Proaktif untuk Menag Soal Penggunaan Jet Pribadi OSO
Jenazah Dua Remaja Korban Tenggelam di Sungai Grobogan Ditemukan Tim SAR
Trump Puji Prabowo sebagai Pemimpin Tangguh di Forum Perdamaian Gaza
Kanselir Merz Dukung Larangan Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun