Pernah nggak sih, lagi scroll media sosial, nemu orang yang ngomongin suatu topik dengan sangat "dalam"? Tapi kalau ditelusuri, ternyata dia bukan ahlinya sama sekali. Ujung-ujungnya, pembahasannya jadi melayang, nggak berdasar, malah sering nyasar ke teori konspirasi. Inilah potret nyata jagat digital kita sekarang: semua orang merasa berhak berpendapat tentang apa pun, tanpa perlu jadi ahli. Hasilnya? Banyak yang cuma jadi "sok tahu".
Fenomena menarik ini sebenarnya sudah dijelaskan dengan cukup apik oleh Tom Nichols lewat bukunya, Matinya Kepakaran. Buku terjemahan dari The Death of Expertise (2017) ini diterbitkan oleh KPG pada akhir 2018. Inti dari "kematian kepakaran" itu sendiri, bagi Nichols, adalah kaburnya batas yang dulu jelas antara profesional dan awam, antara yang benar-benar tahu dan yang cuma "merasa" tahu berkat Google dan Wikipedia.
Apa Sih Bedanya Pakar dan Orang Awam?
Lalu, siapa yang bisa disebut pakar? Nichols mendefinisikannya sebagai orang yang punya pengetahuan komprehensif dan otoritatif di suatu bidang. Singkatnya, perkataan mereka bisa dipercaya karena didukung keahlian yang mendalam. Contohnya gampang: kalau sakit, kita ke dokter. Mau bangun rumah, cari arsitek. Urusan keuangan perusahaan, serahkan ke akuntan.
Mereka ini punya pengetahuan dan skill yang jauh lebih tajam dibanding orang kebanyakan di bidangnya. Jadi wajar kalau kita menjadikan mereka rujukan.
Nah, pembedanya dengan orang awam ada di mana? Menurut Nichols, perbedaannya terletak pada gabungan antara pendidikan formal, bakat, pengalaman panjang, dan yang penting: pengakuan dari rekan sejawat. Ijazah dan sertifikasi itu tanda yang paling kasat mata, sekaligus bukti bahwa kemampuannya sudah diuji dan memenuhi standar.
Peran Internet dalam "Membunuh" Kepakaran
Di sini, peran internet sangat sentral. Bagi Nichols, dunia online justru banyak dipenuhi omong kosong terutama soal politik. Media sosial dan situs web dengan mudah mengubah rumor jadi "fakta". Parahnya, informasi salah itu bisa bertahan bertahun-tahun di internet, nggak seperti koran kemarin yang langsung basi. Ia awet dan selalu muncul di hasil pencarian.
Tapi, jangan salah. Internet bukan satu-satunya biang kerok. Ada faktor lain yang lebih dalam: bias konfirmasi. Nichols mengutip Frank Bruni yang bilang, para penggiat antivaksin misalnya, akan selalu saja mencari "penelitian" sampah untuk mendukung pendapat mereka. Di era digital, kamu berkelana di dunia maya sampai menemukan kesimpulan yang kamu inginkan dari awal. Klik sana-sini cari pembenaran, sampai akhirnya nggak bisa bedakan mana yang cuma lihat sekilas dan mana yang benar-benar kamu pahami.
Nichols bahkan berani bilang, mengakses internet bisa bikin orang lebih bodoh. Kok bisa? Karena aktivitas mencari informasi itu memberi ilusi belajar. Padahal, yang terjadi adalah kita tenggelam dalam lautan data yang nggak kita pahami. Pusing sendiri akhirnya.
Jurnalisme Modern dan Tantangannya
Abad ke-21 memang memberi kita lebih banyak sumber berita. Tapi, banyak belum tentu bagus. Kemajuan teknologi mempermudah siapa pun membuat media, yang konsekuensinya jelas: kompetisi makin ketat. Kompetisi ini memecah pembaca ke dalam kelompok-kelompok politik dan demografi tertentu. Banyaknya saluran juga berarti banyaknya wartawan yang bekerja, entah mereka benar-benar kompeten atau tidak.
Masalahnya nggak cuma di situ. Sekarang, interaksi kita dengan berita sudah berubah total. Orang Nichols ambil contoh di Amerika nggak lagi cuma baca koran atau terima berita dari TV secara pasif. Mereka sekarang diminta pendapatnya, seringkali secara langsung dan real time.


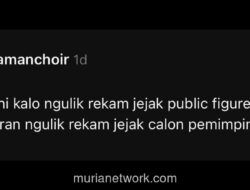




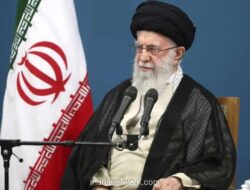



Artikel Terkait
Israel Klaim Khamenei Tewas, Iran Bantah dan Nyatakan Pemimpinnya Selamat
Iran Lancar Serangan Balasan Rudal ke Israel dan Pangkalan AS di Timur Tengah
Imsak Jakarta 1 Maret 2026 Pukul 04.33 WIB, Azan Subuh 04.43 WIB
Lamine Yamal Cetak Hattrick, Barcelona Hancurkan Villarreal 4-1