Sejak akhir November lalu, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diguncang bencana. Banjir bandang dan tanah longsor datang bertubi-tubi, menorehkan salah satu tragedi hidrometeorologi paling kelam dalam sepuluh tahun terakhir. Ribuan nyawa melayang. Ratusan ribu orang terpaksa mengungsi, meninggalkan rumah yang hancur, sekolah yang rusak, puskesmas yang lumpuh, serta infrastruktur vital yang porak-poranda. Ini jelas bukan sekadar cuaca ekstrem musiman. Skala kehancurannya menunjukkan ada yang salah secara struktural dalam cara kita mengelola pembangunan dan lingkungan.
Kerugian ekonominya fantastis, mencapai puluhan triliun rupiah. Angka itu bukan cuma soal beton yang retak atau jembatan yang putus. Tapi juga tentang produktivitas yang lenyap, rantai pasokan regional yang kacau balau, dan beban anggaran negara untuk pemulihan yang membengkak. Intinya, bencana di Sumatera ini adalah pengingat yang mahal: risiko ekologis yang kita abaikan dalam perencanaan, pada akhirnya akan balik menghantam kita sebagai krisis ekonomi dan kemanusiaan.
Memang, hujan ekstrem yang memicu bencana ini tak bisa dipisahkan dari perubahan iklim global. Namun begitu, faktor alam itu bertemu dengan masalah klasik yang tak kunjung tuntas: degradasi lingkungan. Deforestasi, alih fungsi lahan di hulu sungai, dan tata kelola DAS yang lemah sudah jadi cerita lama. Akibatnya, hutan sebagai penyangga alamiah hilang kemampuannya menyerap air. Hujan deras pun dengan mudah berubah menjadi banjir bandang dan longsor yang mematikan.
Dari sisi kebijakan, kondisi ini menunjukkan kerentanan bencana yang kian tinggi. Tekanan pada lingkungan makin berat, sementara kemampuan kita beradaptasi baik secara ekologis maupun kelembagaan jalan di tempat. Risiko bencana sekarang bukan lagi sesuatu yang kebetulan. Ia adalah konsekuensi logis dari pola pembangunan yang lebih mementingkan eksploitasi sumber daya daripada daya dukung lingkungan. Selama pola pikir ini tak berubah, bencana serupa akan terus berulang, dengan dampak yang makin besar.
Di sisi lain, tragedi ini juga memperlihatkan betapa erat kaitannya krisis ekologi dengan ketahanan ekonomi nasional. Jalan dan jembatan yang rusak menghambat distribusi barang. Sekolah dan rumah sakit yang terganggu menurunkan kualitas SDM untuk jangka panjang. Bagi warga yang terdampak, ini berarti kehilangan segalanya: aset, mata pencaharian, akses pada layanan dasar. Jadi, risiko iklim bukan cuma ancaman bagi alam, tapi juga pondasi ekonomi dan sosial kita.
Semua ini menegaskan satu hal: pendekatan pembangunan yang memisahkan pertumbuhan ekonomi dari kelestarian lingkungan sudah ketinggalan zaman. Di tengah risiko iklim yang makin sistemik, ekonomi berkelanjutan justru harus jadi strategi rasional untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Investasi di mitigasi iklim dan pengurangan risiko bencana terbukti jauh lebih murah ketimbang biaya penanganan darurat yang sifatnya cuma reaktif.
Lalu, apa solusinya? Kerangka green growth bisa jadi alternatif. Ia menempatkan keberlanjutan sebagai prasyarat, bukan penghalang, untuk pertumbuhan. Lewat efisiensi sumber daya, transisi energi bersih, dan pengelolaan bencana berbasis sains, pembangunan bisa tetap menciptakan nilai ekonomi tanpa merusak ekosistem. Dalam jangka panjang, pendekatan ini justru membuat ekonomi kita lebih tahan terhadap guncangan.
Peran swasta di sini krusial. Di luar tanggung jawab sosial, dunia usaha punya kapasitas finansial dan inovasi untuk mendorong transisi ke ekonomi hijau. Instrumen seperti obligasi hijau atau investasi berdampak bisa dialirkan untuk mendanai restorasi ekosistem atau membangun infrastruktur tahan iklim. Keterlibatan mereka bukan cuma meringankan beban negara, tapi juga membuka peluang ekonomi baru yang selaras dengan prinsip keberlanjutan.
Tapi semua upaya itu akan percuma tanpa kebijakan publik yang konsisten dan terpadu. Selama ini, penanggulangan bencana kita masih didominasi pola responsif fokusnya pada tanggap darurat dan rehabilitasi. Padahal, masalahnya struktural dan butuh intervensi jangka menengah-panjang yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan.
Menurut sejumlah pengamat, bencana Sumatera ini harusnya jadi titik balik. Pemerintah, akademisi, dan swasta perlu memasukkan ketahanan ekologis secara sistematis ke dalam agenda ekonomi. Caranya? Perkuat tata kelola DAS berbasis data risiko, tingkatkan investasi mitigasi lewat instrumen keuangan hijau, beri insentif bagi praktik bisnis rendah emisi, dan integrasikan kebijakan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan agar kita bergeser dari pola reaktif ke preventif.
Tanpa perubahan paradigma ini, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus bencana dan pemulihan yang melelahkan. Sebaliknya, dengan menjadikan keberlanjutan ekologis sebagai fondasi, musibah di Sumatera bisa jadi momentum untuk mengoreksi arah pembangunan. Menuju pertumbuhan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di tengah krisis iklim yang kian nyata di depan mata.





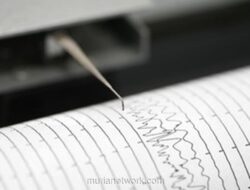





Artikel Terkait
IHSG Terkoreksi, Analis Masih Lihat Peluang Rally ke Level 8.440
DJP Resmi Ingatkan Publik Waspadai Gelombang Penipuan Berkedok Institusi Pajak
HIPMI Soroti Penyusutan Kelas Menengah Pengusaha di Sidang Pleno Makassar
Tembok Mewah Ambruk di Kalibata, Halaman SMPN 182 Rusak Parah