Kedua orang ini, Al-Ghazali dan Ibn Rusyd, seringkali diadu-adukan. Padahal, kalau dicermati, mereka saling melengkapi. Al-Ghazali lebih fokus pada tazkiyatun nafs, membersihkan hati agar pikiran jadi bening. Sementara Ibn Rusyd menekankan nadzar dan istidlal, yaitu mengamati dan menyelidiki bukti-bukti, agar keyakinan makin kokoh.
Intinya sama sih, cuma caranya aja yang beda: manusia yang ideal adalah yang bisa menyeimbangkan antara otak dan kalbu.
Masalahnya, zaman sekarang kita maunya yang cepat. Jawaban instan, pemahaman yang dangkal, baca sekilas, komentar langsung, bahkan marah pun dalam sekejap. Dalam kondisi kayak gini, hikmah ala Islam jadi terasa asing. Padahal, justru di sanalah solusi untuk banyak kegaduhan budaya kita.
Hikmah dalam Islam itu nggak cuma soal kepintaran. Ia lebih kepada keseimbangan. Antara akal dan hati, antara ilmu dan kesadaran batin. Seperti dalam QS. Al-Baqarah:
Hikmah nggak datang dari banyaknya buku yang kita lahap. Tapi dari heningnya kita merenung. Ia muncul saat pikiran kita terbuka menerima kebenaran, bukan saat kita ngotot mengikuti ego.
Mungkin inilah pelajaran paling berharga dari Islam untuk kita semua sekarang: berpikir itu bukan cuma aktivitas otak. Ia juga latihan untuk jiwa. Pikiran yang jernih, selalu bersumber dari hati yang bersih.
Dunia sibuk mencari makna dengan teknologi. Islam justru mengajak kita menyelam ke dalam diri. Ke tempat di mana pikiran dan iman bisa berdialog dengan damai.
Dan di situlah, hikmah sejati bersemayam. Dalam keheningan. Bukan di tengah kebisingan yang tak ada ujungnya.

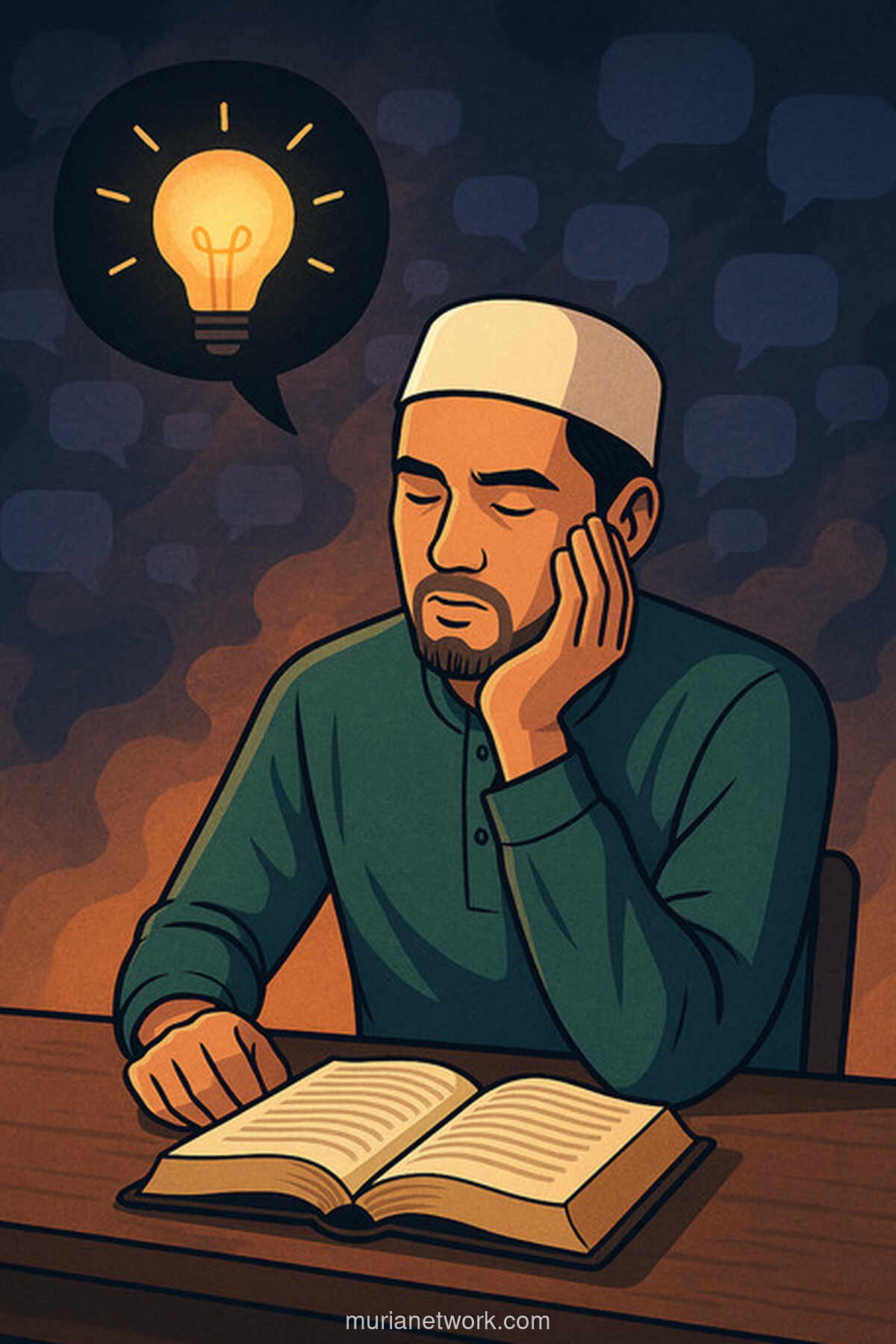









Artikel Terkait
Prasetyo Bantah Isu Pertemuan Prabowo dengan Oposisi
Restoran Keluarga dan Luka Masa Lalu: Kisah Cinta Kedua di Predestined Love
Malam Haru di Cilandak, Sjafrie Sjamsoeddin Berduka untuk Sahabat Seangkatan
Bercak Darah di Kamar Lula Lahfah Diduga Darah Menstruasi