Beberapa minggu lalu, jagat maya Indonesia kembali gempar. Sebuah video lama yang menampilkan interaksi seseorang dengan sekelompok anak beredar luas. Meski cuma potongan singkat tanpa konteks utuh, fragmen visual itu sukses memicu gelombang emosi yang meluas. Hanya dalam hitungan jam, diskusi kecil berubah jadi badai perdebatan massif. Sebuah pola yang makin akrab di tengah lanskap komunikasi kita yang serba cepat ini.
Fenomena ini memperlihatkan satu hal penting: publik tidak cuma bereaksi pada konten, tapi juga pada cara konten itu memicu mekanisme psikologis dan sosial yang sudah lama mengendap di masyarakat. Potongan digital itu ibarat virus bukan karena bahayanya secara intrinsik, tapi karena ia menemukan inang yang tepat: emosi publik, nilai-nilai sosial yang sensitif, dan algoritma media sosial yang mendorongnya berkembang biak.
Arus Bawah Psikologis
Kalau kita tilik dari sudut pandang ilmu kognitif, kesan pertama hampir tak pernah netral. Kahneman (2011) bilang, ketika manusia menghadapi stimulus mengejutkan terutama yang melibatkan kelompok rentan seperti anak otak langsung mengaktifkan mekanisme penilaian cepat. Lebih dekat ke insting ketimbang analisis. Mekanisme ini sebetulnya adaptif secara evolusi, tapi kurang cocok dengan ritme informasi digital yang serba terpotong dan cepat.
Video pendek itu cuma pemicu. Respons besar muncul dari cara otak memproses fragmen: bukan lewat analisis mendalam, tapi lewat intuisi moral. Nickerson (1998) menyebutnya bias konfirmasi kecenderungan untuk memperkuat impresi awal. Publik merasa sudah paham konteks lengkap dari potongan sempit, padahal pemahaman itu dibangun intuisi, bukan fakta utuh.
Perilaku ini juga selaras dengan riset perilaku konsumen. Bettman et al. (1998) dan Payne et al. (1993) menunjukkan bahwa manusia sering memilih jalur pintas (low-effort processing) saat menghadapi informasi kompleks. Dalam konteks video viral, warganet bertindak layaknya konsumen informasi: memilih interpretasi yang paling mudah dan selaras dengan emosi dominan.
Begitu komentar awal bernada marah muncul, publik menafsirkannya sebagai norma moral kolektif. Inilah mekanisme social proof yang dijelaskan Cialdini (2007). Kita tidak cuma melihat konten, tapi juga bagaimana orang lain melihatnya. Emosi pun bergerak seperti gelombang.
Data tambahan memperkuat gambaran ini: Survei Mastel (2023) mencatat 68% warganet Indonesia mengaku pernah menyebarkan konten viral tanpa verifikasi. Sementara riset APJII 2024 menunjukkan 45% responden merasa “terbawa emosi” saat melihat konten bernuansa moral.
Fenomena ini juga memunculkan heuristik representasi kecenderungan untuk menyamaratakan satu potongan perilaku sebagai gambaran utuh suatu kelompok sosial. Akibatnya, publik bukan lagi menilai video itu, tapi menilai kelompok yang mereka bayangkan ada di baliknya. Semua lapisan ini diperkuat oleh apa yang Sloman & Fernbach (2017) sebut illusion of explanatory depth: keyakinan bahwa kita paham sesuatu secara mendalam, padahal yang kita pahami cuma permukaannya.
Bayangan Algoritmik
Di atas arus psikologis tadi, ada lapisan lain yang memperkuat gejolak: algoritma. Penelitian Vosoughi, Roy, dan Aral (2018) membuktikan bahwa informasi yang memicu kemarahan moral menyebar jauh lebih cepat ketimbang informasi netral. Algoritma media sosial tak punya nurani; ia cuma membaca pola keterlibatan: seberapa cepat respons muncul, seberapa intens emosinya, dan seberapa sering interaksi berulang.
Ketika fragmen visual menyangkut anak masuk kategori high-valence emotion indeks emosi yang melonjak tajam algoritma langsung menangkap sinyal itu dan memperluas distribusinya. Publik pun merasa isu itu “ada di mana-mana”, meski sebenarnya cuma amplifikasi digital.
Yang sering terlupakan: algoritma tidak netral. Ia dirancang manusia sering kali insinyur dari Silicon Valley dengan nilai dan budaya yang berbeda dari masyarakat Indonesia. Sistem deteksi harmful content di negara sekuler kerap tak paham nuansa hubungan antara figur agama, otoritas moral, dan sensitivitas masyarakat Nusantara. Saat standar itu diterapkan di sini, respons publik dan mekanisme platform sering tak seirama.
Jadi, teknologi bukan dalang tunggal. Algoritma memengaruhi kita, tapi cara kita meresponsnya sangat ditentukan nilai-nilai lokal, norma sosial, dan narasi yang kita warisi. Di negara dengan sensitivitas moral tinggi seperti Indonesia, satu potongan video bisa picu reaksi sosial yang beda jauh dengan negara yang lebih sekuler. Intinya, teknologi cuma panggungnya. Manusialah yang bawa naskah, aktor, dan tafsirannya masing-masing.
Selain itu, ada yang bisa disebut algoritma wacana: aturan tak tertulis tentang siapa yang layak dicurigai, siapa yang layak dibela, dan bagaimana isu dimaknai. Foucault (1972) bilang, wacana adalah struktur yang membentuk subjek, bukan cuma wadah. Dalam isu anak, wacana perlindungan moral menjadi gravitasi yang menarik semua argumen ke titik urgensi yang sama. Ketika algoritma platform bertemu algoritma wacana, ruang digital berubah jadi akselerator makna. Emosi publik bukan cuma menyebar, tapi diperbesar dan dipercepat secara sistemik.
Di balik semua itu, ada dimensi lain yang sering luput: viralitas adalah bisnis. Setiap lonjakan kemarahan, setiap ribuan komentar yang muncul dalam satu malam, adalah sinyal ekonomi bagi platform. Dalam ekonomi perhatian, emosi adalah mata uang. Keterlibatan meski dipicu keresahan adalah komoditas yang diperdagangkan.







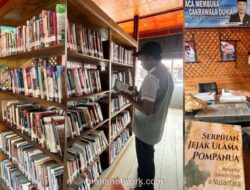



Artikel Terkait
Lechumanan Desak Polisi Tahan Roy Suryo, Kubu Jokowi Serahkan ke Jalur Hukum
Kedai Baca di Bone Jadi Favorit Ngabuburit Ramadan, Fasilitas Lengkap dan Gratis
Buka Puasa di Banjarmasin Hari Ini Pukul 18.43 WIB
KPK Tahan Pejabat Bea Cukai Terkait Kasus Suap dan Rp 5,19 Miliar di Apartemen