Kunjungan Prabowo ke Ibu Kota Nusantara awal tahun ini, lagi-lagi, memantik perdebatan yang tak kunjung usai. Ke mana sebenarnya arah kota ini? Banyak yang bertanya-tanya.
Isu yang terus mengemuka adalah penegasan IKN sebagai "ibu kota politik". Bagi sebagian kalangan, status ini terdengar seperti penyempitan makna, bahkan kemunduran dari cita-cita awal sebuah ibu kota negara yang utuh. Tak sedikit yang curiga, jangan-jangan ini strategi untuk menutupi fakta bahwa pembangunannya sendiri sedang mandek. Kekhawatiran terbesarnya jelas: IKN nantinya cuma jadi kota administratif yang sunyi, tanpa denyut kehidupan kota yang sebenarnya.
Lebih Dari Sekadar Politik
Namun begitu, memandang IKN hanya dari kacamata "ibu kota politik" itu terlalu sederhana. Kalau kita tilik sejarah, justru fungsi politik seringkali jadi cikal bakal pertumbuhan sebuah kota. Persoalannya bukan pada fungsi politiknya itu sendiri. Yang lebih penting adalah, apakah fungsi itu bisa bertransformasi jadi fondasi bagi sebuah polis sebuah kota yang benar-benar hidup, produktif, dan punya makna bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya.
Apa itu polis? Dalam tradisi klasik, ia bukan cuma kumpulan gedung atau pusat pemerintahan. Polis adalah ruang hidup bersama. Tempat di mana warga tidak sekadar numpang tinggal, tapi juga terlibat, berkreasi, dan membangun makna secara kolektif.
Pemikir seperti Aristoteles, sekitar 350 SM, sudah mendefinisikannya sebagai bentuk tertinggi kehidupan bermasyarakat. Tujuannya mencapai "the good life", hidup yang baik. Jadi, nilai sebuah kota diukur dari kualitas hubungan warganya, bukan dari megahnya infrastruktur.
Teori urban modern punya pandangan serupa. Jane Jacobs, pada 1961, menekankan bahwa denyut kota berasal dari keberagaman aktivitas, kepadatan yang manusiawi, dan interaksi spontan di ruang publik. Kota yang cuma jadi pusat kekuasaan itu rapuh. Ia monofungsional. Sebaliknya, sebuah polis membutuhkan warga yang menetap karena pilihan, ekonomi yang tumbuh dari aktivitas riil, dan ruang publik yang hidup. Tanpa itu, kota kehilangan jiwanya.
Lalu ada Henri Lefebvre dengan konsep "hak atas kota". Baginya, ini soal siapa yang berkuasa menentukan bentuk dan fungsi ruang urban. Sementara Manuel Castells mengingatkan, kota modern adalah arena pertarungan antara logika kapital, negara, dan masyarakat. Polis hanya mungkin jika ada keseimbangan.
Nah, dalam konteks IKN, pertanyaan kuncinya jadi bergeser. Bukan lagi "apakah ini ibu kota politik?", melainkan "apakah kota ini dirancang untuk melahirkan warga, bukan sekadar aparatur?" Tantangan sebenarnya adalah mengelola transisi dari kota kekuasaan menuju kota warga. Sejarah akan mencatat, transisi inilah yang menentukan nasibnya: hidup sebagai kota seutuhnya, atau membeku jadi monumen.
Embrio Kota
Di sisi lain, kita tidak bisa menafikan bahwa politik sering jadi embrio. Lihat saja sejarah. Athena, Roma, Beijing semua bermula dari pusat kekuasaan sebelum akhirnya bertransformasi jadi metropolis yang kompleks.
Dalam era modern, pola serupa terlihat. Washington D.C., Canberra, dan Brasília sengaja dibangun sebagai ibu kota politik, bukan tumbuh organik dari pusat dagang.






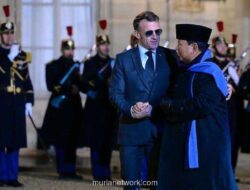




Artikel Terkait
Tanggul Kali Angke Ditambal, Genangan di Pinang Griya Akhirnya Surut
Trump Sebut Pasukan Inggris Di Belakang, London Murka
Tito Karnavian Tinjau Langsung Pemulihan Pasca-Bencana di Aceh Tamiang
Pohon Tumbang Hantam Atap, SPBU Pramuka Raya Terpaksa Tutup Total