Istirahat seharusnya hal yang sederhana, bukan? Tubuh lelah, ya berhenti. Pikiran penat, ya diberi ruang. Tapi kenyataannya nggak sesimpel itu. Bagi banyak dari kita, momen berhenti justru dibayangi perasaan bersalah. Seperti ada dosa kecil karena memilih untuk tidak produktif, yang harus segera ditebus dengan kerja dua kali lipat setelahnya.
Perasaan itu nggak tiba-tiba muncul. Ia tumbuh pelan-pelan dari kebiasaan hidup yang mengukur nilai seseorang dari kesibukannya. Sejak kecil kita dicekoki pemahaman: rajin itu mulia, malas itu aib. Nah, di situlah masalahnya. Istirahat seringkali salah kaprah, dikategorikan sebagai kemalasan.
Di tengah budaya yang memuja kesibukan, berhenti sejenak terlihat seperti kemunduran. Saat kita duduk diam, sering muncul bisikan di kepala, "Kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih berguna." Padahal, tubuh lelah bukan karena kurang semangat, tapi karena memang butuh pemulihan. Titik.
Secara biologis, manusia nggak didesain untuk terus 'on'. Sistem saraf kita bekerja dengan ritme alami: fokus, lalu istirahat. Tanpa jeda yang cukup, konsentrasi buyar, emosi jadi gampang tersulut, dan kelelahan menumpuk jadi kronis. Intinya, istirahat bukanlah bonus atau hadiah. Ia adalah bagian vital dari siklus kerja itu sendiri.
Namun begitu, kita sering memasang syarat. Istirahat baru "diizinkan" kalau semua tugas sudah beres. Padahal, dalam kenyataan, daftar tugas itu hampir nggak pernah habis. Selalu ada yang bisa dikerjakan, selalu ada yang menunggu. Alhasil, istirahat terus ditunda, dan rasa bersalahnya malah menetap.







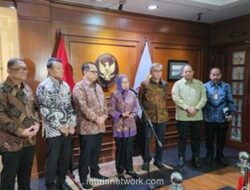



Artikel Terkait
Pantai Akkarena Makassar: Destinasi Favorit Warga dengan Pemandangan Senja Memikat
Banjir Rendam Sejumlah Titik di Makassar, Tello Baru Terparah
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Sukabumi, Tidak Ada Laporan Kerusakan
Harga Emas Batangan Pegadaian Naik Rp 38.000 per Gram