Seorang dosen menggugat undang-undang. Hal itu terdengar janggal, bukan? Profesi yang selama ini digambarkan sebagai penjaga nalar dan pilar peradaban, ternyata harus berjuang lewat jalur pengadilan hanya untuk menegaskan haknya yang paling mendasar: hidup layak. Gugatan terhadap UU Guru dan Dosen itu sebenarnya lebih dari sekadar urusan angka di slip gaji. Ini adalah tanda nyata dari krisis makna yang mendalam, yang menggerogoti wacana pendidikan nasional kita.
Memang, Pasal 51 dan 52 UU tersebut terlihat cukup menjanjikan. Dosen berhak dapat penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum plus jaminan kesejahteraan. Tapi coba lihat lebih dekat. Frasa "di atas kebutuhan hidup minimum" itu samar sekali. Tak ada indikator operasional yang jelas, apalagi mekanisme pengawasan yang tegas. Ketidakjelasan ini, pada akhirnya, malah membuka ruang untuk penafsiran sepihak. Dan dalam prakteknya, yang sering jadi korban adalah dosen-dosen di perguruan tinggi swasta.
Menurut sejumlah saksi, ada jarak yang menganga lebar antara janji negara dan kenyataan yang dihadapi dosen sehari-hari. Di satu sisi, narasi resmi menyebut dosen sebagai profesi terhormat dan sejahtera. Di sisi lain, banyak dari mereka terpaksa menerima penghasilan yang bahkan tak mencapai Upah Minimum Regional. Beban tridarma yang berat dan tuntutan kinerja akademik tinggi tetap ada, sementara imbalan material tak kunjung memadai. Ketika wacana kebijakan tak selaras dengan realitas sosial, yang terjadi adalah krisis legitimasi. Sistem pendidikan itu sendiri mulai dipertanyakan.
Media dan diskursus publik, sayangnya, sering memperparah keadaan. Dosen hampir selalu direpresentasikan sebagai figur idealis, menjalani 'panggilan jiwa' dengan pengabdian tanpa batas. Gambaran yang mulia, tentu saja. Namun begitu, narasi semacam ini punya efek samping yang berbahaya: ia menormalkan kerentanan ekonomi mereka. Pembicaraan soal hak-hak ekonomi, relasi kerja yang adil, dan perlindungan profesional jadi terpinggirkan, tenggelam dalam romantisme simbolik yang justru menutupi persoalan struktural yang nyata.
Inilah mengapa gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu penting. Langkah ini menggeser posisi dosen secara fundamental. Dari sekadar subjek moral yang diharapkan berkorban, menjadi subjek hukum yang menuntut hak konstitusionalnya. Sebagai warga negara. Langkah ini juga membongkar kontradiksi yang selama ini ada: pendidikan disebut-sebut sebagai investasi bangsa, tetapi para aktor intelektual di dalamnya justru sering dianggap sebagai beban biaya.
Dari kacamata ekonomi politik komunikasi, bahasa dalam undang-undang itu bekerja dengan cara yang licin. Istilah-istilah normatif seperti "kesejahteraan" dan "penghasilan layak" berfungsi sebagai retorika untuk legitimasi. Ia menciptakan kesan keberpihakan, tapi tanpa jaminan implementasi yang konkret. Alhasil, dosen terpaksa membuktikan sendiri haknya untuk hidup layak melalui meja hijau sebuah jalan panjang yang seharusnya tak perlu ditempuh dalam sistem pendidikan yang sehat.
Pada akhirnya, ini bukan cuma soal menunggu putusan hakim. Gugatan ini adalah momen refleksi bagi kita semua. Saatnya meninjau ulang cara kita memaknai profesi dosen. Apakah mereka benar-benar dianggap sebagai aset intelektual bangsa yang harus dijaga keberlanjutannya, atau hanya sekadar simbol retoris dalam pidato-pidato tentang kemajuan pendidikan? Selama pertanyaan mendasar ini belum dijawab dengan konsisten lewat kebijakan dan tindakan nyata krisis makna ini akan terus berulang, menghantui masa depan pendidikan tinggi Indonesia.


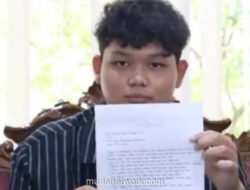








Artikel Terkait
AC Milan Tersungkur di San Siro, Kalah 0-1 dari Parma
Pakar Hukum Soroti Daya Paksa dan Krisis Kepercayaan Publik pada Aparat
Jadwal Imsak dan Subuh Medan 23 Februari 2026: Imsak Pukul 05.12 WIB
Imsak Yogyarta Pukul 04.16 WIB, Ulama Ingatkan Keberkahan Sahur dan Kuatkan Niat