Demokrasi dan liberalisme? Dua hal ini tak selalu berjalan beriringan. Ambil contoh demokrasi Athena kuno. Sistem itu memang mengedepankan partisipasi warga secara langsung, tapi tetap punya sejumlah batasan sosial dan moral yang ketat.
Di Amerika Serikat, perjalanan demokrasinya juga mengalami transformasi besar. Awalnya dibangun dengan fondasi nilai-nilai agama dan komunitas yang kuat. Namun, setelah Revolusi Industri dan menguatnya kapitalisme modern, demokrasi di sana bergeser ke arah liberal yang menekankan kebebasan hampir tanpa batas.
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Para pendiri bangsa kita dari dulu sudah punya visi yang jelas. Mereka tak pernah membayangkan Indonesia menjadi negara liberal. Soekarno dengan tegas bilang, "Demokrasi kita bukan demokrasi Barat. Demokrasi kita adalah demokrasi gotong royong." Pancasila sendiri dirumuskan sebagai jalan tengah menyeimbangkan kebebasan dengan moralitas, kepentingan rakyat, musyawarah, dan tentu saja nilai-nilai ketuhanan.
Bung Hatta punya pendapat serupa. Berkali-kali ia menolak liberalisme, baik di bidang ekonomi maupun politik. Menurutnya, paham itu tak cocok dengan struktur masyarakat Indonesia yang lebih komunal.
Namun begitu, belakangan muncul beberapa gejala yang mengkhawatirkan. Indonesia seperti mulai terdorong ke arah demokrasi liberal. Politik identitas kepentingan kelompok kecil kian mencolok, di mana suara mayoritas sering dianggap tak relevan jika bertentangan dengan ide kebebasan ala Barat. Media sosial jadi ruang kebebasan tanpa batas yang kerap menabrak etika, merusak kehormatan, bahkan menghina agama. Komersialisasi politik pun makin menjadi demokrasi liberal cenderung memunculkan politik uang karena orientasinya memang persaingan bebas. Belum lagi pengaruh lembaga asing yang mendorong nilai-nilai demokrasi liberal sebagai standar universal, padahal belum tentu cocok dengan kultur kita.
Menurut Prof. Yudi Latif, ahli Pancasila, demokrasi Indonesia tak boleh mengabaikan nilai Ketuhanan dan musyawarah. "Demokrasi harus berakar pada kearifan lokal dan moralitas bangsa," tegasnya. "Demokrasi tanpa nilai hanyalah prosedur kosong."
Pandangan senada datang dari Samuel P. Huntington dalam "The Clash of Civilizations". Ia mengingatkan bahwa tak ada satu bentuk demokrasi yang cocok untuk semua bangsa. Setiap peradaban punya dasar nilai yang berbeda-beda. Amartya Sen, ekonom peraih Nobel, juga bilang demokrasi harus dikaitkan dengan nilai-nilai budaya setempat agar tidak kehilangan arah moral.
Dalam tradisi Islam, konsep syura atau musyawarah sebenarnya adalah bentuk demokrasi yang menghormati kebijaksanaan kolektif, tapi tetap dalam bingkai syariat. Imam Al-Mawardi dalam "Al-Ahkam As-Sulthaniyyah" menekankan pentingnya kepemimpinan yang tunduk pada nilai-nilai ilahi, bukan sekadar kehendak bebas manusia. Ibnu Taimiyah pun punya pandangan jelas: "Kekuasaan harus diarahkan untuk menegakkan keadilan, dan keadilan tidak akan tegak tanpa nilai-nilai agama."
Ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa demokrasi dalam Islam boleh diambil, asal tidak menabrak prinsip agama. "Islam menerima demokrasi dalam aspek kebebasan, musyawarah, dan keadilan," katanya. "Tetapi Islam menolak kebebasan absolut yang membolehkan apa yang diharamkan Allah."
Di Indonesia, KH. Hasyim Asy'ari juga pernah menegaskan bahwa umat Islam boleh mengambil sistem modern sepanjang tidak merusak akidah dan akhlak.
Pemikir politik Islam Indonesia, Mohammad Natsir, menolak demokrasi liberal karena dianggap mengeluarkan agama dari ruang publik. Sebagai gantinya, ia menawarkan konsep "theistic democracy" atau demokrasi bertuhan. "Demokrasi harus bertolak dari pengakuan akan kedaulatan Tuhan," ujarnya. "Kedaulatan rakyat berada dalam batas-batas hukum moral ilahiah."
Bagi Natsir, demokrasi tak cukup hanya mengandalkan suara terbanyak. Ia harus berjalan di bawah bimbingan nilai wahyu. Demokrasi yang sepenuhnya sekuler, menurutnya, akan melahirkan relativisme moral yang berbahaya bagi bangsa beragama seperti Indonesia. Gagasan Natsir ini sejalan dengan demokrasi Pancasila yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fondasi moral.
Di Pakistan, pemikir besar Abul A'la Al-Maududi memperkenalkan konsep "theodemocracy" atau teodemokrasi. Baginya, pemerintahan Islam adalah perpaduan antara prinsip demokrasi seperti musyawarah dan partisipasi rakyat dengan prinsip ketuhanan berupa supremasi hukum Allah. "Kedaulatan mutlak hanyalah milik Allah," tegas Maududi. "Manusia diberi wewenang untuk mengatur urusan publik selama tidak melanggar batas-batas syariat."
Konsep teodemokrasi ini menjadi sintesis menarik: rakyat tetap berpartisipasi, tapi nilai ilahi menjadi kompasnya. Gagasan Maududi banyak menginspirasi pemikir Muslim, termasuk di Indonesia.
Jadi, demokrasi Indonesia tak boleh menjadi demokrasi liberal yang bebas nilai. Kita butuh demokrasi yang beretika, bermoral, dan berakar pada budaya serta keyakinan masyarakat. Konsep theistic democracy ala Natsir dan theodemocracy ala Maududi memberikan landasan filosofis yang kuat: demokrasi harus bertuhan, bukan bebas tanpa batas.
Secara historis, istilah "demokrasi" sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno: "dêmos" (rakyat) dan "kratos" (kekuasaan). Artinya kurang lebih "kekuasaan rakyat". Contoh paling awal biasanya merujuk ke Athena sekitar abad ke-5 SM, di mana warga pria dalam lingkup terbatas punya hak bertemu dalam majelis dan memilih wakil atau mendiskusikan kebijakan secara langsung.
Demokrasi modern berkembang pesat setelah Abad Pencerahan di abad ke-18. Gagasan tentang rakyat, kebebasan, dan kesetaraan mulai menjadi wacana umum. Revolusi seperti Revolusi Prancis tahun 1789 dan perkembangan negara-nasional di abad ke-19 dan 20 memperluas hak suara dan memperkuat institusi representatif.
Setelah Perang Dunia II, proses dekolonisasi dan gelombang demokratisasi termasuk di Asia, Afrika, dan Amerika Latin memperbanyak negara yang mengadopsi sistem demokrasi atau elemen-elemen demokrasi.
Pada akhirnya, kita harus mengarahkan demokrasi kita pada theistic democracy demokrasi yang didasari nilai-nilai Ketuhanan. Nilai-nilai Islam sebagai mayoritas di bangsa ini harus menjadi panduan. Jangan sampai demokrasi terjerumus ke arah liberal yang menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan.
Kenyataan pahitnya, kita sering menyaksikan demokrasi tanpa nilai dalam setiap pemilu. Pembagian uang ke konstituen di mana-mana, bagi-bagi sembako, pengerahan aparat untuk mendukung calon tertentu, plus praktik suap menyuap. Selama demokrasi tak dilandasi nilai, maka yang terpilih hanyalah pemimpin semu. Pemimpin palsu. Pemimpin yang kurang peduli rakyat, tapi lebih mementingkan keluarga dan partainya. Semoga ke depan ada perubahan. Wallahu alimun hakim.
Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.

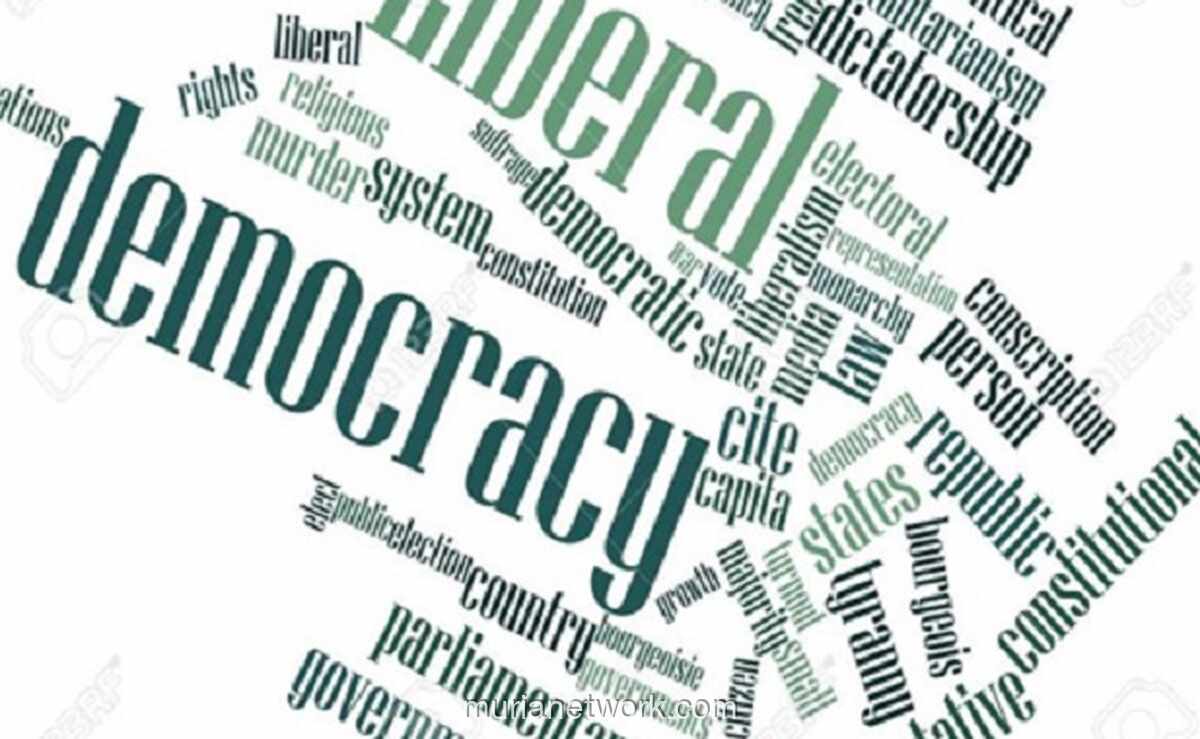









Artikel Terkait
BMKG Peringatkan Hujan Lebat Berpotensi Banjir dan Longsor di Sulsel
Kementan Pantau Pasokan dan Harga Daging-Telur Jelang Lebaran, Kondisi Umum Stabil
Air Terjun Kali Jodoh di Pinrang: Pesona Alam dan Mitos Pencarian Jodoh yang Ramai Dikunjungi
Tiga Buronan KKB Yahukimo Dibawa ke Jayapura untuk Proses Hukum