SURIPTO: JEJAK SEORANG YANG SELALU BERDIRI DI TITIK PALING SULIT
Oleh: Radhar Tribaskoro
Jejak Suripto tidak mudah ditemukan di halaman utama sejarah Indonesia. Namun langkahnya justru membentuk fondasi tersembunyi perjalanan republik ini. Ia muncul di momen-momen genting, ketika bangsa masih berjuang memahami jati dirinya, ketika keberanian lebih sering tampil sebagai kesunyian ketimbang sorak-sorai. Suripto memilih posisi-posisi tak populer, tepat di titik-titik tersulit, tempat satu keputusan dapat mengubah banyak nasib.
Dalam sejarah aktivisme Indonesia, Suripto adalah sebuah anomali. Bukan aktivis yang berteriak dari podium, ia justru hadir di tempat-tempat dimana risiko nyata bukan retorika sedang dipertaruhkan. Bukan politisi yang mencari sorotan, ia justru menguasai seni bekerja di lorong-lorong gelap kekuasaan. Bukan intelejen yang membanggakan misteri, ia paham betul bahwa republik kadang butuh penyelamat yang bekerja tanpa tepuk tangan.
Aktivis yang Tak Pernah Memutus Jarak dengan Nurani
Bagi generasinya, Suripto adalah aktivis yang acuh pada label. Baginya, aktivisme adalah tindakan nyata, bukan sekadar identitas. Ia membaca dinamika politik bukan sebagai panggung heroisme, melainkan pertarungan panjang menjaga kewarasan publik. Ia sadar, bangsa ini tak pernah kekurangan calon pahlawan, namun sering kehilangan orang yang rela bekerja dalam kesunyian.
Dalam sebuah percakapan, Suripto pernah mengutip kalimat bernas: "Di negeri ini, yang paling berbahaya bukanlah penguasa yang rakus, tetapi rakyat yang cepat puas." Dari ungkapan itu tergambar jelas posisinya bukan sebagai moralis yang menghakimi, melainkan penjaga kewaspadaan kolektif. Ia mengingatkan, demokrasi mudah rapuh di tangan generasi yang lelah berpikir.
Dalam diskusi-diskusi terbatas, ia sering menunjukkan ketidaknyamanannya pada gaya perlawanan yang sentimental. Ia yakin aktivisme harus memadukan pembacaan struktural dan keberanian moral. Tanpa struktur, kemarahan hanya jadi bara yang mudah padam. Tanpa moral, analisis struktural berubah jadi sinisme akademis belaka. Di ruang antara keduanya itulah Suripto menemukan panggungnya.
Politisi: Seni Mengambil Risiko untuk Kepentingan Publik
Ketika memasuki dunia politik, banyak yang meragukan ketajaman Suripto akan bertahan. Dunia politik dikenal sebagai arena kompromi dan kepentingan, tempat idealisme mudah tergerus. Namun Suripto justru membuktikan politik bisa menjadi alat koreksi, bukan sekadar panggung ambisi.
Ia tak pernah menjadi politisi yang nyaman. Kursi empuk tak pernah membuatnya lupa bahwa tugas utama politisi adalah membangun masa depan orang lain. Saat bersuara lantang, itu bukan karena emosi, melainkan penolakan untuk melihat republik terperosok di lubang yang sama.
Ciri pembeda Suripto dari politisi kebanyakan adalah kecemasan moral yang selalu dibawanya dalam setiap keputusan. Di tengah iklim politik yang makin pragmatis, kecemasan moral sering dianggap kelemahan. Bagi Suripto, justru itulah kekuatannya.
Pernyataan yang kerap ia ulang: "Politik tanpa kecemasan moral akan membuat pemimpin kehilangan rasa takut kepada kesalahan."
Itulah yang mendorongnya selalu berada di garda depan untuk menegur, mengingatkan, dan mengoreksi baik kepada kawan maupun lawan. Baginya, integritas bukan sekadar atribut pribadi, melainkan prasyarat agar negara tetap berdiri di fondasi yang kokoh.
Intelejen: Dari Ruang Gelap ke Ruang Terang
Sisi lain kehidupan Suripto adalah dunia intelejen. Banyak orang mengenalnya dari peran ini dunia sunyi penuh risiko, yang sering mengubur nama pelakunya dalam arsip-arsip tak terbaca. Tapi Suripto berbeda. Ia bukan intelejen yang memelihara ketakutan. Ia lebih mirip analis yang memetakan risiko politik dan keamanan negara, lalu mengartikulasikannya dengan ketenangan seorang ilmuwan.
Dunia intelejen memberinya perspektif unik yang jarang dimiliki aktivis atau politisi. Ia belajar tentang kerasnya realitas, tentang bagaimana negara bisa runtuh bukan karena musuh eksternal, melainkan kelalaian internal. Ia paham, ancaman terbesar sering berasal dari budaya politik yang kehilangan disiplin moral.
Yang membuat Suripto dihormati adalah konsistensinya menggunakan pengetahuan intelejen untuk kepentingan publik. Ia menolak menjadikan informasi sebagai senjata membungkam lawan politik. Ia memilih menggunakan informasi sebagai alat memperbaiki negara, bukan merusaknya demi kekuasaan.
Dalam percakapan pribadi, ia kerap berujar: "Informasi itu seperti pisau. Di tangan orang benar, ia memotong belenggu; di tangan orang salah, ia membunuh karakter." Prinsip itulah yang dipegangnya hingga akhir.
Integritas yang Bertahan di Tengah Kebisingan
Jika ada satu kata yang tepat menggambarkan Suripto, itu adalah keteguhan. Ia tak mudah goyah, tak terpesona kekuasaan, tak terseret arus. Ia bagai batu karang yang tidak memusuhi ombak, tapi juga tidak tunduk pada gelombang.
Banyak rekan kerjanya mengenang satu hal yang sama: Suripto tak pernah membiarkan persoalan politik menginjak-injak kemanusiaan. Ia tak pernah membiarkan perbedaan pandangan merusak persahabatan. Bahkan saat berseteru secara politik, ia tetap menjaga kemurnian niat. Ia tak pernah membenci orangnya; ia hanya menolak idenya.
Sikap itu semakin langka di zaman ketika perbedaan pandangan langsung berubah menjadi permusuhan pribadi, ketika argumen politik jadi alasan saling merendahkan, ketika ruang publik dipenuhi obsesi menang tanpa memedulikan kebenaran.
Suripto mengajarkan bahwa keberanian tak selalu tentang suara keras. Ia juga tentang keteguhan mempertahankan sudut pandang ketika seluruh dunia mendorong ke arah sebaliknya.
Jejak Seorang Guru Senyap
Bagi banyak generasi aktivis, Suripto adalah guru yang tak memaksa. Ia tidak mengajar dengan ceramah; ia mengajar dengan teladan. Ia tidak membesarkan murid; ia membesarkan keberanian. Ia tidak memberi instruksi; ia menunjukkan arah.
Banyak kisah kecil tentang Suripto yang tak pernah masuk pemberitaan, namun hidup dalam ingatan orang-orang yang disentuhnya. Kisah tentang caranya meredam konflik internal organisasi, caranya memberi nasihat tanpa pretensi, kemampuannya menenangkan ruangan panas hanya dengan satu kalimat jernih.
Dan ada satu kesan yang hampir semua orang bagikan: ia selalu hadir ketika dibutuhkan, namun tak pernah menuntut dihargai ketika tugas usai.
Warisan Nilai yang Tak Mudah Hilang
Mengenang Suripto hari ini bukan sekadar mengenang satu sosok. Ini tentang mengenang sebuah cara hidup. Cara memandang negara dengan rasa memiliki, bukan dendam. Cara memperjuangkan kebenaran tanpa ingin jadi pahlawan. Cara bekerja di titik-titik paling sepi, tempat yang tak dihuni tepuk tangan.
Kita hidup di masa ketika banyak hal bergerak cepat, namun arah sering kabur. Ketika teknologi melimpah, tapi kebijaksanaan menipis. Ketika politik makin keras, namun moral makin sunyi. Dalam situasi seperti ini, mengenang Suripto bukan nostalgia. Ini pengingat bahwa republik bertahan karena ada orang-orang yang rela berdiri di garis tak populer.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi tak bisa hidup tanpa orang berani bersikap. Bahwa politik tak bisa berjalan tanpa orang berani menegur. Bahwa negara tak bisa diselamatkan tanpa orang yang memelihara kecemasan moral.
Selamat Jalan, Suripto
Kini Suripto telah pergi. Tapi orang-orang sepertinya tak pernah benar-benar pergi. Mereka tetap hidup dalam nilai-nilai yang ditinggalkan, dalam keberanian yang ditunjukkan, dalam integritas yang dipertahankan hingga akhir.
Dalam tradisi Jawa ada ungkapan: "Urip iku urup." Hidup adalah nyala. Suripto adalah salah satu nyala itu nyala yang tak membakar, tapi menerangi; nyala yang tak berisik, tapi menunjukkan arah.
Di tengah hiruk-pikuk dunia yang makin gaduh, nyala itu mungkin tampak kecil. Justru karena kecil itulah ia menjadi penting. Pada akhirnya, sejarah suatu bangsa tak hanya dibuat oleh mereka yang duduk di panggung besar, melainkan juga oleh mereka yang tegak di tempat-tempat gelap dan sunyi.
Selamat jalan, Om Ripto. Engkau telah membuktikan bahwa keberanian tak selalu butuh panggung, dan bahwa integritas adalah satu-satunya warisan yang tak dapat dicuri waktu.
Cimahi, 17 November 2025


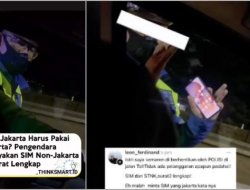



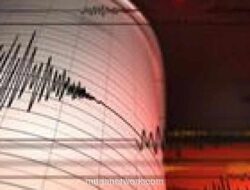




Artikel Terkait
Wakil Ketua BS OJK Soroti Kontradiksi Nilai Ramadhan dengan Korupsi Rp310 Triliun
Anggota Polri Meninggal dengan Luka Mencurigakan, Propam Polda Sulsel Lakukan Visum dan Pemeriksaan
Aktivis HAM Soroti Ironi Anggaran Negara Usai Tragedi Anak Meninggal karena Tak Mampu Beli Alat Tulis
AC Milan Tersungkur di San Siro, Kalah 0-1 dari Parma