Thailand paham betul: diplomasi budaya bukan cuma promosi nasional, tapi alat positioning ekonomi dalam rantai nilai global.
Pengalaman Korsel dan Thailand mengajarkan satu hal: monetisasi budaya butuh konsistensi kebijakan dan keberanian institusional.
Dari Kreativitas ke Kendali: Perebutan Nilai Tambah Budaya
Tak bisa dipungkiri, Indonesia punya modal besar. Keragaman budaya dan SDM kreatif kita melimpah. Berbagai upaya yang dilakukan Korsel dan Thailand, sebenarnya juga sedang kita coba.
Tapi, dari sudut pandang strukturalisme, kesuksesan mereka bukan cuma soal kreativitas. Ini tentang siapa yang menguasai rantai nilai budaya global. Mereka membangun lembaga pembiayaan, riset, distribusi, dan perjanjian dagang yang memastikan nilai tambah tidak bocor ke platform raksasa atau perusahaan asing.
Ketika negara mampu menciptakan struktur produksi budaya yang terintegrasi, ia tak cuma melindungi identitas, tapi juga menjaga nilai ekonominya tetap tinggal di dalam negeri.
Tantangan kita sekarang adalah menjahit berbagai inisiatif yang ada ke dalam satu kerangka nasional. Mulai dari tata kelola data budaya, pendanaan IP, hingga kebijakan ekspor konten digital.
Siapa yang kuasai data budaya dan IP, dialah yang akan kuasai nilai tambah global. Begitulah realitas era ekonomi digital.
Pengaruh Global: Dari Kekayaan Simbolik Ke Kekuatan Ekonomi
Hari ini, kekuatan suatu negara tak lagi hanya ditentukan sumber daya alam atau teknologi keras. Kemampuan menjual narasi dan identitas jadi sama pentingnya.
Korsel memanfaatkan K-pop dan K-drama yang sarat simbol budaya untuk membuka pasar elektronik, pariwisata, hingga gaya hidup. Thailand menjadikan Thai design dan kulinernya sebagai diplomasi gaya hidup yang memperkuat ekspor dan pariwisata.
Mereka berhasil mengubah soft power menjadi export power menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan membangun kepercayaan global.
Di satu sisi, logika liberalisme membuka peluang besar bagi Indonesia. Pasar global untuk konten budaya terus tumbuh, konsumsi lintas negara meningkat, dan digitalisasi memberi jalan bagi narasi lokal untuk bersaing secara setara.
Tapi di sisi lain, perspektif strukturalisme mengingatkan: tanpa kendali atas data, platform, pendanaan, dan distribusi, nilai tambah dari budaya digital akan tetap dikuasai pemain besar entah platform global atau negara yang lebih siap secara institusional.
Tantangan Indonesia adalah merangkai kedua logika ini. Memanfaatkan keterbukaan pasar global sekaligus membangun struktur ekonomi budaya yang membuat nilai strategisnya tetap tinggal di dalam negeri.
Digitalisasi budaya memang langkah awal yang penting. Tapi untuk menjadikannya mesin ekonomi, kita butuh tata kelola yang selaras dengan visi politik dan didukung keberanian institusional.
Pada akhirnya, masa depan budaya Indonesia tak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita digitalkan. Tapi seberapa jauh kita mampu mengubahnya menjadi nilai strategis. Sebab, data budaya bukan sekadar arsip. Ia adalah aset ekonomi dan diplomasi yang menentukan posisi bangsa di peta dunia.
Soft power yang dikelola dengan visi ekonomi bisa menjadi export power baru Indonesia mendorong kreativitas, menciptakan pekerjaan, dan meneguhkan jati diri di tengah persaingan global yang tak lagi ditentukan manufaktur semata, melainkan oleh narasi dan budaya.




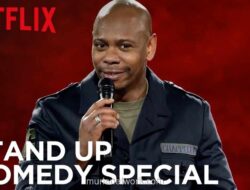






Artikel Terkait
BNI Siapkan Likuiditas Rp24 Triliun untuk Antisipasi Kebutuhan Lebaran 2026
Sekretaris Kabinet Tegaskan Makan Bergizi Gratis Tak Kurangi Anggaran Pendidikan Lain
Kemnaker Buka Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional 2026 untuk 70 Ribu Lulusan Baru
Gubernur DKI Gratiskan Transportasi Umum Saat Lebaran 2026