Sejarah kertas ternyata punya cerita yang panjang. Meski jejak arkeologis menunjukkan keberadaannya sejak abad kedua sebelum masehi, sosok yang kerap disebut sebagai penemunya adalah Cai Lun. Dia adalah seorang pejabat di masa Dinasti Han Timur, yang secara resmi mengumumkan penemuan ini di Lei-Yang, Tiongkok, tepatnya pada tahun 105 masehi.
Rahasia pembuatan kertas dijaga ketat oleh bangsa Tiongkok. Butuh waktu berabad-abad lamanya sebelum teknologi ini akhirnya merembet ke Jepang, lalu ke Timur Tengah, dan akhirnya sampai ke Eropa. Baru pada abad ke-8, pabrik kertas pertama di benua Eropa berdiri di Spanyol.
Perlahan, produksi kertas mulai meluas. Inggris, misalnya, baru memulai produksi besar-besaran di akhir abad ke-15. Sementara di Amerika Serikat, pabrik pertamanya baru didirikan di Pennsylvania pada tahun 1890. Sebelum kertas ditemukan, bayangkan betapa repotnya. Karya sastra, catatan filsafat, hingga tulisan akademik harus ditorehkan di media yang ada: kulit binatang, batang pohon, batu, bahkan daun lontar yang digunakan untuk naskah-naskah Melayu kuno.
Evolusi Pembelajaran
Keterbatasan media tulis itu sama sekali tidak mematahkan semangat para pencari ilmu zaman dulu. Mereka punya cara lain: kekuatan penuturan lisan. Itulah mengapa pertemuan langsung antara guru dan murid menjadi satu-satunya jalan untuk menimba ilmu.
Lihat saja para filsuf Yunani abad ke-6 SM, seperti Thales atau Anaximander. Mereka rela menempuh perjalanan ribuan kilometer, menghabiskan ratusan hari, hanya untuk belajar langsung pada para bijak di pusat peradaban seperti Babilonia atau Mesir. Perjalanan seperti itu jelas butuh tekad baja, fisik kuat, dan bekal yang cukup. Makanya, wajar jika seorang guru hanya punya segelintir murid. Ilmu diajarkan hanya pada orang-orang pilihan.
Memasuki abad ke-8 dan seterusnya, hingga awal tahun 2000-an, budaya mencatat mulai berkembang pesat. Ini sejalan dengan penemuan kertas, tinta, dan mesin cetak. Di era ini, seorang pembelajar mengandalkan kekuatan membaca, menghafal, menulis, dan menganalisis.
Kita mengenal Imam Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam, yang konon hafal 300.000 hadits beserta sanad dan matannya. Bahkan ada yang menyebut angka 500.000. Karya monumentalnya, Ihya Ulumuddin, dalam versi aslinya terdiri dari 12 jilid tebal. Ini menunjukkan kemampuan baca-tulis yang luar biasa.
Tradisi serupa terjadi hampir pada semua ilmuwan besar, baik di Timur maupun Barat. Di era itu, menjadi pintar berarti memiliki kekuatan untuk meneliti karya-karya besar berjilid-jilid, lalu menganalisis dan menuliskannya kembali. Ilmu ada di dalam kepala, bukan sekadar di buku. Seperti pepatah pesantren, 'al-'ilmu fish-shudur laisa fish-thurur'. Imam Ali RA juga pernah berpesan, 'ikatlah ilmu dengan tulisan'.
Saya masih ingat, tahun 1986 saat saya kuliah tingkat satu. Seorang dosen fisika mengajar tanpa membawa buku sama sekali. Dengan kapur di tangan, ia menuliskan penjelasannya di papan tulis secara rapi dan sistematis. Tugas kamilah, para mahasiswa, untuk menyalinnya dengan teliti. Saat itu, guru adalah sumber ilmu utama. Murid yang pintar adalah yang rajin membaca dan menulis.
Semuanya berubah di awal tahun 2000-an. Revolusi teknologi informasi meledak. Internet mulai masuk kampus, dunia terhubung, dan informasi terkumpul di dunia maya. Mesin pencari seperti Yahoo dan Google menjadi gerbang ilmu baru. Jurnal ilmiah dan textbook dalam bentuk e-book bisa diakses dengan lebih mudah, kadang meski harus 'dibobol' dulu.
Hirarki pengetahuan pun berubah. Dosen dan mahasiswa bisa 'balapan' mencari informasi. Siapa yang jago memasukkan kata kunci di mesin pencari, dialah yang lebih dulu dapat ilmu. Kemampuan membaca tetap penting, tapi sekarang untuk menelusuri dan menyaring lautan informasi yang tersedia.
Kini, kita menghadapi babak baru: era kecerdasan buatan atau AI. Mesin ini bisa menyimpan dan memproses jutaan data, menjawab pertanyaan rumit dalam hitungan detik. Lebih dari itu, AI bisa menuliskan puisi, menyusun artikel ilmiah, hingga membuatkan pidato. Modal utamanya cuma satu: kejelasan prompt.
Maka, skill yang dibutuhkan seorang pembelajar di era ini bergeser. Bukan lagi sekadar pandai membaca, tapi pandai bertanya dan merangkai perintah untuk AI. Kalau dulu banyak pelatihan menulis, sekarang marak pelatihan membuat prompt.

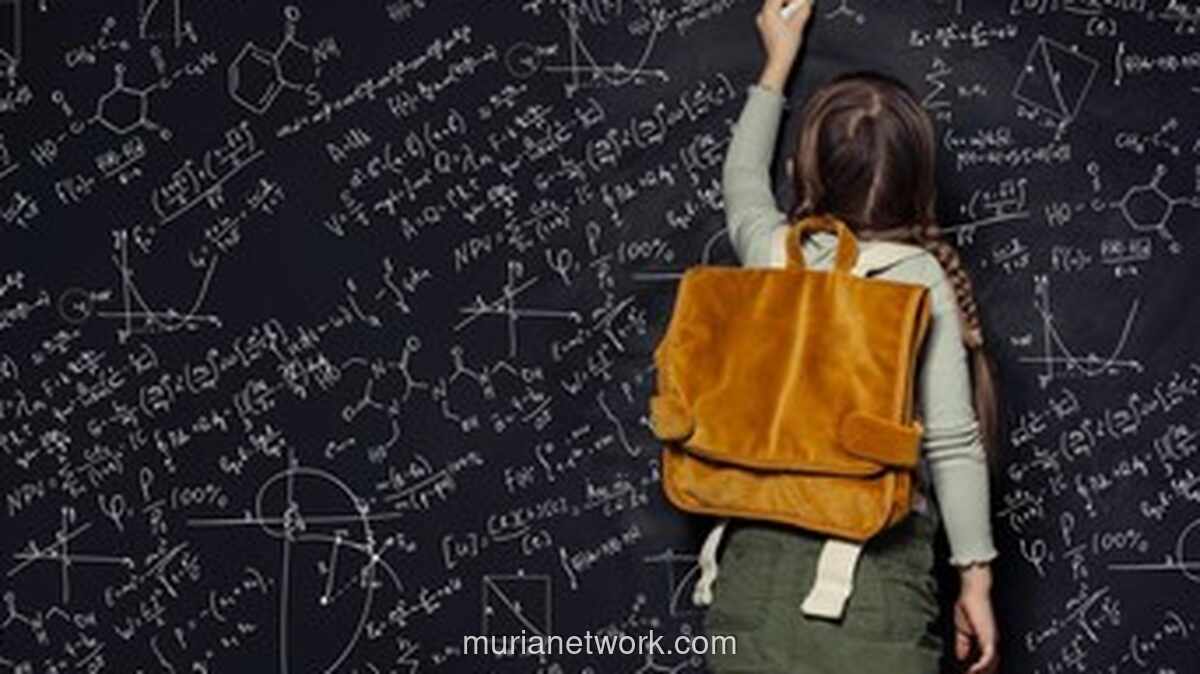









Artikel Terkait
Tangis Keluarga Pecah di Posko RSUP Kariadi Usai Dengar Nasib Lima Kerabat Korban Bus
Peternak Sapi Galang Rp 800 Juta untuk Korban Bencana Sumatera
PKS Anggap Wacana Pilkada Lewat DPRD Perlu Kajian, Sorotan Justru ke Bencana Sumatera
38 Bangunan Liar di Akses UI Dibongkar, Trotoar dan Saluran Air Dikembalikan