Ketika bencana berlalu, yang tersisa seringkali adalah kerentanan. Bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas mereka inilah yang paling merasakan dampaknya. Akses terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan bisa tiba-tiba hilang, meninggalkan mereka dalam situasi yang sangat sulit.
Merespon kondisi itu, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) memutuskan untuk bertindak. Mereka membangun sebuah Dapur PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) di Pantee Lhong, Kabupaten Bireuen, Aceh. Ini bukan sekadar proyek fisik, tapi upaya konkret untuk menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
“Dalam situasi bencana maupun pascabencana, kelompok rentan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak, namun justru paling mudah terabaikan,” ujar Achmad Syafiuddin, Ketua LPPM Unusa, Sabtu (27/12).
“Melalui pembangunan Dapur PMBA ini, Unusa ingin memastikan bahwa hak dasar mereka, khususnya terkait pemenuhan gizi dan kesehatan, tetap terpenuhi secara layak dan bermartabat.”
Program ini adalah bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat, digarap bareng Dinas Kesehatan Bireuen. Fokusnya jelas: memperkuat layanan kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi, dan memastikan sanitasi yang layak untuk kelompok rentan, terutama di masa darurat.
Dana pendukungnya datang dari DPPM, Dirjen Risbang, Kemdiktisaintek, berdasarkan surat pengumuman bernomor 1737/C3/AL.04/2025. Dukungan ini menunjukkan kepercayaan pemerintah pada peran kampus dalam menjawab persoalan nyata di masyarakat.
Namun begitu, Achmad Syafiuddin menegaskan bahwa pendekatannya tak berhenti di bangunan. “Kami tidak berhenti pada pembangunan sarana fisik,” jelasnya.
“Tim Unusa juga melakukan edukasi kesehatan dan gizi, pendampingan praktik pemberian makanan bayi dan anak yang benar, serta penguatan peran masyarakat lokal agar mampu mengelola dan melanjutkan program ini secara mandiri.”
Kolaborasi dengan pemda dan warga setempat disebutnya sebagai kunci. Dengan melibatkan banyak pihak, dapur ini diharapkan tak hanya hidup saat bencana, tapi juga berfungsi di masa normal sebagai pusat layanan gizi komunitas.
Ia menggambarkan betapa kelompok rentan seringkali terpinggirkan saat krisis. Keterbatasan mobilitas dan kebutuhan khusus membuat mereka sulit dapat bantuan dengan cepat. Bahkan, kadang mereka luput dari proses evakuasi.
Di sisi lain, Dapur PMBA ini dirancang sebagai ruang aman yang lebih dari sekadar tempat masak. Ia menjadi titik temu untuk interaksi, edukasi, dan pemulihan baik fisik maupun psikologis terutama bagi ibu dan anak.
Sebagai Ketua Center for Environmental Health of Pesantren (CEHP) Unusa, Syafiuddin melihat program ini sebagai penegasan peran strategis kampus. Dengan memadukan keilmuan, riset, dan pengabdian, Unusa berkomitmen mendorong terwujudnya ketahanan kesehatan yang adil.
Ke depan, ia berharap model di Bireuen ini bisa ditiru di daerah lain yang rawan bencana.
“Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat, upaya perlindungan kelompok rentan diharapkan dapat berjalan lebih sistematis, berkelanjutan, dan berdampak luas,” pungkasnya.
Pada akhirnya, dapur sederhana di Aceh itu bicara tentang hal yang lebih besar: bahwa pemulihan pascabencana harus dimulai dari mereka yang paling lemah. Itulah intinya.








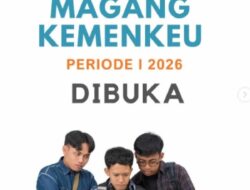


Artikel Terkait
Dua Pilot Tewas Ditembak KKB Usai Pesawat Mendarat di Bandara Korowai
Menkes Tegaskan Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien PBI JK Nonaktif
Pandji Pragiwaksono Tuntaskan Kasus Adat di Toraja dengan Denda Babi dan Ayam
Pemerintah Kembangkan Dashboard Kebijakan untuk Tingkatkan Transparansi di Era Digital